Dewa Arak - Keris Peminum Darah
SATU
Hari sudah agak siang. Sinar sang surya begitu terik, menyengat kulit. Namun semua itu tidak dipedulikan oleh dua sosok tubuh yang melangkah bergegas memasuki hutan. Dua sosok yang ternyata dua orang lelaki itu melangkah gesit, dan bersikap penuh tanggap. Jelas kalau mereka tidak asing lagi dengan ilmu silat.
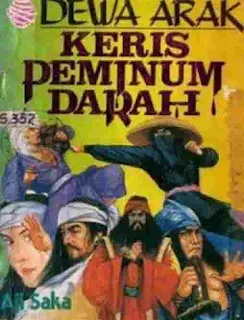
Orang yang dipanggil Rakapitu segera mengedarkan pandangan ke sekeliling. Dia adalah seorang laki-laki bertubuh tinggi besar, kekar dan berotot.
Tapi, kepalanya kecil, sehingga kelihatan lucu sekali. "Rasanya tidak jauh lagi, Gibang," sahut Rakapitu. Tapi, nada suaranya terdengar mengambang. Jelas kalau dia merasa bimbang akan jawabannya sendiri.
"Heh...?! Jadi kau sendiri tidak tahu tempatnya, Rakapitu?" Gibang terperanjat dengan dahi berkerut dalam.
"Tentu saja tahu!" sergah Rakapitu keras seraya menatap tajam wajah rekannya.
"Hm... Lalu..., mengapa sekarang kau kelihatan bingung?"
secercah senyum mengejek tersungging di bibir Gibang. "Siapa yang bingung?!" semakin meninggi suara Rakapitu. Sikap laki-laki yang wajahnya penuh tahi lalat itu menyebabkan amarahnya bangkit. "Aku tengah mencari patokannya. Apa kau sudah melihat pohon beringin yang batangnya sedikit terkelupas?"
Sambil berkata demikian, kepala laki-laki tinggi besar ini menoleh ke kanan dan ke kiri. Gibang pun mau tak mau ikut mengedarkan pandangannya, mencari-cari pohon beringin seperti yang dikatakan rekannya.
"Itu dia...!" teriak Rakapitu gembira, seraya mengarahkan telunjuk kanannya pada sebatang pohon beringin.
Gibang mengikuti arah tudingan itu. Memang benar apa yang dikatakan Rakapitu. Batang pohon beringin itu terkelupas. Seketika itu juga, Rakapitu mempercepat langkahnya. Mau tak mau, Gibang pun melakukan hal yang sama jika tidak ingin tertinggal. Dari pohon beringin itu Rakapitu menuju ke kiri. Dia berjalan menerobos kerimbunan semak dan pepohonan yang lebat.
"Itu tempatnya, Gibang," tunjuk Rakapitu seraya menudingkan telunjuk kanannya ke arah sebuah gua yang terletak tak jauh di depan mereka.
"Hm...," hanya gumam pelan dan tak jelas yang keluar dari mulut Gibang untuk menyambuti ucapan rekannya.
Begitu telah menemukan apa yang dicari, kedua laki-laki ini kian mempercepat langkah. Jelas sudah, tujuan mereka adalah ke gua itu. Tapi, ketika jarak antara mereka dengan mulut gua tinggal sekitar tiga tombak lagi, terdengar suara gerengan. Perlahan saja suara itu, tapi akibatnya telah membuat wajah Rakapitu dan Gibang memucat. Langkah kaki mereka kontan terhenti. Tanpa melihat pun, mereka telah tahu kalau suara gerengan itu tak lain berasal dari seekor harimau.
Sebenarnya baik Rakapitu maupun Gibang sama sekali tidak merasa gentar terhadap harimau. Tapi binatang yang terdapat di gua ini tidak bisa dianggap sembarangan. Binatang itu adalah seekor macan putih ajaib, yang kebal terhadap segala macam senjata. Bahkan juga memiliki kekuatan yang menggiriskan. (Untuk jelasnya, baca serial Dewa Arak dalam episode Prahara Hutan Bandan).
Belum lagi gema gerengan itu lenyap, dari dalam gua keluar seekor macan yang berbulu putih dengan langkah tenang. Besarnya mungkin satu setengah kali macan biasa yang paling besar.
"Grrrh...!" Kembali macan putih itu menggereng. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Sepasang matanya yang bersinar kehijauan menatap tajam wajah kedua tamu tak diundang itu. Mulutnya terbuka memamerkan deretan gigi-gigi yang panjang dan runcing.
Karuan saja hal itu membuat Rakapitu dan Gibang jadi semakin ketakutan. Dengan tubuh gemetar kedua orang itu beringsut melangkah ke belakang. Tapi ternyata macan putih itu tidak bermaksud jahat. Terbukti begitu melihat Rakapitu dan Gibang undur, binatang itu pun tidak mengejar. Macan putih itu hanya menggereng pelan, kemudian membaringkan tubuhnya di depan gua. Tapi wajahnya tetap tertuju pada Rakapitu dan Gibang.
Melihat macan itu tidak mengejar, rasa takut Rakapitu dan Gibang mulai mereda. Kedua orang ini tidak lagi melangkah mundur, tapi diam di tempat. Beberapa saat lamanya, kedua laki-laki ini berdiam diri. Maju tidak, mundur pun tidak.
"Bagaimana, Gibang?" tanya Rakapitu meminta pendapat rekannya.
"Sudah kepalang basah, Kang. Mandi saja sekalian," sahut laki-laki berwajah penuh tahi lalat itu. Nada suaranya terdengar tegas. Meskipun lebih mirip bisikan.
"Bagaimana dengan macan itu?" Rakapitu menunjuk macan putih dengan dagunya.
Gibang terdiam sejenak. Sesaat lamanya matanya menatap macan putih yang terbaring di depan gua. Wajah binatang itu tetap tertuju pada mereka. Tapi tidak ada tanda-tanda kalau akan melakukan sesuatu. Bahkan sepertinya macan putih itu tengah bersenang hati. Terbukti, ekornya mengibas ke sana kemari.
"Tampaknya binatang itu tidak buas, Rakapitu."
"Dugaanmu mungkin benar, Gibang," sahut laki-laki bertubuh tinggi besar itu mendukung penilaian rekannya.
"Kalau begitu, tunggu apa lagi?" desak Gibang dengan suara pelan. "Kita coba saja masuk ke dalam."
"Bagaimana kalau macan itu menyerang?" Rakapitu masih ragu-ragu.
"Kita usahakan agar binatang itu jangan sampai merasa terganggu."
"Aku mengerti," kata Rakapitu. "Tapi bagaimana caranya?"
"Kita melangkah perlahan-lahan," usul Gibang.
"Kalau begitu, kau bergerak dulu. Aku rnengikuti dari belakang," tambah Rakapitu yang masih khawatir kalau macan putih itu akan menyerang.
"Hhh...!" Gibang menghela napas berat, mencoba menenangkan debaran jantungnya yang kembali berdetak cepat, begitu memutuskan untuk nekat menerobos masuk ke dalam gua. Perlahan dan hati-hati sekali Gibang melangkahkan kaki. Tapi baru juga melangkah setindak, ekor macan itu berhenti mengibas. Tampak jelas kalau binatang itu mulai curiga. Tentu saja Gibang melihat hal ini, tapi berpura-pura tidak melihat. Kembali kakinya dilangkahkan. Sementara Rakapitu mulai melangkah maju pula.
"Grrrh...!" Macan putih menggereng pelan sambil menggerak-gerakkan misainya.
Melihat hal ini, Gibang semakin gugup. Jelas kalau macan putih itu telah menunjukkan tanda-tanda mengkhawatirkan bagi diri dan rekannya. Tapi Gibang sudah nekat. Kembali kakinya melangkah. Rakapitu pun terpaksa melangkahkan kakinya pula. Tapi kali ini langkah kedua orang ini tidak setenang semula, dan tampak mulai oleng. Yang pasti, kedua lelaki ini dilanda perasaan tegang.
Mendadak macan putih itu bangkit dari berbaringnya seraya terus menggereng. Gerengannya kali ini lebih keras dari sebelumnya, pertanda kalau mulai marah. Kontan wajah Rakapitu dan Gibang memucat. Langkah mereka pun terhenti, tapi terlambat. Macan itu rupanya sudah merasa terganggu dan marah pada kedua laki-laki itu. Sambil mengaum menggetarkan dada, macan putih itu melompat menerkam Gibang dan Rakapitu. Maka kedua orang ini terkejut bukan main.
"Awas, Rakapitu...!" seru Gibang seraya melempar tubuh ke samping kanan. Dan begitu kedua tangannya menyentuh tanah, tubuhnya segera bergulingan menjauh.
Rakapitu tentu saja tidak mau mati konyol. Laki-laki tinggi besar ini melempar tubuh ke samping untuk menyelamatkan selembar nyawanya. Hanya bedanya, kalau Gibang melompat ke kanan, dia melompat ke kiri. Dan berbareng dengan bangkitnya Gibang, Rakapitu juga bangkit dari bergulingannya.
"Grrrh...!" Kembali macan putih ini menggereng begitu melihat calon korbannya berhasil meloloskan diri dari terkaman. Dan begitu mendarat di tanah, binatang itu kebingungan melihat mangsanya berpencar. Tapi sesaat kemudian macan putih telah kembali menyerang. Kini Gibanglah yang menjadi sasarannya.
Gibang menggertakkan gigi, bersiap-siap menghadapi serangan macan itu. Di tangan kanannya tampak tergenggam sebatang golok besar. Maka begitu melihat binatang itu menerkam, segera dipapak dengan ayunan goloknya.
Bukkk...!
Telak dan keras sekali golok Gibang menghantam bahu macan putih itu. Tapi akibatnya, tubuh laki-laki berwajah penuh tahi lalat ini malah terjengkang ke belakang dan jatuh di tanah. Ini terjadi, karena dia terbawa dorongan tenaga terkaman macan putih itu. Sementara binatang itu sama sekali tidak merasakan apa-apa. Jangankan terluka, merasa sakit pun tidak. Sebaliknya, justru Gibang yang merasa tangannya seperti lumpuh. Goloknya seperti berbenturan dengan sebuah benda yang amat kenyal, dan tanpa dapat ditahan lagi terlepas dari pegangan.
"Auuummm...!" Sambil mengeluarkan auman menggelegar, macan putih itu kembali menerkam. Padahal saat itu tubuh Gibang tengah tergolek di tanah. Rasanya, untuk bangkit berdiri atau melompat tidak ada waktu lagi. Maka tubuhnya segera bergulingan untuk menyelamatkan selembar nyawanya. Untuk yang kesekian kalinya, Gibang lolos dari maut. Dan sebelum macan putih itu terus memburu, bantuan dari rekannya tiba. Rakapitu langsung membabatkan goloknya pada punggung binatang itu.
Bukkk...!
Seperti yang dialami Gibang, Rakapitu pun merasa babatannya seakan-akan menghantam sebuah benda kenyal. Akibatnya, tenaga serangannya berbalik, dan tangannya terasa lumpuh. Hanya saja, sebelum senjata itu terlepas dari pegangan, dia masih mampu mencekalnya.
Macan putih membalikkan tubuhnya menghadap Rakapitu. Binatang ini marah bukan main mengetahui tindakannya dihalangi. Maka serangannya kini dialihkan pada laki-laki tinggi besar itu. Macan putih itu mengayunkan kaki kanan depannya, menyampok ke arah pelipis Rakapitu. Laki-laki tinggi besar itu menggertakkan gigi. Seluruh kekuatan tenaga dalam yang dimilikinya dikerahkan untuk memapak sampokan macan putih itu dengan goloknya. Dia bermaksud membuat kaki binatang itu buntung.
Takkk...!
Terdengar suara keras seperti bunyi logam beradu. Rakapitu begitu terperanjat, menyadari kalau sampokan macan itu ternyata kuat bukan main. Seketika tangan kanannya terasa sakit-sakit. Bahkan lumpuh sejenak. Dan kini tak pelak lagi goloknya terlempar jauh. Rakapitu tahu kalau dirinya kini terancam.
Maka tanpa membuang-buang waktu lagi, segera tubuhnya dilempar ke samping dan bergulingan menjauh. Tapi macan putih itu rupanya tak mau membiarkan mangsanya lolos. Langsung dikejarnya tubuh yang tengah berguling-guling itu. Tapi sebelum macan itu kembali menerkam, terdengar seruan mencegah.
"Putih...! Tahan...!"
Pelan saja suara bernada perintah itu. Meskipun begitu, pengaruh yang ditimbulkannya begitu luar biasa. Macan putih itu langsung menghentikan gerakannya begitu mendengar cegahan, lalu menoleh sebentar. Binatang itu menggereng pelan, kemudian melangkah menghampiri si pemilik suara.
"Hhh...!"
Hampir berbareng Rakapitu dan Gibang menghela napas lega. Keduanya sadar, kalau pertarungan dilanjutkan, pasti akan tewas di tangan macan putih yang kebal itu. Dengan pandangan penuh rasa syukur, kedua lelaki ini mengalihkan pandangan ke arah asal seruan itu.
Di depan gua, tampak berdiri seorang kakek berpakaian kuning. Rambut, alis, kumis, dan jenggotnya telah memutih semua. Tubuhnya agak bungkuk dan kaki kirinya buntung sampai pangkal paha. Di tangan kiri kakek ini tergenggam sebatang tongkat butut untuk menyangga tubuhnya.
Rakapitu dan Gibang mengerutkan alisnya, lalu melangkah menghampiri kakek itu. Macan putih yang kini telah berada di sebelah kakek bertubuh bungkuk itu menggereng pelan, penuh kemarahan.
"Tenanglah, Putih," ujar kakek berpakaian kuning menenangkan. Tangan kanannya mengelus-elus kepala binatang itu.
Seketika itu juga, macan putih itu berhenti menggereng. Tampak jelas kalau binatang ini amat patuh pada kakek bertubuh bungkuk dan berpakaian kuning itu. Hal ini tidak aneh, karena binatang itu memang peliharaannya. Kini macan putih itu hanya menatap penuh curiga pada Rakapitu dan Gibang yang tengah melangkah menghampiri majikannya.
"Siapa kalian? Dan mengapa mengganggu binatang peliharaanku?" tanya kakek berpakaian kuning begitu Rakapitu dan Gibang menghentikan langkahnya. Sepasang mata kakek itu menatap tajam wajah Rakapitu dan Gibang secara bergantian. Jarak mereka terpisah sekitar tiga batang tombak.
"Aku Gibang, Kek," sahut laki-laki berwajah penuh tahi lalat mengenalkan diri. "Dan ini kawanku, Rakapitu." Sambil berkata demikian, Gibang menudingkan telunjuk pada rekannya. Rakapitu menganggukkan kepala sambil tersenyum.
"Hm...," kakek berpakaian kuning hanya bergumam pelan, tak jelas.
"Kami tidak menyerang peliharaan Kakek. Sebaliknya, binatang itulah yang menyerang kami," sambung Gibang memberi penjelasan.
"Tidak mungkin. Putih tidak pernah menyerang orang, terkecuali kalau diganggu lebih dulu," bantah kakek berpakaian kuning.
"Tapi, kami sama sekali tidak mengganggunya, Kek," sambut Gibang lagi, membela diri.
"Benar," sambung Rakapitu. "Kami berdua akan masuk ke dalam gua, dan ingin menemui penghuninya yang bernama Eyang Aji Ranta."
"Akulah orang yang kalian cari itu," kata kakek berpakaian kuning, pelan.
Rakapitu dan Gibang mengerutkan kening. Memang beberapa ciri Eyang Aji Ranta ini, mirip dengan orang yang mereka cari. Tapi, ada ciri yang amat penting yang tidak dimiliki kakek berpakaian kuning itu. Inilah yang membuat kedua laki-laki ini ragu.
"Jadi, kakek yang bernama Eyang Aji Ranta itu?" tanya Gibang masih kurang percaya.
Kakek berpakaian kuning itu menganggukkan kepala sambil tersenyum.
"Tapi setahu kami, sepasang mata Eyang Aji Ranta buta," Rakapitu ikut ambil bagian, mengutarakan keragu-raguannya. Sepasang matanya menatap ke arah mata kakek berpakaian kuning di depannya. Dan memang, sepasang mata kakek itu tidak buta. Gibang menganggukkan kepala pertanda membenarkan ucapan rekannya.
"Aku telah berhasil menyembuhkannya," jawab kakek yang ternyata bernama Eyang Aji Ranta, masih dengan senyum di bibir. Dan ternyata kakek ini juga suami dari Kuntilanak Alam Kubur (Untuk jelasnya, baca serial Dewa Arak dalam episode Prahara Hutan Bandan).
Rakapitu dan Gibang mengangguk-anggukkan kepala pertanda mengerti.
"Sekarang katakanlah, apa maksud kalian datang menemuiku?" tanya Eyang Aji Ranta. Sebagai bekas orang buta, perasaannya jauh lebih tajam dibanding orang lain. Maka, kakek berpakaian kuning ini sudah bisa merasa kalau kedua orang di hadapannya adalah orang baik-baik.
"Ada orang yang sangat membutuhkan bantuan Eyang," sahut Gibang. "Dia sakit parah. Karena mendengar kabar kalau Eyang ahli dalam pengobatan, maka kami lalu memaksakan diri menemui Eyang."
Eyang Aji Ranta terdiam. Memang, dia sering mengobati para penduduk sekitar Hutan Dadap. Maka mendengar permintaan Rakapitu dan Gibang, dia tidak merasa heran. "Di mana tempat tinggal kalian?" tanya Eyang Aji Ranta setelah beberapa saat lamanya termenung.
"Desa Pucung, Eyang," jawab Gibang cepat.
"Desa Pucung...," ulang kakek berpakaian kuning.
"Bagaimana, Eyang?" tanya Gibang penuh harap. "Eyang bersedia?"
Eyang Aji Ranta menganggukkan kepala.
"Terima kasih atas kebaikan hati Eyang Aji Ranta," ucap Rakapitu dan Gibang berbarengan begitu melihat gerak kepala Eyang Aji Ranta. Wajah kedua orang itu nampak berseri-seri.
"Sudahlah. Aku paling tidak suka banyak peradatan," sergah Eyang Aji Ranta penuh teguran.
"Maafkan kami, Eyang," ucap Gibang buru-buru. "Kami terlalu gembira karena Eyang bersedia meluluskan permintaan kami, sehingga tidak bisa menahan luapan perasaan."
Eyang Aji Ranta tidak menyahut. "Putih. Aku akan pergi sebentar. Jaga tempat ini baik-baik," ujar kakek berpakaian kuning pada binatang peliharaannya.
"Grrrh...!" Macan putih menggereng pelan sebagai jawabannya.
"Mari kita berangkat," ajak Eyang Aji Ranta sambil melangkah mendahului meninggalkan tempat itu. Kelihatannya Eyang Aji Ranta hanya melangkah perlahan saja. Tapi hebatnya, dia sudah berada dalam jarak sepuluh tombak dari tempat semula.
Karuan saja hal ini membuat Rakapitu dan Gibang terkejut bukan kepalang. Jelas terbukti kalau Eyang Aji Ranta adalah orang sakti. Tapi mereka tidak bisa berlama-lama tenggelam dalam keterkejutan, karena Eyang Aji Ranta telah berjalan cukup jauh. Kini buru-buru mereka berlari menyusul.
* * * * * * * *
Baru saja tubuh ketiga orang itu lenyap ditelan kejauhan, dari arah yang berlawanan bermunculan belasan orang berwajah kasar dari balik pepohonan. Di tangan mereka tampak tergenggam senjata terhunus. Rupanya kedatangan belasan orang itu diketahui macan putih, maka binatang itu langsung bangkit dari berbaringnya.
Memang sejak Eyang Aji Ranta pergi, macan putih segera membaringkan tubuhnya di depan gua. Dan binatang itu baru bangkit begitu mencium bau banyak orang yang berdatangan ke tempat ini. Macan putih menggereng keras, begitu melihat di depannya telah berkumpul belasan orang berwajah kasar sambil membawa senjata terhunus. Nalurinya langsung mengisyaratkan kalau belasan orang itu tidak bermaksud baik.
"Serbu...!" Salah seorang yang berikat kepala hitam langsung memberi aba-aba. Tangan kanannya yang menggenggam sebatang golok besar diangkat ke atas. Salah satu mata golok tampak bergerigi. Sepertinya dia adalah pemimpin gerombolan ini.
Tanpa menunggu perintah dua kali, belasan orang itu meluruk ke arah mulut gua. Dan karena macan putih berdiri menghadang di depan, mereka terpaksa harus merobohkannya terlebih dahulu. Suara berdesing nyaring, diiringi kilatan senjata-senjata yang ditimpa sinar matahari mengiringi tibanya serangan gerombolan itu.
"Auuummm...!" Sambil mengaum keras menggetarkan jantung, macan putih melompat memapak tibanya belasan senjata yang siap merajamnya. Tak pelak lagi, sekujur tubuh macan putih langsung disambut hujan bermacam-macam senjata tajam. Dan ternyata belasan penyerang itu harus menemui kenyataan pahit. Buktinya, senjata-senjata itu malah terpental balik sewaktu menghantam kulit binatang itu. Bahkan tubuh macan putih itu terus meluncur tanpa bisa ditahan lagi.
Jerit kematian pun terdengar seketika, saat seorang dari mereka diterkam macan putih. Tanpa ampun lagi, gigi-gigi runcing binatang itu menghunjam leher orang malang itu. Sementara kedua kaki depannya, mencengkeram kedua bahunya. Berbareng dengan robohnya tubuh itu di tanah, nyawanya pun melayang meninggalkan raganya.
Kematian salah seorang dari mereka, membuat belasan orang itu jadi murka. Segera tubuh macan putih itu dihujani dengan bacokan dan tusukan senjata. Lagi-lagi, tindakan gerombolan itu hanya membuang tenaga secara percuma saja. Kulit tubuh macan putih itu sama sekali tak mampu ditembus. Bahkan senjata-senjata mereka terpental balik.
Wuttt...! Prattt..!
Kembali seseorang yang berwajah pucat seperti orang penyakitan telah menjadi korban. Kaki kanan depan macan putih itu telah menyampok pelipisnya. Seketika tubuh laki-laki berwajah pucat itu terpelanting dan jatuh di tanah. Tanpa sempat berteriak lagi, orang itu tewas seketika. Tulang pelipisnya retak, terkena sampokan macan putih yang memang keras bukan main.
Macan putih itu terus mengamuk, menyebar maut pada lawan-lawannya. Beberapa saat kemudian, kembali jerit memilukan terdengar diiringi robohnya anggota gerombolan yang lain. Karuan saja hal ini membuat kemarahan pemimpin gerombolan itu bergolak. Sementara, macan putih itu sama sekali belum terluka. Sedangkan empat orang anak buahnya sudah pergi ke alam baka. Bukan tidak mungkin kalau dibiarkan terus, anak buahnya akan habis dibantai binatang buas itu.
"Mundur semua...!" teriak laki-laki berikat kepala hitam. Suaranya terdengar keras bukan main, karena disertai pengerahan tenaga dalam.
Tanpa diperintah dua kali, anggota gerombolan itu saling dahulu-mendahului bergerak mundur. Tapi, macan putih tidak mau membiarkan begitu saja. Binatang itu terus bergerak mengejar mereka. Kembali salah seorang anggota gerombolan menjadi korban, karena ditubruk macan putih dari belakang. Tak pelak lagi, tubuh laki-laki itu pun terjerembab ke depan. Sedangkan macan putih masih berada di atasnya.
Sebelum laki-laki berwajah bopeng itu bangkit, macan putih telah lebih dahulu menghunjamkan giginya di tengkuk. Suara jeritan menyayat terdengar ketika laki-laki berwajah bopeng itu meregang nyawa.
"Keparat..!" maki laki-laki berikat kepala hitam. Perasaan geram yang hebat tampak jelas baik pada wajah maupun suaranya. Seiring hilangnya gema makian itu, tangan kanannya bergerak ke arah pinggang. Sesaat kemudian, di tangan kanannya telah tergenggam seutas cambuk berwarna merah darah. Panjangnya, tak kurang dari satu setengah tombak.
Darrr...! Ledakan keras yang memekakkan telinga terdengar ketika laki-laki berikat kepala hitam ini melecutkan cambuknya.
"Auuummm...!" Sambil mengaum keras, macan putih melompat menerkam laki-laki berikat kepala hitam. Sedangkan yang akan diterkam malah mendengus, namun cepat mengelak. Gerakannya gesit juga, laksana kera dia menyelinap di bawah tubuh macan itu. Sesaat kemudian tubuhnya sudah berada di belakang macan putih, mendekati sebuah pohon besar. Secepat laki-laki berikat kepala hitam itu berada di sana, secepat itu pula cambuknya dilecutkan.
Darrr...! Rrrt..!
"Grrrh...!" Macan putih menggeram keras ketika kaki kiri belakangnya erat sekali terlilit cambuk, dan langsung terikat mati. Sebelum tubuh binatang itu menyentuh tanah, laki-laki berikat kepala hitam itu segera mengikatkan ujung cambuk yang dipegang ke sebatang pohon besar di dekatnya. Hal ini memang sudah direncanakan. Laki-laki berikat kepala hitam itu tersenyum puas setelah selesai mengikatkan ujung cambuknya ke batang pohon.
Sepasang matanya menatap penuh kepuasan pada macan putih yang meronta-ronta berusaha melepaskan diri, tapi tanpa hasil. Cambuk itu bukan cambuk sembarangan, karena terbuat dari bahan yang alot dan sulit diputuskan. Bahkan oleh senjata tajam sekali pun.
"Cari benda itu..!" perintah laki-laki berikat kepala hitam.
Anak buahnya yang tengah menatap penuh kagum, segera bergerak mengikuti perintah pemimpinnya. Sama sekali tidak disangka kalau macan putih yang menggiriskan itu, dapat dilumpuhkan oleh pemimpin mereka dalam segebrakan. Padahal, binatang itu kelihatan perkasa. Buktinya, beberapa nyawa telah melayang akibat terkamannya. Dan kini, binatang itu hanya dapat meronta-ronta, tanpa mampu melepaskan diri dari ikatan cambuk pada kakinya.
Dan memang, anggota gerombolan itu tidak bisa berlama-lama tenggelam dalam kekaguman. Apa lagi, mereka berlomba dengan waktu. Apabila Eyang Aji Ranta keburu kembali, mereka akan menghadapi kesulitan yang amat besar. Benda yang berada di dalam gua harus cepat diambil! Maka anggota gerombolan itu bergegas masuk ke dalam gua. Tak dihiraukan lagi macan putih yang meraung-raung murka melihat anggota gerombolan itu memasuki gua tempat tinggal majikannya.
* * * * * * * *
DUA
Begitu memasuki mulut gua, gerombolan yang kini berjumlah sembilan orang itu bergegas mengedarkan pandangan berkeliling, mencari-cari benda yang diperintahkan pemimpin mereka. Tapi suasana dalam gua yang hanya remang-remang, rupanya cukup menjadi penghalang juga. Besar kemungkinan kalau benda yang dicari tidak akan diketemukan.
Tapi ternyata anggota gerombolan itu sudah memperhitungkannya. Dan kini, tiga orang di antara mereka segera mengeluarkan tiga batang obor dari balik bajunya. Dan berkat tenaga dalam yang lumayan, tidak sulit untuk menyalakan api. Dua batang obor yang terbuat dari kayu nangka itu digosok-gosokkan, hingga menimbulkan percikan api.
Sementara sebatang obor lain didekatkan ke percikan api. Maka begitu ujung obor terkena percikannya api langsung membesar menjadi obor yang menyala. Kemudian, mereka menyulut dua obor berikutnya. Dan kini, suasana dalam gua itu telah terang-benderang oleh tiga batang obor. Dengan bantuan cahaya obor, sembilan orang anggota gerombolan itu meneruskan pencarian.
Sepasang mata masing-masing menelusuri setiap jengkal ruangan yang terdapat dalam gua itu. Dinding, lantai, dan atap diperjksa dengan teliti. Semakin lama langkah sembilan orang itu semakin jauh masuk ke dalam gua. Tapi sampai sekian jauh, benda yang dicari belum diketemukan. Akhirnya mereka sampai di ujung terakhir gua itu, di sebuah ruangan yang cukup luas. Di situlah tempat Eyang Aji Ranta bersemadi dan beristirahat.
"Hei...! Kemarii…!"
Tiba-tiba terdengar seruan salah seorang anggota gerombolan yang berambut keriting. Obor di tangannya diangkat tinggi-tinggi di atas kepala. Sementara sepasang matanya menatap penuh selidik pada sebuah benda berwarna gelap sebesar kepala manusia.
Mendengar seruan itu serentak anggota gerombolan lainnya bergegas menghampiri. Dengan bertambahnya dua batang obor yang menerangi tempat laki-laki berambut keriting, maka sekitar tempat itu jadi semakin terang-benderang.
"Benarkah itu benda langit yang dicari-cari Kakang Wisesa?" tanya laki-laki berambut keriting. Nada suaranya menyiratkan keragu-raguan. Obor yang dipegangnya segera diletakkan ke dinding gua.
"Entahlah...," sahut orang yang mempunyai anting-anting di hidung.
"Aku yakin, benda itulah yang dicari Kakang Wisesa," tegas orang yang berkulit hitam legam. Nada suara dan sikapnya menyiratkan keyakinan besar.
"Ya," sambut yang lainnya. "Kakang Wisesa telah menceritakan ciri-ciri benda langit itu. Dan semua yang dikatakan Kakang Wisesa, sesuai dengan benda ini."
"Kalau begitu, tunggu apa lagi?!" tegas orang yang berambut keriting. "Ambil benda itu, dan kita berikan secepatnya pada Kakang Wisesa!"
Tapi, tidak ada satu pun yang berani mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tak terkecuali, laki-laki berambut keriting sendiri.
"Kau saja yang mengambilnya, Guntara," orang yang di hidungnya ada anting-anting balas mengusulkan pada laki-laki berambut keriting.
"Heh...?! Mengapa harus aku, Gota?!" laki-laki berambut keriting yang bernama Guntara terperanjat.
"Tentu saja tidak harus kau, Guntara," lanjut laki-laki beranting di hidung yang ternyata bernama Gota.
"Tapi, karena kau yang mengusulkan lebih dulu, tidak ada salahnya jika kau yang mengambilnya."
"Apakah benda itu tidak beracun?" tanya Guntara ragu-ragu.
"Itulah yang membuat kami khawatir mengambilnya," sahut Gota tenang.
Guntara langsung terdiam dengan dahi berkerut. Jelas ada sesuatu yang dipikirkannya. Sementara Gota juga tak melanjutkan ucapannya. Maka, keheningan pun menyelimuti tempat itu.
"Hhh...!" Guntara menghela napas berat, memecahkan keheningan yang menyelimuti tempat itu. Semua rekannya tanpa sadar menoleh ke arahnya. "Baiklah. Aku akan mengambilnya," ucap laki-laki berambut keriting memutuskan. Suaranya terdengar agak bergetar, menyiratkan ketegangan hatinya.
Bukan hanya Guntara saja yang merasa tegang. Gota dan rekan-rekan yang lain pun mengalami perasaan yang sama. Apakah benda langit itu beracun atau tidak, Guntaralah yang menjadi kelinci percobaan. Guntara membungkukkan badan, lalu perlahan-lahan menjulurkan tangan kanannya. Tampak tangan laki-laki berambut keriting ini gemetar keras. Keringat sebesar besar jagung membasahi seluruh tubuhnya.
Mula-mula hanya tangan kanan saja yang menyentuh benda berwarna gelap itu. Itu pun hanya sekadar menyentuh saja. Beberapa saat lamanya Guntara membiarkan tangannya menempel pada benda itu. Wajahnya terlihat tegang bukan main. Keringat sebesar-besar jagung semakin banyak membasahi wajah dan tubuhnya. Tapi setelah menunggu beberapa saat, hal-hal yang dikhawatirkan ternyata tidak kunjung terjadi.
Perlahan-lahan raut ketegangan di wajah Guntara mulai sirna. Kini laki-laki berambut keriting itu mulai berani mencengkeram benda berwarna gelap itu. Ketika tidak juga terjadi apa-apa, Guntara mengulurkan tangan kirinya. Maka dengan kedua tangan, diangkatnya benda yang diduga berasal dari langit itu.
Dengan penuh rasa bangga, Guntara mengangkat benda berwarna gelap itu tinggi-tinggi di atas kepala. Baru kemudian kakinya melangkah menuju ke luar. Tanpa berkata apa-apa, Gota dan yang lainnya melangkah mengikuti Guntara dari belakang.
"Hhh...!" Laki-laki berikat kepala hitam yang bernama Wisesa menghela napas berat. Untuk yang kesekian kali, pandangannya dialihkan ke arah pintu gua. Tapi anak buahnya yang sejak tadi ditunggu-tunggu, tak kunjung muncul.
Wisesa khawatir, macan putih dapat meloloskan diri. Masalahnya, sejak tadi binatang itu tak henti-hentinya meronta. Tapi usaha yang dilakukannya itu sia-sia saja. Memang, cambuk yang mengikatnya terlalu alot. Wisesa membiarkan saja macan putih itu meronta-ronta, dan sama sekali tidak berusaha mencegah.
Bahkan laki-laki berikat kepala hitam juga tidak mempergunakan kesempatan ini untuk menyerang macan putih. Karena dia tahu, semua itu percuma saja. Macan putih memiliki kekebalan tubuh yang luar biasa. Menyerangnya hanya melelahkan diri sendiri.
Sambil menunggu anak buahnya keluar dari dalam gua, Wisesa mengawasi macan putih itu. Di saat kesabaran laki-laki berikat kepala hitam ini hampir habis, orang-orang yang ditunggunya muncul. Mula-mula yang terlihat Guntara. Di tangan laki-laki berambut keriting itu tampak sebuah benda berwarna gelap, mirip sebuah batu. Tak salah lagi, pasti itu benda langit!
Melihat hal ini, Wisesa tidak mampu menahan perasaannya lagi. Dia bergegas berlari menyambut. Tak sabar lagi hatinya untuk memiliki benda itu. Karena kedua belah pihak bergerak saling menghampiri, maka Guntara dan Wisesa telah saling berhadapan.
"Inikah benda langit itu, Kang?" tanya Guntara seraya mengangsurkan benda di tangannya.
Dengan bernafsu sekali laki-laki berikat kepala hitam menerima benda berwarna gelap itu, lalu diamat-amatinya sejenak. "Benar!" sahut Wisesa setelah memeriksa benda itu. Nada suaranya menyiratkan perasaan gembira yang meledak-ledak. "Inilah benda langit itu!"
Semua orang yang ada di situ menarik napas lega. Mereka tampak tersenyum gembira karena berhasil menjalankan tugas.
"Mari kita tinggalkan tempat ini," ajak Wisesa seraya bergerak meninggalkan tempat itu, diikuti oleh anak buahnya yang membawa mayat-mayat rekan mereka. Tak dipedulikannya macan putih yang masih meronta-ronta melepaskan diri. Sesaat kemudian tubuh mereka telah lenyap ditelan kerimbunan pepohonan dan semak-semak lebat.
* * * * * * * *
Eyang Aji Ranta segera menghentikan langkahnya begitu mulai mendekati batas tembok Desa Pucung. Dengan sendirinya, Rakapitu dan Gibang yang sejak tadi berlari sekuat tenaga untuk mengimbangi kakek berpakaian kuning itu berhasil menyusul. Sekujur tubuh kedua laki-laki itu nampak dibanjiri peluh, dengan napas terengah-engah.
Dapat dibayangkan, betapa kagetnya hati Rakapitu dan Gibang melihat Eyang Aji Ranta sama sekali tidak terlihat lelah. Bahkan desah napasnya biasa saja. Tidak ada setitik pun peluh nampak di wajahnya, maupun tubuhnya.
"Mengapa tergesa-gesa betul, Eyang?" tanya Gibang dengan suara terputus-putus, karena napasnya masih memburu hebat.
Eyang Aji Ranta menoleh. Ditatapnya sejenak wajah pemuda berwajah penuh tahi lalat itu. "Entahlah, Anak Muda," sahut kakek berpakaian kuning, mendesah. "Yang jelas, perasaanku tidak enak sekali hari ini."
"Maksud, Eyang?" tanya Gibang tidak mengerti.
"Sudahlah, Anak Muda." Eyang Aji Ranta mengulapkan tangannya memutuskan pembicaraan.
Gibang tahu diri. Disadari kalau Eyang Aji Ranta tidak ingin memperpanjang pembicaraan itu. Maka pemuda berwajah penuh tahi lalat ini tidak bertanya lagi. Kini ketiga orang itu melanjutkan perjalanan tanpa berkata-kata. Beberapa kali Rakapitu dan Gibang harus tersenyum dan menganggukkan kepala setiap kali ada yang menyapanya.
"Itu rumahnya, Eyang," kata Rakapitu sambil menudingkan telunjuknya ke sebuah rumah berdinding bilik. Letaknya, terpisah dari rumah-rumah lainnya.
Setelah berkata demikian, Rakapitu bergegas mempercepat langkahnya. Laki-laki bertubuh tinggi besar ini berjalan mendahului. Sesaat kemudian, Rakapitu telah berada di depan pintu yang tertutup itu, dan langsung mengetuknya.
Tok, tok, tok...!
Rakapitu menunggu sejenak. Dan sebentar saja, telinganya menangkap suara langkah kaki mendekati pintu. Derit daun pintu yang dibuka lebar terdengar, bertepatan dengan tibanya Eyang Aji Ranta dan Gibang di sebelah Rakapitu. Dan di balik daun pintu nampak seraut wajah keriput seorang kakek.
"Ini Eyang Aji Ranta, Ki," jelas Rakapitu, memperkenalkan laki-laki tua di sebelahnya. "Orang yang Aki mintai pertolongannya."
"Oh, iya. Mengapa aku begini lupa," kakek pemilik rumah itu menepak kepala, kemudian segera mengulurkan tangan.
"Waskita," sebut kakek pemilik rumah mengenalkan diri.
"Aji Ranta," balas Eyang Aji Ranta, memperkenalkan namanya.
"Silakan masuk dulu, Eyang Aji Ranta," ujar Ki Waskita mempersilakan.
Kakek berpakaian kuning itu terkekeh pelan. "Kedengarannya repot sekali mengucapkannya. Bagaimana kalau panggil aku, Kang Aji saja. Rasanya lebih singkat dan enak didengar," usul Eyang Aji Ranta.
"Dan kau sendiri memanggilku Adi Waskita?!" sambung kakek pemilik rumah. Nada suara maupun raut wajahnya menyiratkan kegembiraan. "Begitu, kan?"
"Tepat sekali, Adi Waskita!" Eyang Aji Ranta menganggukkan kepala.
"Boleh kulihat orang yang sakit itu, Adi?" pinta Eyang Aji Ranta setelah mareka semua duduk di dalam.
Senyum di wajah Ki Waskita seketika lenyap. Tentu saja hal itu membuat Eyang Aji Ranta, Rakapitu, dan Gibang jadi khawatir. Menilik dari sikap kakek pemilik rumah itu, bisa diperkirakan kalau ada hal-hal tidak menyenangkan telah terjadi.
"Orang yang sakit itu telah sembuh," jawab Ki Waskita, pelan.
"Apa??" seru Gibang dan Rakapitu berseru kaget.
Sementara itu, Eyang Aji Ranta nampak tenang-tenang saja. Walaupun sebenarnya juga merasa terkejut, tapi kakek berpakaian kuning ini bisa menyembunyikannya.
"Mengapa bisa begitu, Ki?!" tanya Gibang penasaran. "Bukankah semalam sakitnya amat parah? Begitu juga tadi pagi, sebelum kami berangkat."
Rakapitu menganggukkan kepala pertanda mendukung ucapan rekannya. Sedangkan Ki Waskita hanya mengangkat bahu.
"Bagaimana ini bisa terjadi, Ki?" tanya Rakapitu berusaha tenang.
"Hhh...!" kakek pemilik rumah itu menghela napas. "Aku sendiri tidak tahu, Rakapitu. Tapi yang jelas, orang itu sembuh, tak lama setelah kalian pergi ke Hutan Dadap."
Rakapitu dan Gibang kontan terdiam. Dahi kedua orang ini berkernyit, seperti ada sesuatu yang dipikirkan.
"Sebenarnya... siapakah yang sakit?" tanya Eyang Aji Ranta. Kakek berpakaian kuning ini tidak kuat menahan rasa ingin tahunya. Tapi tidak dijelaskan, pada siapa pertanyaan itu ditujukan.
"Lebih baik kumulai saja dari awal. Agar kau jelas, Kang," kata Ki Waskita. "Kemarin sore beberapa orang penduduk datang membawa seorang laki-laki berpakaian prajurit yang tengah terluka padaku. Di antara mereka, terdapat pula Rakapitu dan Gibang. Dan memang, keahlianku adalah mengobati orang terluka. Maka dia segera kuperiksa. Sedangkan Rakapitu dan Gibang menemaniku melakukan pengobatan."
Ki Waskita menghentikan ceritanya sejenak, untuk mengambil napas. Ditatapnya wajah Eyang Aji Ranta lekat-lekat. Memang kepada kakek berpakaian kuning itulah, cerita ini ditujukan. Rakapitu dan Gibang sudah mengetahuinya, karena ikut terlibat dalam penyelamatan orang itu.
"Setelah memeriksa beberapa lama, akhirnya aku menyerah. Orang itu ternyata terkena racun yang amat jahat. Dan aku tidak tahu cara pengobatannya. Untunglah, racun itu mempunyai daya kerja lambat. Sehingga, orang itu dapat bertahan lama," sambung Ki Waskita. "Maka begitu pagi tiba, Rakapitu dan Gibang segera kuperintahkan untuk menemuimu. Ini kulakukan, karena namamu sudah cukup terkenal dalam hal pengobatan racun. Apalagi orang yang terkena racun juga mengatakan kalau kaulah satu-satunya yang bisa menyembuhkan lukanya. Tapi, sayang...."
Ki Waskita menghentikan ceritanya. Ditariknya napas dalam-dalam lalu dihembuskannya kuat-kuat. "Aku tak tahu, bagaimana kejadiannya. Yang jelas begitu Rakapitu dan Gibang berangkat ke Hutan Dadap, orang itu berangsur-angsur sembuh."
"Jadi, orang itu telah sembuh, Ki?" tanya Gibang ingin lebih jelas lagi.
Ki Waskita menganggukkan kepala, tapi tidak ada sinar kegembiraan di wajahnya. Tentu saja hal ini membuat Gibang dan Rakapitu heran. Mengapa Ki Waskita sama sekali tidak kelihatan gembira?
Dengan perasaan agak bingung, kedua orang ini mengalihkan pandangan pada Eyang Aji Ranta. Lagi-lagi mereka terkejut. Wajah kakek berpakaian kuning ini juga tidak terlihat gembira.
"Ada apa ini?" tanya Rakapitu dan Gibang dalam hati.
"Mengapa kau tidak tampak gembira, Ki?" akhirnya Gibang tak kuasa menahan pertanyaan yang bergolak dalam dadanya.
"Hhh...!" hanya desah napas berat Ki Waskita yang menyahuti pertanyaan laki-laki berwajah penuh tahi lalat itu.
"Katakanlah, Ki," Rakapitu ikut mendesak "Jangan biarkan kami dilanda kebingungan."
Ki Waskita menatap wajah Rakapitu dan Gibang berganti-ganti. "Aku mencium adanya hal yang mencurigakan dalam peristiwa ini...."
Rakapitu mengernyitkan dahi. Pemuda bertubuh tinggi besar ini tidak mengerti maksud ucapan kakek pemilik rumah. Ditatapnya Gibang, tapi laki-laki yang wajahnya penuh tahi lalat itu menggelengkan kepala pertanda tidak mengerti.
"Janganlah berteka-teki, Ki," pinta Gibang memohon pengertian.
"Aku curiga kalau peristiwa ini sudah direncanakan," desah Ki Waskita pelan. "Dugaanku, orang itu sengaja minum racun. Namun juga membawa pemunahnya. Dan begitu Rakapitu dan Gibang pergi, obat pemunahnya segera diminum. Pantas saja orang itu seperti mendesakku agar memanggil Eyang Aji Ranta saja. Hhh.... Memancing harimau keluar sarang. Entah apa yang mereka cari di sarang harimau...."
Eyang Aji Ranta terperanjat. Dugaan Ki Waskita ternyata tidak berbeda dengan dugaannya. Jelas, peristiwa ini sudah direncanakan. Tujuannya, untuk memancingnya keluar gua. Seketika itu pula kakek berpakaian kuning ini teringat kembali dengan perasaan tidak enak yang tadi mengganggunya. "Kalau begitu, aku pergi dulu, Adi Waskita."
Tanpa menunggu jawaban, Eyang Aji Ranta bergegas bangkit, dan langsung melangkah ke luar. Langkahnya kelihatan perlahan saja, tapi hebatnya tubuh kakek berpakaian kuning ini telah berada sekitar delapan tombak dari tempat semula. Padahal, Eyang Aji Ranta hanya mempunyai sebuah kaki!
"Hebat...!" Ki Waskita menggeleng-gelengkan kepala. Perasaan takjub dan kagum menghiasi wajahnya. Harus diakui kalau ilmu meringankan tubuh Eyang Aji Ranta amat luar biasa.
"Ki...! Maksudmu...," Rakapitu yang masih kurang jelas kembali buka suara.
"Kemungkinan semua ini adalah sebuah siasat, yang telah diatur rapi untuk memancing Eyang Aji Ranta keluar dari tempat tinggalnya."
"Apa maksudnya, Ki?" tanya Rakapitu lagi.
"Aku juga tidak tahu, Rakapitu," jawab Ki Waskita.
"Mungkin mereka bermaksud menangkap macan putih?" Gibang mengajukan dugaannya.
"Yaaah..., mungkin saja," sambut Ki Waskita.
* * * * * * * *
TIGA
Kini Eyang Aji Ranta tidak ragu-ragu lagi mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Sekarang dia sendirian, jadi bebas berlari secepat yang diinginkannya. Eyang Aji Ranta memang bukan tokoh sembarangan. Dia adalah seorang tokoh yang memiliki kepandaian tinggi. Kecepatan gerakannya pun luar biasa, meskipun hanya mempunyai kaki sebelah! Tubuh kakek berpakaian kuning ini berkelebat cepat laksana anak panah lepas dari busur. Saking cepatnya, tubuh kakek ini seperti lenyap bentuknya. Yang terlihat hanyalah seleret bayangan kuning melesat menuju Hutan Dadap.
Karuan saja, banyak penduduk Desa Pucung yang terheran-heran begitu melihat sekelebatan bayangan kuning melesat cepat menuju mulut desa. Mereka tidak dapat mengetahui, apakah sebenarnya kelebatan bayangan kuning itu. Meskipun begitu, memang bisa diduga kalau bayangan kuning itu adalah orang yang memiliki kepandaian tinggi. Angin menderu keras begitu bayangan kuning itu lewat, pertanda kuatnya tenaga yang mendorong gerakannya.
Dalam sekejapan saja, mulut Desa Pucung telah terlewat. Tapi, Eyang Aji Ranta sama sekali tidak mengendurkan larinya. Kakek berpakaian kuning ini tetap mengerahkan kemampuan lari yang ditunjang ilmu meringankan tubuh setinggi mungkin. Tak lama kemudian, mulut Hutan Dadap telah terlihat Hal ini membuat semangat Eyang Aji Ranta semakin membesar. Kakek ini terus berlari cepat menuju ke sana.
Eyang Aji Ranta tetap tidak mengendurkan larinya ketika melewati kerimbunan semak-semak dan pepohonan lebat. Tongkat bututnya bergerak ke kiri dan ke kanan, sebagai pembuka jalan. Suara berkerosakan keras dari semak-semak yang terlanda, dan suara berkeretakannya ranting-ranting patah terdengar ketika Eyang Aji Ranta melewatinya. Sebentar kemudian, Eyang Aji Ranta sudah berada beberapa tombak di depan gua tempat tinggalnya.
Tercekat hati kakek ini tatkala melihat macan putihnya terikat di sebatang pohon. Binatang itu sama sekali tidak berusaha melepaskan diri, tapi hanya berputar-putar mengelilingi pohon. Bisa diduga kalau ada sesuatu yang terjadi pada binatang itu. Dan ini membuat Eyang Aji Ranta khawatir bukan main.
Macan putih mengaum keras begitu melihat kedatangan majikannya. Seketika semangat binatang itu bangkit kembali untuk melepaskan diri. Macan itu kembali meronta-ronta. Tapi seperti kejadian sebelumnya, usaha yang dilakukannya sia-sia.
Eyang Aji Ranta segera melepaskan ikatan yang membelenggu binatang peliharaannya. Dengan hati cemas sekujur tubuh macan putih itu diperiksanya, kalau-kalau ada bagian yang teriuka. Lega hati kakek ini begitu tidak terlihat ada luka di tubuh macan kesayangannya.
Macan putih menggereng-gereng. Sementara Eyang Aji Ranta mendengarkan penuh perhatian. Cukup lama juga binatang itu bersikap demikian. Dan ketika macan putih menghentikan gerengan, kakek berpakaian kuning itu menundukkan kepala. Sepertinya Eyang Aji Ranta mengerti arti gerengan macan itu. Dan memang binatang itu seperti mengungkapkan sesuatu.
"Hhh...!" Eyang Aji Ranta menghela napas berat. Sekarang dia tahu maksud orang-orang memancingnya keluar dari tempat tinggalnya. Macan putih telah menceritakannya, walau hanya lewat gerengan.
"Jadi..., benda langit itu yang mereka cari...," gumam Eyang Aji Ranta pelan seraya mengangkat kepalanya. Sepasang matanya menatap ke atas, melihat matahari yang telah melewati atas kepala.
"Grrrh...!" Macan putih menggereng kembali. Tapi nadanya kali ini berbeda dengan sebelumnya. Sementara Eyang Aji Ranta hanya menggelengkan kepala. Secercah senyum pahit tersungging di bibirnya.
"Terima kasih atas kesediaanmu, Putih," sahut kakek berpakaian kuning itu pelan. "Tapi kurasa kita tidak perlu mengejar mereka. Aku yakin, kalau saranmu kuikuti..., kita akan terlibat kembali dalam kekerasan! Padahal, aku sudah muak dengan kerasnya dunia persilatan. Aku ingin, di sisa-sisa hidupku ini dapat hidup tenang."
Eyang Aji Ranta membelai-belai kepala binatang peliharaannya. Dalam hati, dia berterima kasih sekali pada macan putih. Binatang itu tadi mengajaknya mencari orang-orang yang telah mencuri, kalau dia ingin benda langit itu kembali.
"Maafkan aku, Putih. Bukannya menolak usulmu, tapi aku tidak ingin terlibat kembali dalam kekerasan. Kau bisa mengerti, Putih?"
Macan putih itu menggereng pelan.
"Kalau begitu, mari kita kembali ke gua," ajak Eyang Aji Ranta seraya melangkahkan kaki menuju tempat yang dimaksud. Sambil menggereng pelan, macan putih itu bergerak mengikuti. Binatang itu berlari-lari kecil di sebelah majikannya. Tak lama kemudian, tubuh Eyang Aji Ranta dan macan putih itu telah tidak terlihat lagi, lenyap ditelan kegelapan gua.
* * * * * * * *
Waktu berputar sesuai kodratnya. Matahari bergerak menurut aturannya. Timbul di langit sebelah Timur, dan tenggelam di sebelah Barat. Seiring tenggelamnya matahari, kegelapan pun menyelimuti bumi. Malam pun datang menjelang. Kini kehidupan berganti. Tidak ada lagi cicit burung atau keruyuk ayam jantan. Yang terdengar adalah kepak sayap kelelawar yang keluar mencari makan.
Tak jarang pula terdengar kukuk burung hantu menguak keheningan malam. Tapi ternyata tidak hanya binatang-binatang malam itu saja yang keluar meninggalkan tempat tinggalnya. Ternyata, masih ada lagi yang berkeliaran dalam suasana malam sehening itu.
'Makhluk' itu adalah sesosok bayangan hitam yang bergerak cepat menuju Hutan Dadap. Dalam keremangan malam yang hanya diterangi bulan sabit di langit, tidak nampak jelas wajah sosok bayangan hitam itu. Apalagi dia mengenakan caping bambu yang membuat wajahnya terlindung.
Bukan itu saja. Mulai dari bawah mata sampai bawah dagu, ditutupi pula oleh sehelai kain yang berwarna hitam. Kain itu diikatkan ke belakang kepala. Maka lengkaplah sudah tanda tanya, siapa sosok bayangan hitam itu.
Sosok itu melesat terus masuk ke dalam hutan, menerobos kerimbunan semak-semak dan pepohonan yang lebat. Namun mendadak langkahnya berhenti. Capingnya diangkat sedikit ke atas untuk memperjelas pandangannya. Tapi pandangan matanya memang tidak salah. Dalam keremangan malam itu, di sebatang pohon beringin yang berjarak sekitar dua tombak darinya, tertancap sebatang tombak berwarna putih mengkilat.
Bisa diduga kalau orang yang menancapkan tombak di situ memang mempunyai maksud agar hal itu diketahui orang yang dituju. Sosok bayangan hitam itu kemudian melangkah menghampiri. Tampak jelas kalau di dekat mata tombak itu terbelit sebuah rantai baja yang juga berwarna putih, di ujung rantai itu tergantung sebuah tengkorak manusia! Menilik dari ukurannya, dapat diketahui kalau tengkorak itu adalah tengkorak kepala anak kecil.
"Hm...," sosok bayangan hitam itu hanya menggumam pelan, seperti tahu maksudnya. Tiba-tiba terdengar suara berkaokan keras. Panjang dan tiga kali berturut-turut, lalu berhenti. Sebentar kemudian suara itu terdengar lagi seperti tadi. Panjang dan tiga kali berturut-turut.
Bagi orang yang tidak terlalu ambil peduli, tentu akan menduga kalau suara itu berasal dari burung kuak-kuak. Tapi kalau saja orang mau sedikit mencurahkan perhatian, akan jelas kejanggalannya. Suara berkaokan itu nadanya selalu sama. Panjang, dan tiga kali berturut-turut. Lalu, berhenti sejenak. Sesaat terdengar lagi. Begitu seterusnya.
Memang, suara berkaokan itu bukan berasal dari burung kuak-kuak, melainkan dari mulut sosok bayangan hitam itu. Tampaknya dia tengah menanti sesuatu. Tak lama kemudian terdengar suara berkaokan keras pula, tapi berirama lain dengan yang sebelumnya. Suara kaokan kali ini meskipun nadanya panjang, tapi tidak tiga kali berturut-turut. Bunyinya cukup dua kali. Bahkan berhenti agak lama, lalu terdengar kembali.
Tak lama kemudian, terdengar suara gemerisik dari rerumputan yang terlanda sesuatu. Sosok bayangan hitam itu menoleh ke arah asal suara gemerisik. Sepasang matanya menatap ke depan dari balik caping yang bertengger di atas kepala.
Sesaat kemudian, dari balik kerimbunan semaksemak dan pepohonan, bermunculan beberapa sosok tubuh yang semuanya berpakaian hitam. Maka seketika sosok bayangan hitam mengangkat sedikit capingnya. Dengan tatapan mata, dihitungnya jumlah sosok yang berdiri di hadapannya. Ternyata sembilan orang.
"Bagaimana, Wisesa? Berhasil?" tanya sosok bercaping itu, seraya menatap sosok yang berdiri paling depan. Sembilan sosok yang berdiri di hadapan orang bercaping itu memang Wisesa bersama anak buahnya.
"Begitulah, Kang," sahut laki-laki berikat kepala hitam itu. Menilik dari panggilan, dapat diketahui kalau dirinya mempunyai hubungan baik dengan orang bercaping bambu.
"Bagus..!" puji orang bercaping, gembira. "Cepat serahkan padaku!"
"Sabar, Kang," sergah Wisesa buru-buru. "Bagaimana dengan janjimu? Perlu kau ketahui, Kang. Mengambil benda itu sulit sekali."
"Hm... Bukankah aku sudah mengirim orang untuk memancing kakek jompo itu keluar dari guanya?!" sergah orang bercaping penasaran.
"Apa yang kau katakan itu tidak salah, Kang," sahut Wisesa dengan suara tawar. "Tapi, kau melupakan binatang peliharaannya."
"Maksudmu..., macan putih?" orang bercaping mulai teringat.
"Benar, Kang," laki-laki berikat kepala hitam menganggukkan kepalanya. "Binatang itu ternyata kuat sekali. Bahkan empat orang anak buahku tewas ketika berusaha merobohkannya. Kalau saja aku tidak turun tangan, mungkin mereka semua tewas."
Orang bercaping itu hanya mengangguk-anggukkan kepala saja.
"Permintaan kami tidak berat, Kang. Kami hanya mohon agar kau bersedia membantu bila kami menghadapi lawan tangguh."
"Hanya itu yang kau minta, Wisesa?" Laki-laki berikat kepala hitam menganggukkan kepala.
"Jadi, kau bersedia memenuhi permintaan kami, Kang?"
Orang bercaping itu menganggukkan kepala. "Mana benda itu?" pinta orang bercaping itu.
"Guntara...!" Wisesa mendongakkan kepala ke atas pohon.
Belum juga lenyap gema teriakan itu, dari atas pohon melayang turun sesosok tubuh. Lalu, sosok tubuh itu mendarat dengan manisnya di tanah. Di tangannya tergenggam sebuah benda mirip batu berwarna gelap, berukuran sebesar kepala manusia.
Sepasang mata di balik caping itu berkilat-kilat. Secercah senyum mengejek tersungging di mulut yang tertutup kain hitam. Diam-diam dipujinya kecerdikan laki-laki berikat kepala hitam. Ternyata Wisesa tidak meninggalkan kewaspadaannya. Kepala rampok itu menyuruh salah seorang anak buahnya untuk membawa benda itu, dan bersembunyi. Dia berjaga-jaga, kalau-kalau sosok bercaping akan bertindak tidak jujur.
Wisesa segera mengambil benda itu dari tangan anak buahnya. "Ini benda itu, Kang," laki-laki berikat kepala hitam itu mengangsurkan benda langit pada orang bercaping.
Orang bercaping itu mengulurkan tangan menyambut. Beberapa saat diperiksanya benda itu, sambil mengetuk sana-sini.
"Bagaimana, Kang?" tanya Wisesa.
"Hm...." Hanya gumaman tak jelas dari orang bercaping itu yang menyambuti ucapan Wisesa. Kemudian benda itu dimasukkannya ke dalam buntalan kain hitam yang tersampir di punggung.
Mendadak, tangan sosok bercaping itu bergerak ke pinggang. Cepat bukan main gerakannya. Dan begitu kembali ke tempat semula, di tangannya telah tergenggam sebilah keris berkeluk tujuh. Dan secepat keris itu tergenggam, secepat itu pula ditusukkan ke leher Wisesa.
Wisesa terperanjat. Sebagai seorang tokoh hitam, tentu saja dia tidak menjadi kaget mendapat serangan tak terduga-duga ini. Tapi kecepatan gerak sosok bercaping itu benar-benar di luar dugaan. Karena sejak tadi sudah bersiap siaga, maka begitu melihat datangnya serangan maut yang mengancam nyawa, Wisesa segera melempar tubuh ke samping. Dia langsung bergulingan di tanah beberapa kali.
"Serang...!" Sambil terus bergulingan di tanah, laki-laki berikat kepala hitam ini memberi perintah. Wisesa juga khawatir, selagi dia bergulingan, serangan susulan dari orang bercaping itu datang.
Singgg, singgg, singgg...!
Sinar-sinar berkilatan berpendar ketika anak buah Wisesa menyerbu orang bercaping itu dengan senjata terhunus. Suara-suara berdesing nyaring mengiringi hujan serangan itu. Orang bercaping menggertakkan gigi melihat serangannya dapat dielakkan. Belum lagi serangan susulan dilancarkan, serangan anak buah Wisesa telah datang bertubi-tubi bagai hujan. Terpaksa maksudnya dibatalkan untuk mengirimkan serangan pada laki-laki berikat kepala hitam itu.
Tranggg, tranggg...!
Suara berdentang nyaring terdengar berkali-kali begitu orang bercaping menggerakkan kerisnya, menangkis tiga buah serangan yang datang lebih dulu. Bunga-bunga api seketika memercik ke sana kemari. Guntara dan dua orang kawannya terperanjat begitu merasakan tangan yang berbenturan dengan senjata lawan terasa lumpuh. Hampir saja senjata-senjata mereka terlepas. Dan kini keadaan mereka amat berbahaya.
Untung pada saat yang gawat, serangan rekan-rekan mereka yang lain tiba. Sehingga, orang bercaping itu tidak mempunyai kesempatan mengirimkan serangan susulan. Kembali terdengar suara keras denting senjata beradu, diikuti percikan bunga-bunga api di udara. Dan di saat itulah, Wisesa telah berhasil memperbaiki keadaannya. Dan dia ikut terjun dalam kancah pertempuran kembali.
"Kau ceroboh, Brajageni...! Kau mencari penyakit sendiri! Kalau saja tadi kau tidak bertindak macam-macam, pemunah racun ini akan kuberikan! Tapi sekarang, jangan harap!" ancam Wisesa keras.
"Jangan merasa menang dulu, Wisesa! Kau kira aku tidak tahu kalau benda langit itu ditaburi racun? Ha ha ha...! Racun bagiku adalah permainan anak-anak, Wisesa! Racunmu sama sekali tidak berarti bila digunakan padaku!"
"Keparat!" maki Wisesa kalap. "Serbu...!" Tanpa menunggu perintah dua kali, anak buah Wisesa segera meluruk ke arah Brajageni.
"Hmh...!" Brajageni mendengus. Mendadak tangan kanannya dimasukkan ke balik baju. Dan begitu tangan itu dikeluarkan, secepat itu pula dikibaskan.
Serrr...! Wisesa terperanjat. Sebagai tokoh yang telah berpengalaman, dia tahu benda yang mengeluarkan suara berdesir itu.
"Awas...!" teriak Wisesa seraya melempar tubuh ke samping kanan dan bergulingan menjauh. Laki-laki berikat kepala hitam ini berhasil lolos dari maut.
Tapi tidak demikian anak buahnya. Serangan itu sama sekali tidak disangka-sangka. Apalagi, datangnya selagi tubuh mereka telah dekat dengan lawan. Tambahan lagi, suasana malam yang remang-remang membuat mereka tidak dapat melihat jelas benda yang datang menyambar. Tapi meskipun begitu, mereka berusaha menyelamatkan diri semampunya begitu mengetahui ada bahaya mengancam.
Suara-suara jerit kesakitan terdengar begitu benda-benda yang tak lain adalah jarum-jarum halus itu mengenai sasaran. Jarum-jarum itu tentu saja bukan jarum sembarangan, karena mengandung racun ganas. Terbukti begitu empat di antara mereka terkena, langsung saja meringis sambil memegang bagian yang terluka. Mereka jatuh menggelepar-gelepar di tanah beberapa saat lamanya, kemudian tidak bergerak lagi untuk selamanya.
Wisesa meraung keras. Laki-laki berikat kepala hitam ini murka bukan kepalang. Segera senjata andalannya dicabut. Senjata yang berupa sebatang golok besar yang sisi-sisinya bergerigi mirip gergaji itu telah diputar-putarnya.
"Hiaaat..!" Seraya berteriak keras, Wisesa melompat. Dan dari atas, golok di tangannya dibabatkan cepat ke arah leher Brajageni. Ada suara mengaung yang cukup keras mengiringi tibanya serangan itu. Jelas, laki-laki berikat kepala hitam ini memiliki tenaga dalam cukup tinggi.
Pada saat yang sama, Guntara dan Gota yang berhasil selamat dari serangan jarum-jarum beracun, juga meluruk menyerang Brajageni. Guntara menyerang dari depan dengan sebuah tusukan tombak ke arah dada, sementara Gota menyerang dari belakang. Pedangnya menusuk cepat ke arah punggung.
Mendapat serangan maut yang berbarengan, tidak juga membuat Brajageni gugup. Bahkan malah ditunggunya hingga semua serangan itu menyambar dekat. Lalu dengan perhitungan matang seorang yang memiliki ilmu meringankan tubuh tingkat tinggi, Brajageni segera melempar tubuh ke belakang. Dan dengan sendirinya, serangan yang datang dari belakang dan depan kandas. Sementara serangan Wisesa ditangkisnya.
Tranggg...!
Bunga api memercik ke sana kemari begitu kedua senjata beradu keras bukan main. Wisesa menggigit bibir ketika merasakan tangannya pegal-pegal. Dengan meminjam tenaga benturan, Brajageni bersalto ke belakang sekali. Dan ketika berada di belakang Gota, tangannya bergerak mendorong. Kelihatannya perlahan saja. Tapi akibatnya, tubuh laki-laki beranting di hidung itu terhuyung ke depan seperti diseruduk banteng!
Guntara terperanjat kaget. Pada saat itu, tombaknya tengah ditusukkan ke depan, dan tidak mampu ditahan lagi. Maka dapat dibayangkan betapa kaget hatinya ketika melihat tubuh Gota menyambut ujung tombaknya. Sementara, ujung pedang Gota pun mengarah dadanya.
Crabbb, cappp...!
Rentetan kejadian itu berlangsung begitu cepat. Dan tahu-tahu, tubuh Gota dan Guntara telah tersungkur di tanah dengan senjata yang saling hunjam tubuh mereka. Nyawa kedua orang itu langsung melayang tanpa memperdengarkan suara sedikit pun. Tidak hanya sampai di situ saja tindakan Brajageni. Begitu kedua kakinya mendarat, tangannya kembali mengibas. Disambutnya serbuan sisa-sisa anak buah Wisesa.
Singgg, singgg...!
Cappp, cappp, cappp...!
Empat senjata rahasia berbentuk bintang itu mengenai dahi sisa anak buah Wisesa dengan telak dan keras. Senjata rahasia itu menghunjam sampai setengahnya lebih. Seketika itu juga tubuh keempat orang itu roboh di tanah. Sesaat mereka menggelepar-gelepar, kemudian diam tidak bergerak lagi. Wisesa hanya bisa memandang semua ini dengan wajah pucat laksana mayat. Semua anak buahnya telah tewas. Dan sekarang, dia hanya tinggal seorang diri.
"Bersiaplah untuk mati, Wisesa!" ancam Brajageni lambat lambat tapi penuh tekanan. Ada ancaman maut dalam suaranya.
"Keparat kau, Brajageni!" teriak Wisesa kalap. "Kau atau aku yang harus mati!" Setelah berkata demikian, laki-laki berikat kepala hitam menerjang orang bercaping itu. Golok di tangannya menusuk cepat ke arah dada.
Brajageni hanya mendengus. Buru-buru kakinya melangkah ke kiri seraya mendoyongkan tubuh. Maka serangan itu lewat sejengkal di sebelah kanan pinggangnya. Pada saat itulah, keris di tangannya dibabatkan ke arah perut lawan. Wisesa terperanjat melihat bahaya maut yang mengancamnya. Dengan semampu mungkin dia berusaha mengelak. Tapi....
Crattt..!
Ujung keris itu menyerempet perut Wisesa. Seketika itu juga kulit laki-laki berikat kepala hitam itu sobek. Cairan berwarna merah kehitam-hitaman segera merembes keluar. Ternyata, keris itu mengandung racun!
"Uuuh...!" Wisesa mengeluh. Kepalanya dirasakan pusing. Pandangan matanya berkunang-kunang. Laki-laki berikat kepala hitam ini sadar kalau racun itu telah bekerja. Perasaan pusing yang menyerangnya semakin menjadi-jadi. Tubuh Wisesa mulai oleng, dan kemudian jatuh di tanah. Dia menggelepar-gelepar meregang nyawa.
"Ha ha ha...!" Brajageni tertawa terbahak-bahak. Sebuah tawa bernada kemenangan. "Selamat tinggal Wisesa...!"
Setelah berkata demikian, Brajageni lalu melesat meninggalkan tempat itu. Ditinggalkannya Wisesa yang tengah sekarat menanti datangnya maut Brajageni yakin kalau laki-laki berikat kepala hitam itu akan tewas. Dia yakin, racunnya tidak pernah gagal mengambil nyawa orang. Sesaat kemudian, tubuh laki-laki bercaping itu telah lenyap ditelan kegelapan malam.
Wisesa tidak mempedulikan Brajageni lagi. Rasa sakit yang mendera tubuhnya benar-benar menyiksa. Bahkan ucapan terakhir laki-laki bercaping itu tidak didengarnya lagi. Laki-laki berikat kepala hitam ini hanya bisa menyesali dirinya. Mengapa dia mau saja waktu diajak bekerja sama untuk mendapatkan benda langit itu? Tapi, Wisesa hanya mempunyai waktu menyesal sebentar saja. Karena beberapa saat kemudian, nyawanya segera pergi ke alam baka.
* * * * * * * *
EMPAT
Brajageni meninggalkan Hutan Dadap dengan diliputi perasaan gembira. Sungguh tidak disangka, kalau semudah ini masalahnya akan beres. Kini tinggal satu pekerjaan lagi yang harus diselesaikannya, maka dia akan memiliki sebuah senjata pusaka yang ampuh. Laki-laki bercaping ini terus berlari mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Dalam waktu sebentar saja, Hutan Dadap telah jauh ditinggalkannya.
Brajageni terus berlari disertai pengerahan ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya. Lesatannya bagaikan bayangan setan yang berkelebat, menyelusup rapatnya pepohonan dan semak belukar. Lesatannya baru diperlambat ketika terlihat sebuah rumah berdinding bilik di kejauhan. Rumah itu letaknya terpencil, jauh dari rumah-rumah yang lainnya. Ke sanalah laki-laki bercaping ini menuju.
Semakin lama jarak antara Brajageni dengan rumah itu semakin dekat. Ketika jaraknya tinggal sekitar dua tombak lagi, laki-laki bercaping ini menghentikan larinya sama sekali. Kini Brajageni melangkah perlahan mendekati pintu.
Tok, tok, tok..!
Kelihatannya perlahan saja Brajageni mengetukkan tangannya. Tapi akibatnya, daun pintu itu bergetar keras laksana dipukul palu godam yang besar.
"Siapa?" terdengar suara teguran dari dalam, diiringi langkah-langkah kaki mendekati pintu.
Brajageni sama sekali tidak menyahuti. Bahkan caping bambunya semakin ditekankan ke bawah. Maka, wajahnya jadi semakin tersembunyi.
Kriiit..! Suara berderit tajam terdengar begitu daun pintu itu terbuka. Tampaklah seorang kakek di balik pintu. Kulitnya hitam legam, bertelanjang dada. Sepasang matanya menatap tamu tak diundang ini penuh selidik. Belum sempat kakek berkulit hitam itu bertanya, Brajageni telah mendorong daun pintu, lalu melangkah masuk. Langsung ditutupnya daun pintu begitu berada di dalam.
"Kau yang bernama Empu Sawung?" tanya Brajageni langsung pada pokok persoalan.
Kakek berkulit hitam mengerutkan alis. Sungguh dia tidak senang mendapat perlakuan yang begitu kasar dari tamu tak diundang ini. Apalagi orang ini baru pertama kali dilihatnya. Untunglah hati kakek ini sedikit sabar. Kalau tidak, pasti langsung dihajarnya tamu tak diundang ini.
Brajageni jadi gusar melihat kakek berkulit hitam itu sama sekali tidak menjawab pertanyaannya. Dengan kasar, dicengkeramnya leher baju kakek itu. Dan didekatkan wajah kakek itu ke wajahnya.
"Jawab pertanyaanku!" bentak Brajageni. Sepasang mata Brajageni menatap bengis, menusuk langsung ke bola mata kakek yang bernama Empu Sawung. Ada ancaman maut yang terkandung dalam sinar matanya. Tapi kakek berkulit hitam tetap diam, dengan sikap tetap tenang. Sepasang matanya malah menatap lepas ke atap rumah.
"Keparat..!" maki Brajageni keras. Laki-laki bertubuh tinggi kurus ini tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dengan kasar, didorongnya tubuh kakek pemilik rumah itu.
Brakkk...!
Punggung kakek berkulit hitam itu membentur keras dinding yang terbuat dari papan. Mulut kakek itu menyeringai, menahan rasa sakit akibat benturan itu. Perlahan-lahan tubuhnya merosot ke bawah. Brajageni mencabut kerisnya, kemudian bergerak menghampiri. Langkahnya lebar-lebar, sehingga dalam beberapa tindak saja, telah berada di depan kakek pemilik rumah. Perlahan-lahan Brajageni berjongkok.
"Jangan buat kesabaranku habis!" ancam laki-laki bertubuh tinggi kurus ini. "Kaukah orang yang bernama Empu Sawung?! Jawab...! Atau kau ingin bisu selamanya?!"
Brajageni mendekatkan kerisnya ke wajah kakek berkulit hitam itu, bersikap mengancam. Tapi, kakek itu tetap membisu. Maka kesabaran Brajageni pun habis. "Kau pikir aku main-main, heh?!"
Setelah berkata demikian, perlahan-lahan keris di tangan laki-laki tinggi kurus ini bergerak, siap hendak memotong lidah kakek berkulit hitam yang tetap diam membisu. Tapi, mendadak saja gerakannya terhenti. Pendengarannya yang tajam menangkap adanya langkah kaki mendekati ruangan ini. Arahnya dari dalam rumah.
Menilik dari gerakannya, Brajageni tahu kalau pemilik langkah itu sama sekali tidak memiliki ilmu meringankan tubuh. Andaikata memiliki, tingkatannya masih rendah sekali. Langkahnya pun terdengar berat. Meskipun begitu, Brajageni tidak bersikap ceroboh dan memandang rendah. Kepalanya menoleh tatkala mendengar langkah kaki itu tiba-tiba berhenti.
Di ambang pintu yang menuju ke dalam, tampak berdiri seorang bocah perempuan berusia sekitar sebelas tahun. Rambutnya panjang dan berkulit putih bersih.
"Kakek...," panggil bocah perempuan itu.
Sesaat Brajageni tercenung. Jadi, bocah perempuan itu adalah cucu kakek berkulit hitam ini? Secercah senyum keji tersungging di bibir yang tertutup kain hitam itu. Perlahan dia bangkit berdiri, lalu berjalan menghampiri bocah perempuan itu.
Kakek berkulit hitam ini terkesiap begitu melihat laki-laki bercaping melangkah menghampiri cucunya. "Ayu! Lari...!" seru kakek berkulit hitam itu seraya bergerak bangkit. Dan secepat tubuhnya berdiri, secepat itu pula Brajageni diterkamnya.
Sementara itu gadis kecil itu hanya menatap tak mengerti melihat kakeknya diancam. Malah saat kakeknya menyuruh pergi, dia seperti tak mampu pergi dari situ. Gadis itu kian gemetar melihat laki-laki bercaping semakin mendekati. Lidahnya terasa kelu, tak mampu mengucapkan kata-kata.
Namun laki-laki tinggi kurus itu hanya mendengus. Dan sekali tangannya bergerak, tangan kanan kakek berkulit hitam telah tercekal. Dan sekali Brajageni bergerak mendorong, maka tubuh kakek berkulit hitam itu langsung terhuyung menabrak dinding. Tanpa mempedulikan keadaan kakek berkulit hitam itu, Brajageni meneruskan maksudnya. Dengan sekali mengulurkan tangan, tubuh bocah perempuan bernama Ayu itu telah ditangkapnya.
"Lepaskan cucuku...!" teriak kakek berkulit hitam keras seraya menggoyang-goyangkan kepala, akibat rasa pusing yang diderita dari benturan tadi.
"Ha ha ha...!" Brajageni tertawa bergelak. Dengan kasar, laki-laki tinggi kurus itu menjambak rambut Ayu. Karuan saja gadis kecil itu menjerit kesakitan. Tapi Brajageni malah tertawa terbahak-bahak. Bahkan cengkeramannya semakin diperkuat. Maka jerit kesakitan anak itu pun semakin nyaring terdengar.
"Jahanam! Iblis terkutuk!" maki kakek berkulit hitam dengan suara mengandung isak tangis. Pilu hati kakek ini melihat cucunya disiksa tanpa dia mampu berbuat sesuatu untuk menolongnya. "Lepaskan cucuku! Aku berjanji akan memenuhi apa pun permintaanmu."
Kembali Brajageni tertawa bergelak. "Kalau saja sejak tadi kau bersikap begitu, kau, dan cucumu tidak perlu mengalami hal seperti ini."
Setelah berkata demikian, laki-laki tinggi kurus ini lalu melepaskan Ayu. Seketika itu juga, bocah perempuan itu menghambur ke arah kakek berkulit hitam yang segera mengembangkan kedua tangannya.
"Kakek... Ayu takut..," keluh bocah perempuan itu sambil memeluk kakeknya erat-erat. Wajahnya disembunyikan di pelukan kakek berkulit hitam. Ayu tak berani menoleh, takut melihat Brajageni.
"Tenanglah, Ayu," hibur kakek berkulit hitam sambil mengusap-usap rambut gadis kecil itu penuh kasih sayang.
"Jawab pertanyaanku, sebelum terlambat. Kaukah orang yang bernama Empu Sawung?!" selak Brajageni tidak sabar.
Kakek berkulit hitam itu menganggukkan kepala.
"Jawab...!" hardik Brajageni dengan suara mengguntur. "Kau punya mulut, bukan?!" Keras bukan kepalang bentakan itu. Kakek berkulit hitam sendiri sampai terjingkat kaget. Apalagi Ayu. Gadis kecil itu makin erat memeluk kakeknya. Bahkan tubuhnya nampak menggigil.
"Benar. Aku Empu Sawung...," sahut kakek berkulit hitam, pelan.
Brajageni mengambil buntalan yang tersampir di punggungnya. Lalu dibuka dan dikeluarkan isinya. "Kuminta, kau membuatkan aku sebuah keris. Keris yang mempunyai bilah lurus."
Kakek berkulit hitam yang ternyata bernama Empu Sawung itu memperhatikan benda mirip batu, berwarna gelap itu. Perlahan-lahan tangan kanannya diulurkan. Dirabanya benda langit yang berada di tangan Brajageni itu. Untunglah, laki-laki tinggi kurus itu telah membersihkan racun yang semula ditaburkan Wisesa di batu itu. Kalau tidak, Empu Sawung mungkin sudah tidak bernyawa lagi.
"Bahan yang amat baik," ucap Empu Sawung jujur.
Tapi Brajageni sama sekali tidak menggubrisnya. "Tiga hari lagi aku akan datang untuk mengambil pesananku," kata laki-laki tinggi kurus itu dingin. "Dan ini bayarannya." Setelah berkata demikian, laki-laki tinggi kurus ini melemparkan buntalan kain kecil.
Cringgg,..! Suara berdencing nyaring terdengar begitu buntalan kain kecil itu menimpa lantai.
Eyang Sawung memandang buntalan kain itu dengan sinar mata hampa. Kakek ini sama sekali tidak berharap kalau laki-laki bercaping ini akan membayar pesanannya. Yang ada di benaknya hanya satu, Brajageni harus buru-buru angkat kaki dari rumahnya.
"Ingat, Sawung!" ancam Brajageni sebelum melangkah meninggalkan tempat itu. "Jangan coba-coba mempermainkanku! Akibatnya akan sangat mengerikan!"
Dan sebelum gema suaranya lenyap, tubuh Brajageni sudah tidak berada di situ lagi. Empu Sawung seketika bergidik, tidak berani main-main. Kakek ini tahu, orang seperti Brajageni bukan termasuk orang yang suka menggertak sambal saja. Empu Sawung melihat sinar kekejaman di mata orang bercaping itu.
* * * * * * * *
Empu Sawung bekerja keras, bagai tidak pernah merasa lelah. Kakek ini adalah seorang pandai besi sejati. Tidak ada hal yang paling menggembirakan hatinya, kecuali membuat sebuah senjata dari bahan yang baik. Dan benda yang dibawa Brajageni adalah sebuah bahan yang amat bagus. Dan itu diketahuinya betul! Maka, kini Eyang Sawung mengerjakannya penuh semangat.
Tanpa mengenal lelah, Eyang Sawung membakar benda langit di tungkunya. Sampai warnanya agak gelap berubah merah membara, kemudian menempanya. Suara berdentang nyaring dari benda logam yang beradu selalu terdengar dari ruang kerja Eyang Sawung. Kakek berkulit hitam ini bekerja penuh ketekunan, berusaha keras untuk merampungkan tugas tepat pada waktunya.
Tepat pada hari yang dijanjikan, keris itu selesai dibuat. Sebuah keris yang mempunyai bilah lurus, tidak berkeluk sama sekali. Kakek berkulit hitam itu memandanginya penuh rasa puas. Eyang Sawung menghela napas lega. Sebentar lagi Brajageni tentu akan datang. Tapi kali ini Eyang Sawung sama sekali tidak merasa khawatir. Ayu telah kembali ke rumah orang tuanya, dan kini dirinya kembali sendirian di rumah yang terpencil ini. Perlahan kakinya melangkah kembali ke ruang depan.
"Hhh...!" Eyang Sawung menghela napas berat. Kemudian menghempaskan tubuhnya di kursi. Sebentar matanya dipejamkan, tak lama kemudian sudah tertidur. Entah sudah berapa lama tertidur, Eyang Sawung tidak mengetahuinya. Yang jelas, dia terbangun ketika mendengar bentakan keras menggelegar.
"Bangun, Bandot Tua Pemalas...! Mana pesananku...?!"
Eyang Sawung kontan gelagapan begitu tahu-tahu di depannya telah berdiri orang yang ditunggu-tunggu. Siapa lagi kalau bukan laki-laki bertubuh tinggi kurus dan bercaping bambu. Dengan kesadaran yang belum sepenuhnya pulih, Eyang Sawung menatap ke luar rumah. Ternyata di luar gelap. Berarti hari sudah malam. Dalam sekejapan itu, otaknya bekerja keras. Dan teringatlah kakek ini kalau setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia duduk di kursi dan memejamkan mata. Jadi, rupanya dia tertidur.
"Keparat..!" Amarah Brajageni meluap begitu melihat Eyang Sawung tidak mengambilkan pesanannya, tapi malah celingukan. Kakinya pun bergerak menendang.
Krakkk..! Terdengar suara berderak keras ketika kaki salah satu kursi patah terkena tendangan laki-laki tinggi kurus itu. Tak pelak lagi, kursi itu pun oleng. Dan karuan saja hal itu membuat Eyang Sawung semakin gelagapan, kaget.
"Bandot tua...!" tanpa peduli kalau Eyang Sawung belum sadar sepenuhnya, Brajageni mencekal leher baju kakek itu dan mengangkatnya ke atas. "Jangan main-main denganku! Bagaimana dengan pesananku?! Cepat sebelum kupuntir batang lehermu!"
"Ppp..., pe..., pesanan apa...?" tanya kakek berkulit hitam terputus-putus. Dahinya berkernyit dalam seperti tengah mengingat-ingat sesuatu.
Brajageni yang memang pemarah, tidak sabar lagi. Tangannya langsung bergerak. Tapi sebelum mengenai sasaran, Eyang Sawung telah keburu teringat.
"Ah, ya...! Aku ingat sekarang...! Keris, kan?!"
Brajageni menurunkan tubuh kakek itu, seraya melepaskan leher baju laki-laki tua itu. "Ya! Bagaimana? Sudah selesai?!"
Eyang Sawung menganggukkan kepala, kemudian beranjak ke dalam. Sebentar kemudian dia sudah kembali lagi. Di tangan kakek berkulit hitam ini sudah tergenggam sebilah keris. "Ini keris pesananmu," kata Eyang Sawung sambil mengangsurkan keris di tangannya. "Sebuah senjata pusaka yang hebat."
Brajageni mengulurkan tangannya. Diambilnya keris yang diangsurkan kakek berkulit hitam itu, lalu perlahan-lahan dihunusnya. Tampak sebuah keris yang bilahnya berwarna hitam pekat. Laki-laki tinggi kurus ini mendekatkan keris itu ke kulitnya. Dahinya berkernyit ketika tidak merasaka akibat apa-apa. Sementara, Eyang Sawung yang melihat adanya kernyit di dahi
Brajageni jadi berdebar-debar hatinya. "Jangan coba-coba menipuku, Sawung!" ancam Brajageni. Keras, dan kasar suaranya. Sepasang matanya menatap penuh ancaman pada kakek berkulit hitam itu.
"Aku tidak mengerti maksudmu, Kisanak," jawab Eyang Sawung jujur.
"Keris ini tidak terbuat dari benda pesananku!"
Merah padam selebar wajah Eyang Sawung mendengar tuduhan itu. Betapa tidak? Sebab, setengah mati membuat keris itu, malah dituduh menipu!
"Jaga mulutmu, Kisanak! Seumur hidup, belum pernah aku menipu orang lain! Keris itu kubuat berdasarkan benda yang kau berikan padaku!"
Brajageni menatap wajah Eyang Sawung tajam-tajam, mencoba mencari kebenaran di wajah itu. Dan laki-laki tinggi kurus ini menghela napas berat tatkala menangkap adanya kesungguhan di sana. Jelas kalau kakek berwajah hitam itu tidak berbohong.
Beberapa saat lamanya Brajageni termenung. Dahi laki-laki tinggi kurus ini berkernyit, pertanda ada sesuatu yang dipikirkannya. Sesaat kemudian, kerut-kerut di dahinya lenyap. Dengan agak terburu-buru keris miliknya yang tergantung di bawah punggung dicabut dengan tangan kiri.
Sekarang di tangan Brajageni terdapat dua bilah keris. Keris yang terbuat dari benda langit berada di tangan kanan. Sementara keris miliknya berada di tangan kiri. Laki-laki tinggi kurus ini menatap kedua keris itu berganti-ganti, dengan senyum tersungging.
Kemudian perhatiannya dipusatkan pada kedua tangan. Setelah mengambil napas dalam-dalam, tenaga dalam di bawah pusarnya disalurkan ke arah kedua tangan. Sekejap kemudian sebuah aliran tenaga dalam mengalir ke kedua tangannya.
"Hih...!" Brajageni menggertakkan gigi, lalu keris yang berada di kedua tangannya diadu.
Tranggg...!
Bunga api seketika memercik ke udara begitu kedua keris itu berbenturan. Eyang Sawung yang semula tidak mengerti maksud orang bercaping itu memegang dua buah keris, kini paham. Rupanya, Brajageni ingin mencoba keampuhan keris pesanannya.
Sepasang mata Brajageni terpelalak lebar. Tampak keris yang berada di tangan kirinya punggal. Padahal, keris miliknya itu bukan keris sembarangan, melainkan sebuah keris pusaka yang ampuh. Tak diragukan lagi kalau keris yang berada di tangan kanannya itu terbuat dari benda langit!
"Bagaimana, Kisanak?!" tanya Eyang Sawung. Ada nada kemenangan dalam suaranya. Sekali lihat saja, kakek berkulit hitam itu tahu kalau keris yang punggal itu bukan keris sembarangan.
Sedangkan Brajageni sama sekali tidak menyahuti ucapan kakek itu. Benaknya tengah dipenuhi pertanyaan yang tidak mampu dijawab. Semua itu berpangkal dari keris yang terbuat dari benda langit ini. Laki-laki tinggi kurus ini tidak bisa menyangkal lagi. Jelas sudah kalau keris itu terbuat dari benda langit. Dan itu berarti Eyang Sawung tidak menipunya. Kakek pandai besi itu telah melakukan pekerjaannya dengan baik.
"Kau benar, Sawung," kata Brajageni pelan. Datar dan dingin suaranya. "Keris ini memang terbuat dari benda pesananku. Kau tahu, dari mana benda ini berasal?"
Eyang Sawung menggelengkan kepala. "Selama hidupku, belum pernah kutemukan benda seperti itu. Sebuah benda yang terbuat dari campuran logam-logam. Beberapa di antaranya sama sekali tidak kukenal. Entah, dari mana kau mendapatkannya... Ataukah... benda itu tidak berasal dari bumi?"
"Tepat. Benda itu jatuh dari langit. Jadi, namanya benda langit! Benda yang diperebutkan orang-orang rimba persilatan!" sahut Brajageni pelan tapi tajam.
"Ahhh...!" Eyang Sawung terperanjat.
"Kau tahu, Sawung. Apa yang terjadi jika mereka tahu, kalau keris yang terbuat dari benda langit ini ada di tanganku?" sambung Brajageni.
Meskipun Brajageni baru berbicara sampai di sini, namun Eyang Sawung sudah menduga kelanjutan ucapan laki-laki tinggi kurus itu. Kontan hati kakek ini berdebar tegang. Sudah bisa dirasakan, ada bahaya maut yang mengancamnya. Tapi, kakek berkulit hitam tetap bersikap tenang. Sejak pertama kali bertemu dan melihat sikap Brajageni. Eyang Sawung memang sudah bersiap untuk menerima kematian.
Brajageni rupanya memang tidak membutuhkan jawaban Eyang Sawung. Terbukti begitu kakek berkulit hitam itu sama sekali tidak menanggapi pertanyaannya, dia sama sekali tidak peduli. "Mereka semua akan memburuku untuk mendapatkan keris ini!" tandas Brajageni tajam. "Bila itu terjadi, ada dua buah pilihan. Aku atau mereka yang mati!"
Kembali Brajageni menghentikan ucapannya. Ditatapnya wajah Eyang Sawung dengan sinar mata mengandung ancaman. "Aku tidak mau hal itu terjadi. Maka sedapat mungkin akan kuusahakan untuk mencegah tersebarnya berita ini! Tapi sayang, ternyata sudah ada orang yang mengetahuinya! Maka sebelum orang itu menyebarluaskan, harus lebih dulu dibungkam mulutnya! Kau tahu siapa orang itu, Sawung?!"
Eyang Sawung tersenyum getir. Perlahan kepalanya terangguk. "Aku," kata kakek berkulit hitam itu, tenang.
"Tepat!" Brajageni tertawa bergelak. "Kau harus mati, Sawung!"
"Telah kuduga sebelumnya, Kisanak!" sahut Eyang Sawung mantap. Tak ada nada kegentaran dalam suaranya.
"Ha ha ha...!" Brajageni tertawa bergelak. Mendadak sekali tawa itu. Dan secara tiba-tiba pula, suara tawa itu terhenti. "Kau menjadi orang pertama yang akan mencicipi kehebatan keris ini, Sawung!"
Setelah berkata demikian, Brajageni melompat menerjang kakek pandai besi itu. Keris di tangannya meluncur deras ke arah dada, menimbulkan suara bersiutan nyaring. Sebenarnya Eyang Sawung memiliki ilmu silat. Tapi, kepandaian yang dimiliki hanya sekadarnya saja. Tenaga dalam yang dimilikinya pun hanya sedikit saja. Kakek pandai besi ini hanya memiliki tenaga luar yang besar. Dan itu tidak aneh, mengingat pekerjaan kakek berkulit hitam itu adalah pandai besi.
Sialnya, lawan yang menyerangnya adalah Brajageni. Seorang tokoh sesat yang memiliki kepandaian tinggi. Eyang Sawung berusaha semampunya untuk mengelak. Tapi....
Cappp...! Telak dan keras sekali keris itu menghunjam dada Eyang Sawung, sampai hampir ke gagangnya. Seketika Brajageni melepaskan pegangan pada keris. Sepasang mata kakek pandai besi ini terbelalak. Tubuhnya seketika ambruk ke tanah. Dia menggelepar, sesaat kemudian diam tidak bergerak lagi.
Bukan hanya Eyang Sawung yang membelalakkan sepasang matanya. Brajageni pun demikian juga. Sepasang matanya terbelalak karena melihat kejadian aneh yang terpampang di depannya. Begitu keris itu menancap di dada Eyang Sawung, sama sekali tidak ada darah yang keluar dari luka yang robek itu. Jangankan mengalir, menetes pun tidak! Saking terkejutnya, Brajageni tidak buru-buru menarik kembali keris itu. Jadi untuk beberapa saat lamanya, keris itu terhunjam di dada kakek pandai besi itu.
Kembali kejadian yang aneh terjadi. Entah dari bagian dada yang tertembus, atau dari bilah keris yang masih terhunjam, yang jelas dari situ keluar asap. Semula sedikit dan tipis saja, tapi lama kelamaan semakin banyak dan tebal. Melihat peristiwa yang sama sekali tidak diduga ini, tentu saja Brajageni terpukau. Tapi, hanya sesaat saja. Sekejap kemudian, dia sudah bisa bersikap biasa kembali. Dengan dahi berkernyit, diperhatikannya asap yang semakin menebal itu.
Tak lama kemudian, asap itu mulai menipis dan semakin sedikit. Sampai akhirnya, asap itu lenyap sama sekali. Dan begitu asap itu sirna, untuk yang kesekian kalinya sepasang mata Brajageni terbelalak. Betapa tidak? Tubuh Eyang Sawung yang terhunjam keris kini telah berubah kurus dan pucat. Tidak ada tanda-tanda darah yang keluar dari tubuh kakek pandai besi itu.
Brajageni memang seorang tokoh hitam yang kejam. Tidak ada kata ampun bagi orang yang berurusan dengannya. Sudah biasa baginya membunuh banyak orang sambil tertawa. Menyiksanya pun sudah merupakan kegemaran. Tapi melihat peristiwa kali ini, tak terasa bulu kuduknya merinding. Perasaan ngeri pun mencekam hatinya. Masih dengan perasaan ngeri, kerisnya dicabut. Beberapa saat lamanya, Brajageni menatap mayat itu. Kemudian, dia melesat cepat keluar rumah itu, menembus gelap dan heningnya malam.
* * * * * * * *
LIMA
Brajageni berlari cepat mengerahkan seluruh ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya. Kenyataan yang dihadapi benar-benar membingungkan hatinya. Melihat keampuhannya, tak dipungkiri lagi kalau keris itu benar terbuat dari benda langit. Tapi, kenapa tidak menunjukkan pengaruh lain seperti yang selama ini diketahuinya. Hal ini benar-benar membuatnya tidak mengerti.
Belum begitu jauh berlari, laki-laki bertubuh tinggi kurus ini terpaksa memperlambat langkahnya. Sekitar beberapa tombak di depan nampak berdiri sesosok tubuh. Menilik dari sikapnya, dapat diketahui kalau orang itu sengaja menghadang perjalanannya.
Brajageni menghentikan langkahnya ketika telah berjarak tiga tombak dari sosok yang menghadang perjalanannya. Dalam keremangan cahaya bulan di langit, dapat terlihat jelas sosok penghadang jalannya.
Sosok itu ternyata seorang laki-laki bertubuh pendek kekar. Pakaian tanpa lengan membungkus tubuhnya yang bulat. Usianya tak lebih dari tiga puluh lima tahun. Sebuah cambuk berwarna hitam seperti warna pakaiannya, tampak tergenggam di tangan.
"Cambuk Halilintar...," desis Brajageni. Perlahan saja suaranya. Tapi karena suasana malam yang hening, ucapan itu terdengar nyaring.
Berbeda dengan Brajageni, laki-laki pendek kekar yang berjuluk Cambuk Halilintar itu sama sekali tidak mengenal laki-laki tinggi kurus ini. "Kalau ingin selamat, serahkan keris itu padaku, Kisanak," ancam Cambuk Halilintar. Menilik dari sikap dan nada suaranya, Cambuk Halilintar yakin sekali kalau dirinya akan mengalahkan Brajageni.
"Hmh...!" Brajageni mendengus. Meskipun telah mengenal penghadangnya, dia sama sekali tidak merasa gentar. Orang yang berjuluk Cambuk Halilintar ini memang terkenal sebagai tokoh sesat yang memiliki kesaktian cukup tinggi. "Apa maksudmu, Cambuk Halilintar? Aku sama sekali tidak mengerti," sahut Brajageni berpura-pura.
"Kau ingin menyerahkannya baik-baik, atau..., ingin aku merampasnya dengan kekerasan?!" ancam Cambuk Halilintar. Sama sekali tidak dipedulikan jawaban Brajageni tadi. "Perlu kau tahu, Kisanak. Aku telah mengetahui semuanya sejak kau ribut-ribut dengan Eyang Sawung. Itulah sebabnya, aku mencegat di sini. Karena aku tahu kau akan melalui jalan ini"
Mendengar ucapan ini Brajageni sadar kalau tidak ada gunanya lagi berpura-pura. Yang harus dilakukannya adalah membungkam mulut Cambuk Halilintar selama-lamanya. Kalau tidak, kemungkinan besar berita mengenai keris yang berasal dari benda langit ini akan tersebar luas. Dan yang pasti, akan banyak tokoh persilatan yang datang untuk memperebutkannya.
Maka jika hal itu terjadi, Brajageni yakin kalau dirinya tidak akan sanggup mempertahankannya. Tanpa ragu-ragu lagi, Brajageni segera mencabut keris yang berasal dari benda langit itu. Dan secepat keris itu tercabut, secepat itu pula ditusukkan ke arah dada Cambuk Halilintar.
Singgg...!
Suara berdesing Nyaring mengiringi tibanya serangan itu. Cambuk Halilintar seketika terperanjat. Sungguh tidak disangka kalau serangan lawan begitu dahsyat. Dan ini benar-benar di luar dugaan. Maka, laki-laki bertubuh pendek kekar ini langsung bersikap waspada, karena baru merasakan kedahsyatan serangan lawan. Dengan agak gugup dan terburu-buru dia mengelak, melempar tubuh ke belakang lalu bersalto beberapa kali di udara.
Tapi Brajageni sama sekali tidak memberinya kesempatan. Begitu lawannya melempar tubuh ke belakang, segera dikejarnya. Keris di tangannya ditusukkan bertubi-tubi ke berbagai bagian tubuh Cambuk Halilintar yang mematikan. Dan begitu kedua kaki Cambuk Halilintar mendarat di tanah, serangan Brajageni telah mengancamnya. Meskipun begitu, Cambuk Halilintar mampu juga membuktikan kelihaiannya. Sebelum serangan keris itu tiba, cambuk di tangannya telah lebih dulu bergerak.
Darrr...! Ledakan keras terdengar, begitu laki-laki pendek kekar ini melecutkan cambuknya. Dan seiring ledakan itu, ujung cambuk itu meluncur cepat ke arah ubun-ubun Brajageni. Hebat dan berbahaya bukan main serangan cambuk ini. Jangankan ubun-ubun yang merupakan jalan darah kematian manusia. Bahkan batu karang yang paling keras pun akan hancur bila terkena lecutan ini.
Brajageni tentu saja mengenal serangan berbahaya ini. Maka segera serangannya diurungkan. Tidak hanya itu saja yang dilakukan laki-laki tinggi kurus ini. Sambil membatalkan serangan, Brajageni melempar tubuhnya ke samping, lalu bergulingan di tanah.
Cambuk Halilintar yang kini telah mengetahui kalau lawan di hadapannya bukan tokoh sembarangan, tidak ragu-ragu lagi mengeluarkan seluruh ilmu yang dimiliki. Sadar akan kelebihan jangkauan senjatanya, maka begitu lawan menjauhkan diri, dia segera memburu. Cambuk di tangannya meledak-ledak di udara mencari sasaran. Sesaat kemudian, terjadilah pertarungan sengit antara kedua orang itu.
Di jurus-jurus awal, pertarungan berlangsung menarik dan seru. Masing-masing pihak mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Suara mendesing nyaring dari keris Brajageni, dan suara ledakan cambuk dari Cambuk Halilintar menyemaraki pertarungan.
Begitu pertarungan menginjak jurus ketiga puluh, mulai tampak keunggulan Brajageni. Kalau dibandingkan, laki-laki tinggi kurus ini memang masih lebih unggul daripada Cambuk Halilintar. Baik dalam hal ilmu meringankan tubuh, maupun ilmu tenaga dalam.
Hanya saja karena Cambuk Halilintar menggunakan cambuk, keunggulan Brajageni dalam hal tenaga dapat tertandingi. Benturan antara cambuk dengan keris, sukar terjadi seperti beradunya keris dan pedang. Itulah yang menyebabkan sampai sekian lama, Brajageni belum mampu mendesak lawannya. Dan hal ini tentu saja membuat laki-laki tinggi kurus itu merasa penasaran bukan main.
Sebagai akibatnya, serangan-serangannya pun jadi semakin dahsyat. Satu hal lagi yang menyulitkan Brajageni mendesak Cambuk Halilintar adalah jangkauan senjata lawan yang jauh lebih panjang ketimbang senjatanya. Tambahan lagi, Cambuk Halilintar ternyata tahu kelebihannya dalam hal jangkauan serangan. Maka laki-laki pendek kekar itu selalu mengajak bertanding jarak jauh.
Brajageni tentu saja tidak mau bertindak bodoh. Sedapat mungkin diusahakan agar pertarungan dapat terjadi dalam jarak dekat. Maka yang terjadi adalah pertarungan yang kurang menarik. Di satu pihak, Brajageni berusaha keras mengajak lawan bertarung jarak dekat dan di lain pihak, Cambuk Halilintar berusaha keras agar pertarungan dapat berlangsung jarak jauh.
Itulah sebabnya, mengapa laki-laki bertubuh pendek kekar ini selalu melompat ke belakang untuk menjaga jarak setiap kali lawan mendesak. Tak lupa, dikirimkannya serangan lecutan-lecutan cambuk, untuk menahan desakan Brajageni. Hasilnya, begitu memasuki jurus kelima puluh, pertarungan berlangsung tidak menarik. Mereka berdua seperti tidak bertarung, tapi bermain kejar-kejaran.
Brajageni di pihak pengejar, sedangkan Cambuk Halilintar pihak yang diburu. Karena Cambuk Halilintar bertarung sambil mundur, maka sedikit demi sedikit pertarungan berpindah tempat. Sehingga tanpa disadari, begitu pertarungan menginjak jurus ketujuh puluh, pertarungan sudah bergeser jauh dari tempat semula.
Brajageni menggertakkan gigi. Perasaan cemas mulai menggayut di dadanya. Dia khawatir kalau pertarungan ini akan menarik perhatian orang. Masih untung kalau bukan tokoh persilatan. Tapi kalau tidak? Celakalah dirinya! Cambuk Halilintar harus cepat dibereskan sebelum yang dikhawatirkan terjadi.
"Hih...!" Brajageni mengibaskan tangan kirinya. Seketika itu pula terdengar suara berdesir pelan. Dan dalam keremangan sinar rembulan, tampak benda-benda kecil berwarna hitam melesat cepat ke arah Cambuk Halilintar.
Laki-laki bertubuh pendek kekar ini terperanjat. Meskipun hanya samar-samar, tapi bisa diduga kalau benda yang menuju ke arahnya pasti jarum yang mengandung racun ganas! Cambuk Halilintar tidak berani bertindak ceroboh. Cepat bagai kilat tubuhnya dilempar ke belakang dan bersalto beberapa kali di udara. Maka jarum-jarum itu hanya mengenai tempat kosong.
Tapi hal itu sudah diperhitungkan Brajageni. Maka begitu lawannya meloloskan diri, tangannya kembali mengibas. Lagi-lagi terdengar suara berdesir halus ketika jarum-jarum beracunnya meluncur cepat menuju sasaran. Tidak hanya itu saja yang dilakukan laki-laki bertubuh tinggi kurus itu. Dia juga langsung melompat menyusul, melakukan serangan dengan kerisnya.
Cambuk Halilintar terkejut bukan kepalang. Serangan kali ini ternyata jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Karena di samping serangan itu tiba di saat tubuhnya tengah berada di udara, serangan lain pun datang menyusul.
"Hup!" Begitu laki-laki bertubuh pendek kekar ini mendaratkan kedua kakinya di tanah, serangan jarum-jarum beracun itu telah menyambar dekat. Maka sebisa-bisanya cambuknya digerakkan.
Darrr, darrr...!
Hebat bukan main permainan cambuk laki-laki bertubuh pendek kekar ini. Meskipun dalam keadaan yang sangat sulit, masih mampu membuktikan kalau julukan Cambuk Halilintar yang disandangnya bukan sekadar julukan kosong. Nyatanya semua jarum beracun itu tersampok runtuh. Tapi sebelum Cambuk Halilintar sempat berbuat sesuatu, serangan susulan dari Brajageni telah menyambar tiba. Keris di tangan laki-laki bertubuh tinggi kurus itu meluncur cepat ke arah perutnya.
Cappp...!
"Aaakh...!" Cambuk Halilintar menjerit keras. Keris itu menghunjam sampai ke gagang. Dan kejadian seperti sebelumnya pun kembali terulang. Asap yang mula-mula tipis dan sedikit, kemudian menebal dan banyak. Sampai akhirnya, asap itu sirna dan muncul kembali. Dan begitu asap itu benar-benar lenyap, tubuh Cambuk Halilintar yang telah menjadi kurus kering karena kehabisan darah, ambruk ke tanah dengan nyawa melayang.
Brajageni terpaku. Kini baru disadari kalau kejadian yang menimpa Empu Sawung akibat keris yang terbuat dari benda langit itu. Hanya yang menjadi tanda tanya, ke mana perginya darah Empu Sawung dan Cambuk Halilintar? Dengan benak masih dipenuhi tanda tanya, Brajageni memasukkan keris itu ke sarungnya. Tapi, gerakannya terhenti di udara. Dia merasa seperti ada hawa yang cukup dingin menghembus kulitnya, berasal dari bilah keris itu.
Dahi Brajageni seketika berkernyit. Tadi pun, sehabis membunuh Empu Sawung, ada hawa cukup dingin yang menghembus kulitnya begitu keris itu akan dimasukkan ke sarungnya. Tapi Brajageni buru-buru mengusir pikiran yang menggelayuti benaknya. Dia khawatir, kalau berlama-lama di sini, bukan tidak mungkin akan ada tokoh persilatan lain yang datang kemari. Masih untung kalau menang. Kalau kalah? Itulah sebabnya, meskipun dengan benak yang masih dipenuhi berbagai macam pertanyaan yang bergolak, laki-laki tinggi kurus ini bergerak cepat meninggalkan tempat itu.
* * * * * * * *
Entah sudah berapa lama dan berapa jauh berlari, Brajageni tidak mempedulikannya. Yang diketahui cuma satu. Dirinya telah berada di dalam Hutan Dadap, menembus tempat yang jarang didatangi orang. Brajageni terus berlari, meskipun malam telah mulai berlalu. Dini hari telah mulai datang. Ayam jantan mulai berkokok bersahut-sahutan. Sebentar lagi, matahari akan menerangi mayapada.
Laki-laki bertubuh tinggi kurus itu baru memperlambat larinya, tatkala pandangan matanya tertumbuk pada sebatang pohon beringin yang tinggi, dikelilingi pepohonan dan semak-semak lebat. Brajageni menghentikan langkah ketika jaraknya dengan pohon beringin itu tinggal dua tombak lagi.
Pohon itu besar sekali, berukuran lebih dari empat pelukan tangan orang dewasa. Ada satu keanehan pada pohon itu. Di bagian bawah batangnya terdapat sebuah lubang berbentuk setengah lingkaran. Dan tanpa ragu-ragu, Brajageni melangkah menghampirinya. Baru juga melangkah beberapa tindak, dari dalam pohon itu melesat sesosok bayangan yang langsung melancarkan serangan bertubi-tubi ke dada, ulu hati, dan pusar Brajageni.
Brajageni terkejut bukan main. Apalagi begitu merasakan hembusan angin kuat yang menyambar sebelum serangan tiba. Karena mengelak sudah tidak memungkinkan lagi, maka diputuskan untuk menangkisnya. Tahu akan kedahsyatan serangan itu, laki-laki tinggi kurus ini mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk menangkis.
Plak, plak, plak...!
Benturan keras terdengar berkali-kali begitu sepasang tangan yang sama-sama mengandung tenaga dalam penuh beradu. Akibatnya, tubuh Brajageni terjengkang ke belakang. Kedua tangannya dirasakan seperti patah-patah. Bahkan dadanya pun terasa sesak bukan main. Terdengar suara berdebuk keras ketika tubuh Brajageni terjatuh di tanah. Dari seringai yang nampak di wajahnya, dapat diketahui kalau dia merasa kesakitan.
Dengan pandangan mata nanar, Brajageni menatap penyerangnya. Dalam keremangan malam yang telah berganti dini hari, samar-samar dapat terlihat wajah dan potongan tubuh sosok yang ternyata seorang kakek bertubuh sedang mengenakan pakaian serba merah. Kumis dan jenggotnya nampak hitam. Tapi anehnya, kulit wajahnya putih sekali, seperti kapur.
"Hm…!" Kakek bermuka putih itu mendengus. Kedua tangannya dengan jari-jari terbuka, nampak bersilang di depan dada. Lalu perlahan-lahan jari-jari tangannya mengepal, menimbulkan suara berkerotokan keras. Wajah Brajageni pucat pasi begitu melihat gerakan kakek bermuka putih.
"Guru...! Tahan...!" teriak laki-laki bertubuh tinggi kurus, keras. Nada suaranya terdengar agak bergetar, karena dilanda perasaan tegang dan takut yang menggelegak.
Seketika itu juga jari-jari tangan kakek bermuka putih yang semula sudah mengepal keras, mengendur mendadak. "Apa katamu?!" seru kakek bermuka putih. Wajah dan suaranya menyiratkan perasaan kaget yang amat sangat. "Siapa kau sebenarnya?!"
"Aku Brajageni, Guru," sahut laki-laki bertubuh tinggi kurus cepat. "Lupakah Guru padaku?"
"Brajageni?!"
"Benar, Guru," Brajageni menganggukkan kepala. "Begitu berubahkah wajahku sehingga Guru sampai tidak mengenalku lagi. Dan bahkan hampir saja membunuhku."
"Kunyuk!" umpat kakek bermuka kurus itu. "Bagaimana aku bisa mengenalmu, kalau wajahmu disembunyikan seperti itu?!"
Brajageni tersentak. Betapa bodohnya dia! Pantas saja gurunya sama sekali tidak mengenali. Ternyata caping dan kain yang menutup wajahnya belum ditanggalkan. Maka buru-buru penyamarannya ditanggalkan.
"Kau mengagetkan aku saja, Brajageni," desah kakek muka putih itu setelah menyaksikan sendiri kalau orang bercaping itu benar muridnya. "Semula aku merasa heran melihat racunku sama sekali tidak bekerja. Tapi kini, semuanya telah menjadi jelas."
Brajageni hanya bisa tersenyum. Gurunya ini memang berwatak telengas. Dalam setiap serangan, racunnya tak pernah ketinggalan. Dan lagi, racun-racunnya pasti memiliki akibat yang menggiriskan. Hal itu sebenarnya tidak aneh. Karena, kakek bermuka putih itu berjuluk Raja Racun Muka Putih!
"Jelaskan, mengapa kau sampai melakukan penyamaran seperti ini, Brajageni?" pinta kakek bermuka putih, pelan. Ada tuntutan yang besar dalam nada suaranya.
"Terpaksa, Guru. Aku kini membawa keris yang terbuat dari benda langit. Kalau wajahku kutampilkan, maka seluruh tokoh persilatan pasti akan mengejarku. Dan tentu aku bisa celaka, Guru."
Kemarahan yang melanda hati Raja Racun Muka Putih langsung sirna, berganti perasaan kaget yang bergelora. Kepalanya menoleh ke sana kemari sebentar. "Masuk...," ujar Raja Racun Muka Putih seraya melangkah memasuki lubang yang terdapat di batang pohon.
Dengan agak bergegas, Brajageni melangkah di belakang gurunya. Laki-laki bertubuh tinggi kurus ini tahu, di dalam pohon besar inilah tempat tinggal Raja Racun Muka Putih. Sebuah tempat yang agak sulit untuk diketahui orang lain. Siapa yang menyangka kalau sebenarnya bagian dalam pohon itu tak ubahnya bagian dalam rumah pada umumnya?
* * * * * * * *
"Mana keris yang kau katakan itu, Brajageni?" tagih Raja Racun Muka Putih tatkala mereka berdua telah duduk di dalam.
Brajageni segera mengambil keris yang terselip di belakang tubuhnya, lalu menyerahkan pada gurunya. Kakek bermuka putih mengulurkan tangan menerima. Diawasinya sejenak benda itu, sebelum akhirnya dihunus perlahan-lahan. Sepasang matanya merayapi sekujur bilah keris yang terbuat dari benda langit, kemudian memasukkannya kembali lambat-lambat.
"Ceritakan dengan jelas, bagaimana kau bisa mendapatkan benda langit itu. Karena sepengetahuanku, hanya Dewa Arak dan kawan wanitanya saja yang berhasil keluar dari Hutan Bandan dalam keadaan hidup. Dan sepatutnya, dialah yang mendapatkan benda itu. Tapi ternyata tidak. Benda langit itu lenyap, seiring lenyapnya peristiwa yang menggegerkan hutan itu." (Untuk lebih jelasnya silakan baca serial Dewa Arak dalam episode Prahara Hutan Bandan).
"Semua ucapanmu betul, Guru," sahut Brajageni membenarkan. "Tapi ternyata ada tokoh yang kita lupakan. Eyang Aji Ranta, namanya. Dan ternyata Dewa Arak menyerahkan benda langit itu kepadanya."
"Hm...," Raja Racun Muka Putih hanya menggumam pelan.
"Itu pun kuketahui setelah beberapa waktu lamanya, Guru," sambung Brajageni. "Dan begitu kucari, kakek itu ternyata telah tidak berada lagi di situ. Eyang Aji Ranta telah pindah ke Hutan Dadap. Maka segera kususun rencana untuk mendapatkan benda itu. Karena aku merasa bila menghadapi secara terang-terangan tidak mungkin menang. Terpaksa dia kulawan dengan siasatku."
Brajageni menghentikan ceritanya sejenak, untuk mengambil napas.
"Waktu itu, kuperintahkan seorang kepala rampok yang pernah kutolong dari tangan maut seorang pendekar untuk melaksanakan rencanaku. Seorang anak buahnya yang kuberi pakaian prajurit kulukai dengan racun ganas, dan kubuang di dekat Desa Pucung. Semuanya berjalan lancar sesuai rencana. Dia ditemukan penduduk desa, dan segera dibawa ke rumah Ki Waskita, dukun ampuh desa itu."
Kembali Brajageni menghentikan ceritanya untuk mengambil napas seraya mencari kata-kata yang tepat untuk melanjutkan ceritanya.
"Dan seperti yang sudah kuduga, Ki Waskita tidak mampu menyembuhkan luka itu. Atas desakan orang yang kuracun, Ki Waskita kemudian menyuruh dua orang penduduk untuk meminta bantuan Eyang Aji Ranta. Kakek itu memang dikenal sebagai orang yang ahli mengobati penyakit akibat racun," lanjut laki-laki bertubuh tinggi kurus itu. "Tak lama setelah utusan itu pergi, orang yang kulukai sembuh. Karena, dia kubekali obat penawar racunnya."
Raja Racun Muka Putih mengangguk-anggukkan kepala.
"Dan begitu Eyang Aji Ranta telah pergi untuk mengobati, rombongan perampok mengambil benda langit itu. Usaha mereka berhasil, lalu benda langit itu diserahkan padaku. Dan setelah itu, mereka semua kukirim ke akhirat."
"Ha ha ha...!" Tiba-tiba tawa Raja Racun Muka Putih meledak. Tampak jelas kalau hatinya gembira bukan main mendengar ucapan muridnya. Memang kakek ini memiliki sifat mengerikan. Gembira sekali jika mendengar penderitaan orang lain.
"Hm.... Lalu?" tanya kakek muka putih itu penuh gairah.
Brajageni lalu menceritakan semua kejadiannya. "Begitulah, Guru," ujar Brajageni menutup ceritanya. "Aku ingin menanyakan kepada Guru tentang hal-hal aneh pada keris ini."
Raja Racun Muka Putih tercenung sejenak. Dahinya berkernyit, seperti tengah berpikir keras. Brajageni tidak berani mengganggu. Dibiarkannya saja kakek muka putih itu berbuat demikian. Hanya sepasang matanya saja yang menatap tajam setiap gerak-gerik yang dilakukan Raja Racun Muka Putih. Setelah beberapa saat lamanya tercenung, Raja Racun Muka Putih menghunus kembali keris itu. Diperhatikannya baik-baik bilah keris yang berwarna hitam kelam itu.
"Aku akan memeriksanya dulu, Brajageni. Mungkin membutuhkan waktu beberapa hari. Dan selama itu, aku tidak mau diganggu. Kau mengerti?!"
"Mengerti, Guru," sahut Brajageni seraya menganggukkan kepala. "Aku pergi dulu."
* * * * * * * *
ENAM
"Hhh...!" Seorang pemuda berwajah tampan menghapus keringat yang membasahi wajahnya dengan punggung tangan. Kepalanya mendongak ke atas, menatap ke arah matahari yang berada di atas kepala. Sinarnya memancar dengan garang ke bumi. Pemuda itu berusia sekitar dua puluh satu tahun. Tubuhnya tegap berisi, terbungkus pakaian berwarna ungu. Sebuah guci arak terbuat dari perak tersampir di punggungnya.
Ada satu hal yang aneh pada diri pemuda berpakaian ungu ini. Rambutnya ternyata tidak berwarna hitam seperti layaknya yang terdapat pada pemuda umumnya, tapi berwarna putih. Rambutnya benar-benar seperti orang yang telah berusia tua, hanya saja warnanya lebih indah. Putih keperakan!
Langkah pemuda berambut putih keperakan ini berhenti ketika sepasang matanya tertumbuk pada sesosok tubuh hitam yang tergolek di tengah jalan. Bergegas, dihampirinya sosok yang tergolek itu. Sesaat kemudian, pemuda berambut putih keperakan ini telah berada di hadapan sosok hitam itu. Sekali lihat saja, dia tahu kalau sosok itu telah tidak bernyawa lagi.
Pemuda itu kemudian berjongkok, karena melihat mayat yang nampak aneh! Begitu mengenaskan, kurus kering, dan pucat pasi. Sepertinya seluruh darah di tubuhnya telah habis tanpa sisa. Sepasang mata pemuda berpakaian ungu itu kemudian beredar berkeliling. Di sekitar tempat itu tampak jarum-jarum berserakan. Menilik dari warnanya, dapat diketahui kalau jarum-jarum itu mengandung racun.
Bukan hanya itu saja yang ditemukan pemuda berambut putih keperakan ini. Ternyata di situ juga tergeletak sebuah cambuk berwarna hitam pekat. Dan memang, mayat itu adalah mayat Cambuk Halilintar yang tewas di tangan Brajageni.
"Keadaan mayat ini sungguh mengerikan. Seluruh darah di tubuhnya habis. Tapi anehnya, tidak ada bercak-bercak darah di tanah. Ke manakah perginya darah orang ini?" gumam pemuda berambut putih keperakan dengan perasaan bingung. "Padahal melihat luka di perutnya, jelas kalau orang ini tertusuk senjata tajam."
Tapi walau pemuda berpakaian ungu ini telah memutar otaknya untuk mencari-cari jawaban, dia tak juga menemukannya. Sebaliknya, dia justru kepusingan. Sadar kalau tidak akan menemukan jawabannya, pemuda berambut putih keperakan ini menghentikan pemikirannya.
Pemuda itu kemudian bangkit, dan melangkahkan kakinya menghampiri sebuah tempat yang terlindung. Diambilnya sebatang kayu yang cukup kuat. Lalu dengan kayu itu, digalinya tanah. Menakjubkan! Hanya menggunakan sebatang kayu, pemuda itu membuat sebuah lubang berbentuk persegi panjang yang cukup besar. Dan dengan waktu yang cukup singkat pula, pekerjaannya diselesaikan.
Tidak lebih lambat dari orang-orang yang terbiasa bekerja kasar membuat lubang menggunakan cangkul. Ketika sebuah lubang terbuat, pemuda berambut putih keperakan itu lalu menyeret mayat Cambuk Hatitintar. Dan dimasukkannya mayat itu ke dalam lubang, kemudian ditimbunnya dengan tanah. Baru setelah semuanya selesai, pemuda itu melanjutkan langkahnya kembali.
Kini pemuda berambut putih keperakan itu tidak melangkah pelan seperti sebelumnya, tapi bergerak mempergunakan ilmu meringankan tubuh. Dalam sekali langkah saja, tubuhnya sudah melesat sebelas tombak. Luar biasa! Pemuda berambut putih keperakan itu terus berlari cepat. Kini sinar matahari yang terik dan menyengat tidak dirasakan lagi olehnya. Dan tak lama kemudian, dia telah melihat tembok batas sebuah desa. Maka pemakaian ilmu meringankan tubuhnya dihentikan. Kemudian, kakinya melangkah seperti biasa.
Dengan langkah tenang, pemuda berambut putih keperakan itu melangkah memasuki mulut desa itu. Tak dipedulikannya pandangan mata keheranan dari penduduk desa yang melihat keadaan rambutnya yang menyolok. Langkahnya tetap tenang ketika memasuki sebuah kedai. Sesaat pemuda berambut putih keperakan itu menatap ke sekeliling. Kedai ini tampak kecil saja, dan kebetulan tengah kosong. Dia pun memilih satu di antara beberapa meja yang ada di dalamnya.
Seorang laki-laki setengah tua bermuka codet, bergegas menghampiri. Rupanya, dialah pemilik kedai ini. "Mau pesan apa, Den?" tanya laki-laki bermuka codet itu. Pelan dan sopan suaranya.
"Berikan aku seguci besar arak," sahut pemuda berambut putih keperakan itu.
Pemilik kedai itu bergegas kembali ke dalam. Tak lama kemudian, dia sudah kembali sambil membawa seguci besar arak, berikut sebuah gelas bambu. Dan setelah meletakkannya di meja pemuda itu, laki-laki bermuka codet itu bergegas kembali.
Pemuda berambut putih keperakan itu lalu menjumput guci arak yang tersampir di punggungnya, kemudian meletakkannya di atas meja. Perlahan guci arak pesanannya diangkat dengan enaknya. Seolah-olah yang diangkat hanya sebuah benda ringan saja. Suara bercegukan terdengar ketika arak di guci besar itu dituang ke guci arak perak yang bentuknya jauh lebih kecil. Tak lama kemudian, guci perak itu sudah penuh.
Kini pemuda berambut putih keperakan itu menuangkan arak ke dalam gelas bambu. Sesaat kemudian, dia sudah menikmati minumannya. Entah sudah berapa gelas arak yang masuk ke perutnya. Mendadak, pemuda berpakaian ungu itu menghentikan minumnya sejenak. Pendengarannya yang tajam menangkap adanya banyak langkah kaki ringan di luar kedai. Paling tidak pemilik langkah-langkah itu cukup berisi juga. Seketika, dia bersikap waspada.
Meskipun begitu, pemuda berambut putih keperakan itu tetap berlaku tenang. Kembali gelas bambunya diangkat, untuk meneruskan minumnya. Dia bersikap seolah-olah tidak tahu akan kehadiran orang-orang di depan pintu kedai. Tapi pendengarannya dipasang setajam mungkin, bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi.
Dengan sudut matanya, pemuda berambut putih keperakan itu melihat dua sosok tubuh yang melangkah memasuki pintu kedai, kemudian menghampiri tempat duduknya. Langkah mereka berhenti tepat di sebelah meja pemuda itu. Mau tak mau, pemuda berpakaian ungu itu menghentikan minumnya. Kepalanya mendongak menatap ke arah empat orang yang juga tengah menatapnya.
"Semula aku tidak percaya ketika mendengar kalau desa ini kedatangan orang aneh. Pemuda berambut putih keperakan menyandang guci, dan berpakaian ungu. Tapi ternyata berita itu benar. Sungguh tidak kusangka kalau orang sepertimu sudi datang ke desa ini, Dewa Arak!" kata seorang laki-laki berusia sekitar empat puluh tahun. Tubuhnya tinggi kurus dan berpakaian putih. Kumis dan jenggotnya masih berwarna hitam. Tapi rambut di bagian pelipisnya telah bercampur warna putih. "Kenalkan, aku Ki Jayus! Kepala Desa Pucung!"
Setelah berkata begitu, laki-laki berpakaian putih ini mengulurkan tangan pada pemuda berambut putih keperakan. Pemuda berpakaian ungu yang memang Dewa Arak alias Arya Buana tersenyum. Disambutnya uluran tangan kepala desa itu, lalu dijabatnya erat-erat.
"Kau terlalu berlebih-lebihan, Ki. Panggil saja aku Arya," sahut Dewa Arak. Risih hatinya melihat sikap kepala desa itu yang terlalu berlebih-lebihan.
"Dan ini Wikalpa! Guru silat kenamaan Desa Pucung!" ujar Ki Jayus lagi seraya melepaskan genggaman tangannya, memperkenalkan orang yang berada di sebelahnya.
Dia adalah seorang laki-laki bertubuh tinggi kurus, berusia sekitar empat puluh lima tahun. Pakaiannya hitam. Kumis dan jenggot jarang-jarang menghias wajahnya. Arya mengulurkan tangannya, tapi Wikalpa sama sekali tidak menyambutnya. Bahkan, sebaliknya malah tersenyum mengejek. Terpaksa walau dengan muka merah, Dewa Arak menarik kembali tangannya.
"Memang sifatnya begitu, De... eh! Arya," Ki Jayus cepat-cepat menengahi keadaan yang tidak enak itu. "Tapi, percayalah. Hatinya sangat baik."
Dewa Arak hanya menganggukkan kepala, tidak menyahuti ucapan Kepala Desa Pucung itu.
"Sayang sekali kami tidak bisa menemanimu minum, Arya. Kami mempunyai sebuah urusan penting tentang Empu Sawung. Pandai besi desa kami itu telah tewas semalam. Keadaan mayatnya mengerikan sekali. Kurus kering dan pucat pasi seperti kehabisan darah...!"
Setelah berbasa-basi sebentar, Ki Jayus melangkah meninggalkan tempat itu. Wikalpa pun mengikuti di belakangnya, meninggalkan Dewa Arak yang tengah tercenung kaget. Jadi, masih ada lagi korban dengan tubuh kurus kering kehabisan darah? Kalau begitu, di desa ini tengah terjadi sesuatu. Dewa Arak bertekad dalam hati untuk mencoba mengungkap rahasia pembunuhan yang penuh teka-teki itu. Makanya dia memutuskan untuk tinggal di sini sementara waktu.
Setelah menyelesaikan minum dan membayar pesanannya, Arya melangkah meninggalkan tempat itu. Kini tidak ada Melati di sampingnya. Gadis berpakaian putih itu, sudah kembali ke Kerajaan Bojong Gading. Kerusuhan masih saja terjadi di sana, karena ada dugaan Kerajaan Bojong Gading sedang lemah akibat pemberontakan Adipati Tasik.
* * * * * * * *
Waktu berlalu tanpa disadari. Terkadang cepat laksana anak panah lepas dari busur. Tapi kadang pula merayap seperti seekor keong. Tak terasa tiga hari telah berlalu, sejak Brajageni menyerahkan keris pada gurunya. Dia memang selalu menunggu, sehingga terasa membosankan.
"Bagaimana, Guru?" tanya Brajageni begitu datang menagih janji gurunya.
"Keris ini akan menjadi senjata luar biasa, Brajageni," jelas Raja Racun Muka Putih.
"Maksud, Guru?" tanya Brajageni ingin tahu.
"Begitu mendengar ceritamu tentang keanehan keris ini, aku lalu memeriksanya. Dan hasil yang kudapatkan, begitu mengejutkan!"
"Apa itu, Guru?" Brajageni mulai bergairah.
"Keris ini adalah keris peminum darah, Brajageni," sahut kakek muka putih itu.
"Maksud, Guru?"
"Setiap kali ditusukkan ke tubuh lawan, keris ini akan menghisap darahnya."
"Ahhh...!" Brajageni terperanjat.
"Setiap kali meminum darah, keris ini akan mendapat sebuah kekuatan menggiriskan," sambung Raja Racun Muka Putih, tanpa mempedulikan keterkejutan muridnya.
"Kekuatan apa itu, Guru?"
"Hanya satu yang baru kuketahui, Brajageni," jawab Raja Racun Muka Putih bernada mengeluh.
"Apa itu, Guru?" meskipun hatinya agak kecewa mendengar gurunya hanya mengetahui satu, tapi Brajageni tak bisa menahan rasa keingintahuannya.
"Hawa dingin yang luar biasa!"
"Tapi kenyataannya tidak demikian, Guru," bantah Brajageni ketika teringat pada salah seorang korban keris itu.
Raja Racun Muka Putih mendengus. Dia sudah tahu, mengapa laki-laki tinggi kurus itu berkata demikian. "Darah yang diminumnya, tidak cukup untuk menimbulkan pengaruh sampai seperti itu," selak kakek bermuka putih itu. "Itulah sebabnya, hanya angin dingin biasa yang menghembus kulitmu."
"Jadi, maksud guru...?"
"Keris itu membutuhkan darah yang lebih banyak, Brajageni. Dan juga, selama keris itu belum menunjukkan hasil yang diharapkan, jangan dipisahkan dari darah!"
"Memangnya kenapa kalau dipisahkan, Guru?" tanya Brajageni ingin tahu, meskipun sebenarnya sudah bisa menduga.
"Kekuatan yang timbul itu akan kembali lenyap...."
Brajageni mengangguk-anggukkan kepala. Semua yang dikatakan gurunya benar-benar masuk akal. "Kesimpulannya..., keris itu harus direndam dalam darah. Begitu kan, Guru?"
"Tepat!" jawab Raja Racun Muka Putih cepat. "Dan setelah itu, kita akan membuktikan keampuhan senjata ini!"
"Kalau begitu, malam ini juga aku akan mulai bergerak, Guru."
Raja Racun Muka Putih sama sekali tidak menyahut. Hanya bibir atasnya saja yang bergerak sedikit, pertanda menanggapi ucapan muridnya. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Brajageni segera melesat cepat meningalkan tempat itu.
* * * * * * * *
Tong tong, tong...! Bunyi kentongan terdengar mengiringi langkah dua orang peronda, yang berjalan mengelilingi wilayah Desa Pucung. Kedua orang ini tak lain dari Rakapitu dan Gibang.
"Rakapitu..."
Laki-laki bertubuh tinggi besar itu menoleh. "Ada apa, Gibang?" tanya Rakapitu.
Gibang terdiam sesaat, nampak kalau merasa ragu-ragu untuk berbicara. Karuan saja hal ini membuat rekannya kesal. Untung, sebelum laki-laki tinggi besar itu memuntahkan kekesalannya, Gibang telah terlebih dulu membuka suara.
"Kau tidak merasa ada keanehan malam ini, Rakapitu?"
"Kau ini bicara apa, sih?!" Rakapitu malah balik bertanya. Nada suaranya menyiratkan kekesalan. Rupanya, dia tengah tidak mau diganggu.
"Dengar dulu, Rakapitu," sahut Gibang cepat. "Aku belum selesai bicara!"
Rakapitu pun menghentikan ucapannya. Tangannya yang memegang kentongan kembali bekerja.
Tong, tong, tong...! Bunyi kentongan itu terdengar nyaring menembus kesunyian malam yang mencekam.
"Malam ini perasaanku tidak enak sekali, Rakapitu," keluh Gibang setelah suara kentongan itu lenyap. "Bahkan bulu kudukku sampai berdiri."
"Hm.... Lalu?" tanya Rakapitu dengan suara sumbang, seperti dilanda ketegangan.
Memang sebenarnya, dia sejak tadi dicekam perasaan tidak enak dan rasa takut yang aneh. Itulah sebabnya, laki-laki tinggi besar ini jadi agak kesal ketika Gibang membuka pembicaraan seperti itu. Akibatnya, rasa takutnya semakin besar melanda hatinya.
"Perasaanku..., ada sesuatu yang akan terjadi..," sambung Gibang pelan, lebih mirip bisikan.
Belum juga laki-laki berwajah penuh tahi lalat ini menutup mulut, pandangan matanya menangkap adanya sosok serba hitam tak jauh di depan mereka. Sosok serba hitam itu berjarak sekitar lima tombak dengan mereka. Hati Rakapitu dan Gibang tercekat. Apalagi ketika menyadari kalau kini mereka tengah berada di tempat yang agak jauh dari rumah-rumah penduduk.
Rakapitu dan Gibang sudah bisa memperkirakan kalau sosok serba hitam itu mempunyai maksud buruk. Tanpa ragu-ragu lagi, Gibang segera memindahkan obornya ke tangan kiri. Sementara tangan kanannya cepat bergerak ke arah pinggang.
Srattt..!
Sinar terang berpendar ketika golok itu keluar dari sarung. Sementara Rakapitu masih tetap belum bertindak apa-apa. Hanya sepasang matanya saja yang menatap sosok serba hitam itu penuh selidik. Di tangan kanannya tetap tergenggam kentongan. Dalam keremangan sinar bulan, tampak sosok hitam itu memang berniat menghadang mereka.
Sosok bertubuh tinggi kurus. Pakaiannya serba hitam. Wajahnya terturup kain hitam mulai dari bawah mata. Bukan itu saja. Kepalanya pun terbungkus sebuah caping bambu. Memang tidak ada yang menyangka kalau sosok di balik semua itu adalah Brajageni. Namun siapa pun orangnya, Rakapitu dan Gibang harus bersikap waspada.
"Siapa kau?!" tanya Gibang agak keras, dengan jantung berdetak kencang. Sikap dan dandanan orang ini menimbulkan kecurigaan di hatinya.
Namun bukan jawaban yang didapatkan Gibang. Tapi terjangan! Tanpa berkata-kata lagi, Brajageni segera melompat. Tangan kanannya yang berbentuk cakar meluncur deras ke arah dada.
Wuuut…!
Angin menderu keras mengiringi tibanya serangan Brajageni. Jelas, serangannya itu mengandung tenaga dalam tinggi. Hal ini tidak aneh, karena laki-laki bertubuh tinggi kurus ini telah mengerahkan seluruh tenaga dalam yang dimiliki. Gibang terkejut bukan main melihat kecepatan gerak lawannya. Dengan gugup, obor yang dipegang dilemparkan ke arah tubuh lawan yang tengah menuju ke arahnya.
Brajageni hanya mendengus. Terpaksa serangannya dibatalkan. Dan secepat itu pula tangannya dikibaskan ke arah obor yang tengah menyambarnya.
Takkk...! Suara berderak keras terdengar begitu batang obor itu hancur berkeping-keping.
"Hiaaat..!" Gibang berseru keras seraya melompat menerjang. Golok di tangannya menusuk cepat ke arah perut Brajageni. Rakapitu pun tak tinggal diam. Maka cepat dipukulnya kentongan berkali-kali.
Tong, tong, tong...!
Suara kentongan tanda bahaya pun terdengar. Dan sehabis memberi tanda, laki-laki tinggi besar ini mencabut golok untuk membantu rekannya yang tengah menghadapi Brajageni. Golok di tangannya membabat cepat ke arah leher.
Brajageni geram bukan kepalang melihat Rakapitu memukul kentongan tanda bahaya. Sudah dapat diperkirakan kalau tak lama lagi penduduk desa akan berdatangan. Dan dia tidak ingin masih berada di sini saat para penduduk datang. Bila hal itu terjadi, maka akan banyak penduduk yang menjadi korban.
Brajageni tidak menginginkan hal itu. Malam itu cukup dua orang saja yang akan dijadikan korban. Sisanya esok malam. Makanya, kini dia harus bertindak cepat. Brajageni sama sekali tidak berusaha mengelak atau menangkis, saat kedua orang lawannya bergerak menyerang. Sepertinya laki-laki bertubuh kurus itu tidak mempedulikan mereka. Karuan saja hal ini membuat Rakapitu dan Gibang jadi gembira. Mereka menduga laki-laki bercaping itu tidak mampu mengelakkan serangan gabungan yang dilakukan.
Takkk, takkk...!
Dua batang golok itu membalik ketika mengenai sasaran. Sementara tangan kedua orang penyerang itu bergetar hebat, sampai-sampai senjata yang digenggam hampir terlepas dari pegangan. Tidak hanya itu saja yang dilakukan Brajageni. Tubuhnya cepat menyelinap ke belakang. Dan setibanya di sana, cepat laksana kilat, kedua tangannya menepuk tengkuk Rakapitu dan Gibang Gerakan Brajageni cepat bukan mata.
Terdengar suara keluhan lirih, disusul robohnya tubuh kedua orang itu begitu kedua tangan Brajageni hinggap di sasaran. Rakapitu dan Gibang kontan pingsan. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Brajageni menyambar mereka sebelum menyentuh tanah. Dan secepat itu pula laki-laki serba hitam itu melesat kabur dari situ, sambil memanggul tubuh kedua orang yang akan menjadi korbannya.
Baru saja tubuh Brajageni lenyap ditelan kegelapan malam, para penduduk Desa Pucung muncul di tempat itu. Jumlah mereka tak kurang dari dua puluh orang. Di tangan mereka semua tergenggam sebatang obor, membuat suasana di tempat itu jadi terang-benderang. Dengan dipimpin empat orang peronda lain yang tadi berjaga-jaga di pos, para penduduk mencari-cari di sekitar tempat itu.
"Kau yakin suara kentongan itu berasal dari sini, Guriang?" tanya salah seorang penduduk yang berusia setengah baya.
Guriang, yang ternyata adalah seorang pemuda, langsung menoleh. "Aku yakin sekali, Paman," sahut Guriang, mantap.
"Kalau begitu, mari kita cari di sekitar sini!" seru laki-laki setengah baya itu.
"Hey...!" seru salah seorang penduduk. Telunjuk tangan kanannya menuding ke tanah.
Seperti mendapat aba-aba, belasan orang rekannya menoleh ke arah yang ditunjuk, kemudian bergegas melangkah menghampiri. Guriang membungkukkan tubuhnya, memungut dua batang golok. Kemudian diperhatikannya golok itu dengan seksama.
"Ini golok Rakapitu dan Gibang," desak Guriang.
"Berarti mereka tadi berada di sini...," sambut seorang penduduk yang berbibir tebal dan hitam.
"Benar!" sahut Guriang memberi dukungan.
"Mekipun tanda-tandanya sedikit, bisa diketahui kalau di sini telah terjadi pertarungan...."
"Tapi, ke mana mereka...?!" tanya seorang penduduk yang bertubuh kecil kurus. Tidak jelas, kepada siapa pertanyaan itu ditujukan. Dan andaikata ditujukan pun, orang yang ditanya tidak akan bisa menjawabnya. Mereka semua memang sama-sama tidak tahu.
"Kita berpencar mencarinya," lagi-lagi Guriang yang mengambil keputusan cepat. "Kita memecah diri menjadi empat kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari lima orang. Bagaimana? Setuju?!"
"Setuju...!" sahut belasan orang penduduk serentak.
Guriang tersenyum lebar melihat sambutan yang menggembirakan itu. Setelah merundingkan kembali, apa-apa yang hams dilakukan, keempat orang itu pun segera berpencar. Dua puluh orang penduduk yang terbagi menjadi empat kelompok mulai menyusuri sekitar daerah itu. Mereka mencari-cari dengan penuh semangat. Mereka menguak kerimbunan pepohonan dan semak-semak seraya memanggil-manggil nama kedua orang peronda itu. Tapi, tetap saja tidak ada tanda-tanda keberadaan Rakapitu dan Gibang.
Akhirnya setelah lama mencari-cari tanpa hasil, para penduduk putus asa. Kedua kaki mereka telah lelah sekali. Leher terasa sakit, dan suara pun serak karena terlalu sering memanggil-manggil. Sedangkan, yang dicari tak kunjung datang. Satu demi satu kelompok pencari itu mulai kembali ke pos masing-masing dengan langkah lesu. Mereka hanya dapat berharap, agar kedua orang itu selamat.
* * * * * * * *
TUJUH
Hari masih pagi di Desa Pucung. Matahari yang berbentuk bola raksasa baru saja muncul di ufuk Timur. Warnanya merah jingga. Suasana pagi yang semula sunyi, mendadak dipecahkan oleh teriakan keras diiringi sesosok tubuh yang berlari terpontang-panting. Menilik dari pakaiannya, dia pasti penduduk Desa Pucung. Orang itu terus saja berlari cepat, sekalipun telah memasuki desa. Tentu saja hal ini menarik perhatian beberapa penduduk lainnya.
"Ada apa, Soma?" tanya seorang yang rambutnya dikuncir, pada laki-laki berpakaian kuning yang tengah berlari-lari itu.
Tapi Soma sama sekali tidak menghiraukannya, dan malah terus saja berlari. Hal ini membuat laki-laki berkuncir itu penasaran. Segera perhatiannya dialihkan pada orang yang berada di sebelahnya.
"Ada apa?" tanya laki-laki berkuncir itu.
Tapi orang yang ditanya juga hanya menggelengkan kepala.
"Sepertinya dia menuju ke rumah kepala desa," tebak seorang penduduk yang bermata picak.
"Pasti ada sesuatu yang akan dilaporkannya," sambut laki-laki yang berambut dikuncir.
Karena perasaan ingin tahu, orang-orang itu pun bergerak mengikuti. Dan memang, apa yang dikatakan orang bermata picak itu benar. Soma ternyata menuju rumah kepala desa.
"Ki..! Ki...!" masih dalam keadaan berlari-lari, dan dalam jarak tak kurang dari lima tombak, laki-laki berpakaian kuning itu berteriak-teriak memanggil Ki Jayus yang kebetulan tengah berada di halaman. Karuan saja hal ini membuat Kepala Desa Pucung itu terperanjat.
"Ada apa?!" tanya Ki Jayus ketika Soma telah berada di hadapannya.
"Anu, Ki...." Dengan terputus-putus karena napasnya masih memburu, Soma berusaha berbicara.
"Tenanglah dulu," ujar Ki Jayus pelan. "Kau tidak akan bisa mengatakannya kalau tidak tenang dulu."
Laki-laki berpakaian kuning yang bernama Soma itu terdiam, berusaha menenangkan diri.
"Tarik napas dalam-dalam, lalu keluarkan," saran Ki Jayus.
Kembali laki-laki setengah baya itu menuruti anjuran Kepala Desa Pucung itu. Napasnya segera ditarik dalam-dalam, lalu dihembuskan kuat-kuat. Memang setelah beberapa kali melakukan hal itu, dia mulai merasa tenang.
"Sekarang, katakanlah. Mengapa kau bersikap seperti itu?" ujar Ki Jayus penuh wibawa.
"Mereka, Ki. Aku telah menemukannya," Soma berusaha menjelaskan.
"Mereka siapa?" Ki Jayus mengerutkan kening. "Bicaralah yang jelas!"
"Rakapitu dan Gibang, Ki."
"Rakapitu dan Gibang?!" ulang Ki Jayus lambat-lambat. "Memangnya, ada apa dengan kedua orang itu?!"
"Jadi..., kau belum mengetahuinya, Ki?" sekarang malah laki-laki berpakaian kuning itu yang terheran-heran.
"Mengetahui? Mengetahui apa?!" tanya Ki Jayus, tak mengerti.
"Rakapitu dan Gibang hilang secara aneh semalam, setelah memukul kentongan tanda bahaya," jelas laki-laki berpakaian kuning itu.
"Heh?! Mengapa aku tidak diberi tahu?!" ada nada teguran dalam pertanyaan itu.
"Kami belum sempat memberitahukanmu, Ki," selak sebuah suara menyahuti, sebelum Soma menjawab.
Serentak Ki Jayus dan laki-laki setengah baya menoleh ke arah asal suara. Di sana berdiri Guriang dan tiga orang lainnya. Mereka berempat adalah yang bertugas ronda semalam.
"Semalam kami ingin memberitahukanmu, tapi malam sudah terlalu larut. Dan menjelang dini hari, kami terpaksa mengurungkannya. Maaf, Ki. Kami tidak ingin mengganggumu," jelas Guriang mewakili rekan-rekannya.
"Hm...," hanya gumaman tak jelas yang menyambuti ucapan pemuda bertubuh kekar itu.
"Rencananya, pagi ini kami akan memberitahumu. Sekalian meneruskan pencarian. Tapi, rupanya kami sudah didahului Kakang Soma."
"Aku telah menemukan mereka, Guriang," jelas Soma.
"Aku telah mendengarnya tadi, Kang," sahut Guriang. "Bagaimana keadaan mereka?"
"Tidak ada harapan sama sekali," sahut Soma bernada mengeluh.
"Jadi...?" suara Guriang tercekat di tenggorokan.
"Ya," Soma menganggukkan kepala. "Mereka tewas."
"Ya, Tuhan...!" hampir berbareng, semua mulut berseru.
"Mari kita ke sana...!" ajak Ki Jayus yang terlebih dulu sadar dari kesedihannya.
Tanpa membuang-buang waktu lagi, keenam orang itu segera meninggalkan tempat itu, menuju tempat Rakapitu dan Gibang ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Di tengah perjalanan mereka bertemu rombongan penduduk yang bermaksud menyusul Soma. Dan begitu para penduduk itu mengetahui maksud rombongan kecil itu, mereka juga ikut menggabungkan diri.
Semakin lama rombongan itu semakin banyak jumlahnya. Dan menjelang mulut desa, Dewa Arak dan Wikalpa yang kebetulan ada di situ segera menggabungkan diri. Suara riuh seperti ada serombongan lebah marah terdengar ketika para penduduk berbicara satu sama lain. Soma bertindak sebagai penunjuk jalan, membawa rombongan penduduk ini menuju Hutan Dadap.
"Bagaimana kau bisa menemukannya, Soma?" tanya Guriang. Ada nada penasaran dalam suaranya. Maklum, semalam dia bersama rekan-rekannya telah mencari-cari sampai semalam suntuk, tapi tanpa hasil.
"Aku pun menemukannya secara tidak sengaja, Guriang. Kau tahu kan, aku selalu mencari kayu bakar, di hutan ini. Dan secara tidak sengaja aku melihat mayat mereka. Mengerikan!"
Setelah berkata demikian, Soma bergidik. Namun, Guriang tidak menanggapi. Sehingga laki-laki setengah baya itu pun menghentikan ucapannya. Tak lama kemudian rombongan penduduk Desa Pucung ini telah memasuki Hutan Dadap. Soma terus berjalan di depan, sampai akhirnya tiba di depan sebatang pohon yang di sekitarnya terdapat semak-semak.
"Di situlah mayat mereka kutemukan," tunjuk laki-laki berpakaian kuning itu memberi tahu. Telunjuk tangan kanannya menuding ke arah pohon dan semak-semak.
Guriang dan tiga orang rekannya segera melangkah maju, lalu menguak kerimbunan semaksemak. Sementara yang lainnya menunggu di tempat.
"Ah...!" Terdengar jerit pelan bernada keluhan. Sesaat kemudian, keempat orang itu bergerak terhuyung-huyung keluar kerimbunan. Wajah mereka tampak pucat pasi.
"Guriang! Ada apa...?!" tanya Ki Jayus tak sabar.
"Mengapa mayat mereka tidak dibawa keluar?!"
Tapi Guriang sama sekali tidak menyahuti pertanyaan Kepala Desa Pucung itu. Tampak jelas kalau dia masih dilanda keterkejutan yang amat sangat. Melihat hal ini, Wikalpa jadi tidak sabar lagi. Segera kakinya melangkah, memasuki kerimbunan semak-semak itu.
Kini para penduduk kembali menanti, dengan perasaan tegang. Mereka ingin tahu, apa yang akan terjadi lagi. Tapi, tidak terdengar suara keluhan sedikit pun dari dalam kerimbunan semak-semak itu. Bahkan tak lama kemudian, laki-laki berkumis jarang-jarang itu telah keluar dari kerimbunan semak-semak. Di bahu kanan kirinya sudah terpanggul dua sosok tubuh.
Dengan wajah tenang, Wikalpa menurunkan tubuh yang dipanggulnya. Memang yang dikatakan Soma benar, bahwa dua sosok mayat itu adalah Rakapitu dan Gibang. Tapi, keadaan mereka benar-benar mengerikan. Kepala hampir terlepas dari leher, sedangkan tubuhnya kurus kering dan pucat seolah-olah tak ada darah setetes pun di tubuh mereka. Bukan itu saja. Sekujur tubuh mereka juga penuh luka sayatan. Bahkan pakaian kedua orang itu compang-camping.
Arya mengerutkan alisnya. Kembali Dewa Arak melihat mayat-mayat dengan luka-luka yang sama dengan yang pernah ditemukannya. Apakah ada makhluk peminum darah yang berkeliaran di desa ini?
"Keparat...!" Ki Jayus, Kepala Desa Pucung itu menggertakkan gigi begitu melihat mayat kedua orang warganya. "Iblis mana yang telah melakukan semua ini?!"
Tapi tidak ada satu pun warganya yang menjawab pertanyaan itu. Mereka semua sama menundukkan kepala.
"Guriang...! Bagaimana ini bisa terjadi?! Bukankah Rakapitu dan Gibang bertugas bersamamu?"
Guriang mengangkat kepala, menatap sebentar wajah Ki Jayus. "Maafkan aku, Ki," pinta Guriang. "Waktu peristiwa itu terjadi, aku tidak berada bersama mereka."
"Hm.... Lalu, kau berada di mana?!" sentak Ki Jayus.
"Aku dan yang lain berada di gardu jaga, Ki. Sementara Rakapitu dan Gibang berkeliling."
"Hm...," hanya gumaman pelan yang keluar dari mulut Kepala Desa Pucung itu.
"Ki...," sapa Arya begitu mendapat kesempatan.
"Ada apa, Arya?" tanya Ki Jayus seraya menoleh ke arah pemuda berambut putih keperakan itu.
"Apakah ini adalah kejadian yang baru pertama kali?" tanya Arya ingin tahu.
"Tidak, Arya," Ki Jayus menggelengkan kepala. "Ini adalah kejadian yang kedua kalinya. Kejadian pertama telah menimpa Empu Sawung."
Dewa Arak menganggukkan kepala. Jadi, ini adalah kejadian ketiga kalinya yang dilihat Arya. Yang kedua adalah sosok hitam yang kemudian dikuburkannya.
"Keadaan mayat mereka mengerikan sekali, Ki," kata Arya lagi. "Sepertinya darah di seluruh tubuh mereka habis! Apa mungkin di desa ini ada makhluk peminum darah?"
Ki Jayus mengangkat bahu. "Aku sama sekali tidak tahu, Arya. Tapi yang jelas, aku belum pernah mendengarnya."
Dewa Arak terdiam.
"Nanti malam penjagaan harap lebih ditingkatkan. Kalian semua harus bersikap waspada. Begitu melihat gelagat mencurigakan, lekas pukul kentongan secepatnya," ujar Ki Jayus pada Guriang.
"Baik, Ki," semua kepala terangguk pelan.
"Bagus! Sekarang mari kita kembali, mengurus mayat kedua orang ini dulu," ujar Ki Jayus lagi.
Sesaat kemudian, rombongan penduduk Desa Pucung itu pun bergerak meninggalkan Hutan Dadap.
* * * * * * * *
Malam itu suasana terasa lebih menyeramkan. Kematian demi kematian yang datang susul-menyusul, benar-benar membuat Desa Pucung geger. Para penduduknya kini dicekam rasa ketakutan. Mereka khawatir, kalau pembunuh misterius itu akan mendatangi mereka.
Tong, tong, tong…!
Suara kentongan terdengar mengusik keheningan malam sepi yang hanya dihiasi bulan sabit di langit. Guriang dan ketiga orang kawannya mengedarkan pandangan ke sekeliling. Masing-masing mengawasi arah yang berlainan.
"Hei...!" seru Guriang kaget. Mendadak saja, sesosok bayangan hitam bertubuh tinggi kurus tampak melesat cepat ke arahnya. Pemuda bertubuh pendek kekar ini memang bertugas mengawasi belakang. "Cepat menyingkir...!"
Seraya berseru demildan, Guriang melompat ke samping, dan membuang tubuhnya ke tanah. Begitu juga ketiga orang kawannya. Maka serangan sosok hitam itu hanya mengenai tempat kosong.
"Cepat pukul kentongan...!" teriak Guriang keras seraya melompat menyerang sosok hitam itu. Golok di tangannya membabat cepat ke arah leher sosok bercaping itu.
"Hmh...!" Sosok hitam yang jika dibuka selubung kain hitamnya adalah Brajageni, hanya mendengus. Tangan kirinya bergerak cepat ke arah golok yang menyambarnya.
Tappp…!
Guriang terbelalak kaget ketika goloknya dapat dicengkeram lawan. Dan sekali Brajageni bergerak membetot, kontan tubuh pemuda pendek kekar ini terhuyung ke depan. Di saat itulah telunjuk kanan laki-laki tinggi kurus ini bergerak cepat ke arah dada.
Tidak ada pilihan lagi bagi Guriang, kecuali melepaskan goloknya dan melempar tubuh ke belakang. Maka, serangan Brajageni hanya mengenai tempat kosong. Pada saat yang sama, salah seorang peronda telah memukul kentongan.
Tong, tong, tong...!
Suara kentongan tanda bahaya terdengar keras menguak keheningan malam sepi. Brajageni menggertakkan gigi. Sayang, dia harus berusaha keras agar calon korbannya tidak mati. Korbannya harus dibawa dalam keadaan hidup kalau ingin darah itu berguna untuk kerisnya. Dengan perasaan geram, Brajageni melompat menyerang. Laki-laki tinggi kurus ini tahu, kalau dia harus bertindak cepat. Masalahnya, orang-orang pasti akan berkumpul di sini.
Maka tanpa ragu-ragu lagi, segera dikerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Betapapun Guriang dan ketiga orang kawannya telah mengerahkan seluruh kemampuan, namun dalam dua gebrakan saja, laki-laki tinggi kurus ini telah berhasil menotok lemas dua orang lawannya. Dan secepat kedua orang itu roboh, secepat itu pula Brajageni memanggulnya. Kemudian, laki-laki tinggi kurus itu membawanya kabur.
Di saat itulah, melesat sesosok bayangan ungu. Dan dengan gerakan indah dan manis, sosok bayangan itu bersalto beberapa kali di udara, kemudian hinggap di hadapan Brajageni.
"Mau lari ke mana, Penjahat Keji?!" bentak sosok ungu yang tak lain dari Dewa Arak. Sepasang mata pemuda berambut putih keperakan itu merayapi sekujur tubuh laki-laki bercaping.
Brajageni tercenung bingung. Dia kini tengah memanggul tubuh dua orang korbannya. Lalu, bagaimana mungkin melawan Dewa Arak? Di saat laki-laki bertubuh tinggi kurus ini kebingungan, sesosok bayangan merah tiba-tiba menerjang dari udara ke arah Dewa Arak dengan serangan totokan-totokan jari tangan terbuka lurus ke arah ubun-ubun dan pelipis.
Arya terperanjat. Sama sekali tidak disangka akan mendapat serangan mendadak dan dahsyat begitu. Tanpa pikir panjang lagi, pemuda berambut putih keperakan itu membalikkan tubuh dan menggerakkan tangan menangkis.
Plak, plak, plak...!
Terdengar benturan keras seperti dua batang logam beradu ketika dua pasang tangan yang sama-sama mengandung tenaga dalam tinggi berbenturan. Akibatnya sungguh hebat! Tubuh Dewa Arak terhuyung dua langkah ke belakang. Sekujur tangannya terasa bergetar hebat. Sementara sosok bayangan merah itu terpental balik ke atas.
Arya terkejut. Disadari kalau penyerangnya memiliki tenaga dalam amat kuat. Tenaga sosok bayangan merah itu tidak kalah dengan tenaganya sendiri. Sebenarnya, bukan hanya Dewa Arak saja yang terkejut. Ternyata sosok bayangan merah itu pun dilanda perasaan yang sama. Dan dengan gerakan indah dan manis, kakinya mendarat di tanah.
Brajageni tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia tahu kalau sosok bayangan merah itu adalah gurunya yang berjuluk Raja Racun Muka Putih. Maka tanpa pikir panjang lagi, laki-laki bertubuh tinggi kurus ini melesat kabur.
"Hey...!" seru Arya keras seraya melesat memburu. Tapi sebelum maksud Dewa Arak terlaksana, sesosok bayangan merah telah berkelebat cepat dan tahu-tahu telah berada di hadapannya. Mau tak mau Arya terpaksa mengurungkan niatnya untuk mengejar Brajageni. Sosok bayangan merah di hadapannya ini memang seorang lawan yang amat tangguh.
Dalam keremangan malam yang hanya diterangi cahaya bulan, Dewa Arak menatap penyerangnya. Dia adalah seorang kakek bertubuh sedang, berpakaian serba merah. Kumis dan jenggotnya berwarna hitam. Sangat pas sekali dengan kulit wajahnya yang putih seperti kapur. Kulit wajahnya yang putih, nampak terlihat jelas dalam suasana malam kelam.
"Ha ha ha...!" Raja Racun Muka Putih tertawa keras sekali. Bahkan bagai menggelegar seperti guntur. Jelas kalau tawanya disertai pengerahan tenaga dalam.
Dan akibatnya sungguh hebat. Guriang dan seorang temannya yang masih berada di situ seketika terjungkal jatuh. Dari mulut, hidung, dan telinga kedua orang itu mengalir darah segar. Yang pasti, mereka tewas seketika dengan dada pecah.
Arya kaget bukan main, merasakan pengaruh suara tawa itu. Dadanya tergetar hebat dan telinganya pun berdengung keras. Buru-buru tenaga dalamnya dikerahkan untuk menahan serangan tawa Raja Racun Muka Putih.
Belasan orang penduduk yang berdatangan, dan berada dalam jarak yang cukup jauh pun mengalami akibat yang serupa. Tubuh mereka terjungkal, lalu buru-buru mendekapkan kedua tangan ke telinga dalam usaha menahan serangan suara tawa itu.
Meskipun tidak melihat, Arya tahu apa yang dialami para penduduk itu. Dan kalau dibiarkan, mereka semua akan tewas. Maka pemuda berambut putih keperakan ini segera menghentakkan kedua tangannya ke arah lawan menggunakan jurus 'Pukulan Belalang'.
Wusss...!
Angin keras berhawa panas menyengat, menyambar ke arah Raja Racun Muka Putih. Seketika tokoh sesat yang menggiriskan ini terperanjat, mengenali serangan berbahaya itu. Maka tanpa membuang-buang waktu lagi, tubuhnya segera dilempar ke samping dan bergulingan di tanah.
Dengan sendirinya, suara tawanya pun terhenti. Tanpa diduga, begitu kakek bermuka putih ini bangkit dari berguling, tubuhnya langsung melesat ke arah kerumunan penduduk yang tadi terjungkal di tanah sambil mendekap telinga. Dan sekali tangan kakek ini terulur, dua sosok tubuh telah berada dalam panggulannya.
Tentu saja Dewa Arak tidak membiarkan begitu saja. Cepat laksana kilat tubuhnya melompat memburu. Tapi, rupanya hal itu sudah diperhitungkan Raja Racun Muka Putih. Tangan kanannya yang bebas langsung dikibaskan. Maka sekumpulan benda-benda berbentuk serbuk berbau amis memuakkan, meluncur ke arah Arya. Pemuda berambut putih keperakan ini tidak punya pilihan lagi, kecuali cepat melompat ke samping dan bergulingan di tanah. Untunglah taburan serbuk beracun dari lawannya mengenai tempat kosong.
Raja Racun Muka Putih memang tidak bermaksud sungguh-sungguh menyerang. Serangan itu ternyata dimaksudkan hanya untuk mencegah usaha Dewa Arak menghalangi kepergiannya. Maka begitu Arya mengelak, kesempatan ini segera dipergunakannya. Tubuhnya melesat cepat bagai kilat. Dan dalam sekejapan saja, tubuhnya sudah lenyap ditelan kerimbunan pepohonan di tengah kegelapan malam.
DELAPAN
"Hhh...!" Dewa Arak menghela napas berat, dan sama sekali tidak mengejar. Dia merasa, hal itu sama sekali tidak ada gunanya. Maka bergegas perhatiannya dialihkan pada para penduduk desa yang masih terduduk di tanah.
"Mana Ki Jayus dan Wikalpa?" tanya Arya, setelah tidak melihat adanya kedua orang itu dalam kerumunan penduduk. Tidak ada satu pun penduduk yang menyahut.
"Aneh...," gumam Dewa Arak pelan. "Kedua orang itu tidak pernah ada setiap kali terjadi pembunuhan seperti ini."
"Kau menduga, mereka pelakunya, Dewa Arak?" tanya Soma begitu mendengar nada suara Arya.
"Tidak sampai sejauh itu. Aku hanya agak curiga saja. Ketidakhadiran merekalah yang membuatku curiga. Apalagi ciri-ciri kedua orang itu mirip sosok hitam bercaping," sahut Arya tidak berani menduga sembarangan. "Tapi yang membuatku ragu, mengapa sampai kedua-duanya tidak hadir pada setiap kejadian."
"Jadi, salah satu di antara mereka kau curigai sebagai pelakunya, Dewa Arak?" desak Soma lagi.
Perlahan kepala Arya mengangguk.
"Andaikata benar, siapa di antara kedua orang itu yang lebih kau curigai?" tanya Soma ingin tahu.
"Ki Jayus," kata Arya pelan.
"Hm...! Mengapa bukan Wikalpa, Dewa Arak?!" Soma terkejut. "Aku lebih condong padanya."
"Mengapa?" tanya Arya ingin tahu.
"Gerak-geriknya kasar. Dan lagi, pakaiannya pun cocok dengan orang tadi," sahut laki-laki berpakaian kuning memberi alasan.
"Aku lebih condong pada Ki Jayus," pelan suara Dewa Arak.
"Apa dasarnya hingga kau menuduh begitu?" kejar Soma. Rasa penasarannya terdengar jelas dalam suaranya.
Arya menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya kuat-kuat, sebelum menjawab pertanyaan itu. "Seorang pembunuh yang tidak ingin dikenali, dengan sendirinya berusaha menyamarkan diri. Wikalpa terlalu menonjol sikap kasarnya. Juga pakaiannya. Jadi, itulah sebabnya aku lebih condong pada Ki Jayus," urai Dewa Arak panjang lebar.
Soma kontan terdiam, kemudian bangkit berdiri. Sikapnya diikuti penduduk lainnya. Mereka juga tak lupa membawa mayat Guriang dan rekannya. Arya pun melangkah di belakang mereka. Menjelang tembok batas desa, tampak sosok berpakaian putih berlari-lari menyambut. Sosok itu bertubuh tinggi kurus.
Baik Dewa Arak maupun penduduk Desa Pucung segera mengetahui, siapa adanya sosok berpakaian putih itu. Meskipun jaraknya masih cukup jauh, namun potongan tubuh sosok itu sangat dikenal. Siapa lagi kalau bukan Ki Jayus! Dugaan mereka memang tidak salah! Laki-laki berpakaian putih itu memang Ki Jayus, Kepala Desa Pucung. Seketika jantung Dewa Arak dan Soma berdebar tegang, karena teringat akan pembicaraan tadi. Begitu telah berada dekat mereka, tanpa mempedulikan yang lain, Ki Jayus berlari mendekati Dewa Arak. Kemudian ditariknya tangan Dewa Arak, menjauhkannya dari rombongan penduduk.
"Kalian berangkat lebih dulu...!" seru Ki Jayus pada para penduduk yang menghentikan langkah, dan baru kembali berjalan setelah mendengar perintah itu. Setelah rombongan penduduk itu melangkah pergi, Ki Jayus menarik tangan Arya melangkah meninggalkan tempat itu. Mereka menuju arah yang berlawanan.
"Ada apa, Ki?" tanya Arya. Teringat akan dugaannya, membuat pemuda berambut putih keperakan ini bersikap waspada.
Ki Jayus tidak langsung menjawab, tapi terus saja melangkah. Arya yang merasa penasaran terpaksa mengikuti, meskipun kini tangannya tidak dituntun seperti tadi.
"Aku telah mengetahui tempat persembunyian orang bercaping itu, Arya," jelas Kepala Desa Pucung pelan seraya menolehkan kepala ke kanan dan ke kiri sambil tetap melangkah. Jelas kalau Ki Jayus tidak ingin ada orang lain yang mendengar ucapannya.
"Benarkah apa yang kau katakan itu, Ki?" tanya Arya meminta ketegasan, seraya ikut melangkah di sebelah Kepala Desa Pucung itu.
Ki Jayus menatap Arya tajam-tajam. "Kau tidak mempercayaiku, Arya?" tanya laki-laki berpakaian putih itu. Ada nada ketidak-senangan dalam suaranya.
"Bukannya tidak percaya, Ki," sahut Arya mengelak. "Tapi merasa ragu...."
"Apa yang membuatmu ragu, Arya?" selak Ki Jayus ingin tahu.
"Dari mana kau mengetahui tempat tinggal orang bercaping itu, Ki?"
"Diam-diam aku mengikutinya," sahut laki-laki berpakaian putih itu.
Dewa Arak menoleh. Menatap wajah Ki Jayus tanpa berkata-kata.
"Begitu mendengar suara kentongan tadi, aku segera menuju ke sana. Tapi, kulihat kau tengah bertempur menghadapi seorang kakek berpakaian merah. Sementara orang bercaping hitam kulihat melarikan diri sambil membawa dua orang wargaku. Semula aku kebingungan, tapi akhirnya kuputuskan untuk mengikuti orang bercaping itu. Ternyata usahaku tidak sia-sia, karena aku berhasil mengetahui sarangnya," jelas laki-laki berpakaian putih panjang lebar.
Arya tercenung mendengar uraian panjang lebar Ki Jayus. Hatinya jadi ragu dengan dugaannya semula. Kalau apa yang di katakan Kepala Desa Pucung ini benar, berarti orang bercaping itu adalah Wikalpa! Sementara, dugaan kalau orang bercaping adalah Ki Jayus kontan menguap. Memang, rasanya tidak mungkin kalau Kepala Desa Pucung ini pelakunya. Benar kata Soma. Pasti pembunuh biadab itu adalah Wikalpa!
"Sekarang apa rencanamu, Ki?"
"Kita serbu sarang mereka...!" sahut Ki Jayus. Tegas dan mantap kata-katanya.
"Sekarang, Ki?" tanya Arya memastikan.
Ki Jayus menggelengkan kepala. "Besok," jawab laki-laki berpakaian putih itu.
* * * * * * * *
Hari masih pagi. Angin yang sejuk dan dingin berhembus pelan, terasa nikmat sampai ke dalam dada. Tampak dua sosok tubuh melangkah pelan memasuki Hutan Dadap. Dua sosok itu adalah Dewa Arak dan Ki Jayus.
"Ki...," ucap Arya memecah keheningan pagi.
"Hm...," hanya gumam pelan Ki Jayus yang menyambuti sapaan Arya.
"Apakah kau sanggup menghadapi orang bercaping itu?" tanya Arya ragu-ragu.
"Aku tidak berani memastikannya, Arya," jawab laki-laki berpakaian putih bernada memutar.
Dewa Arak terdiam, tidak berkata-kata lagi. Dan karena Ki Jayus juga tidak berkata-kata lagi, suasana pun jadi hening. Kini yang terdengar hanyalah suara kerosak rerumputan dan semak-semak kering yang terpijak kaki-kaki mereka.
Mendadak Arya mengernyitkan keningnya. Pendengarannya yang tajam menangkap adanya suara langkah perlahan dan ringan di belakangnya. Tapi, dia berpura-pura tidak tahu, dan terus saja melangkah. Hanya saja, Dewa Arak mulai bersikap waspada, bersiap-siap menghadapi serangan mendadak.
"Masih jauhkah tempat itu, Ki?" tanya Arya lagi ketika mereka telah semakin jauh masuk ke dalam hutan. Tidak ada sahutan yang menyambuti pertanyaan Dewa Arak. Karuan saja hal itu mengherankan hati Arya. Apalagi ketika beberapa saat menunggu, juga tak terdengar sahutan.
"Hih...!" Mendadak Ki Jayus mendoyongkan tubuh ke kanan sambil mengirimkan kibasan tangan kiri ke arah pelipis Arya.
Karuan saja hal ini membuat pemuda berambut putih keperakan ini terkejut. Sama sekali tidak disangka kalau akan mendapat serangan maut yang dilakukan dalam jarak dekat dan tiba-tiba sekali. Tapi Dewa Arak adalah tokoh berkepandaian tinggi, yang telah kenyang bertempur menghadapi tokoh-tokoh licik dan menggiriskan. Sudah tak terhitung lagi ancaman maut dan serangan mendadak yang dihadapinya.
Maka meskipun berada dalam keadaan gawat seperti itu, Dewa Arak masih mampu menyelamatkan diri. Cepat-cepat tubuhnya didoyongkan ke kiri, sehingga kibasan itu mengenai tempat kosong. Hanya berjarak sekitar tiga jari dari sasaran semula. Menilik dari rambut dan pakaian Arya yang berkibaran keras, bisa diperkirakan kekuatan tenaga dalam yang terkandung dalam serangan itu.
Belum juga Dewa Arak berbuat sesuatu, Ki Jayus telah melancarkan serangan susulan. Laki-laki berpakaian putih ini mengirimkan tendangan miring ke arah pelipis, sambil memutar tubuh. Arya tetap bersikap tenang, karena sudah tidak berada dalam keadaan berbahaya lagi. Namun demikian, dia masih berada dalam keadaan terdesak. Tanpa ragu-ragu, segera ditangkisnya serangan lawan dengan tangan kanan.
Plakkk...!
Ki Jayus memekik tertahan. Tubuh laki-laki ini terhuyung dua langkah ke belakang. Sementara, Dewa Arak hanya merasakan tangan yang berbenturan dengan kaki Kepala Desa Pucung itu bergetar. Dan hebatnya, kuda-kudanya sama sekali tidak bergeming.
"Ha ha ha...!"
Terdengar suara tawa terbahak-bahak mengandung pengerahan tenaga dalam tinggi. Sesaat kemudian, di belakang Ki Jayus telah berdiri Raja Racun Muka Putih.
"Ini milikmu, Brajageni...!" kata Raja Racun Muka Putih seraya menyerahkan sebilah keris kepada Ki Jayus. Laki-laki berpakaian putih itu langsung menerimanya.
"Brajageni?!" ulang Dewa Arak.
"Ha ha ha...!" Raja Racun Muka Putih tertawa bergelak. "Brajageni tunjukkanlah padanya siapa dirimu."
"Baik, Guru," sahut Ki Jayus yang ternyata adalah Brajageni. Kemudian laki-laki berpakaian putih ini menyelinap ke balik rerimbunan pohon.
Begitu tubuh Kepala Desa Pucung itu lenyap di balik kerimbunan pepohonan, Arya kembali mengalihkan perhatian pada Raja Racun Muka Putih. Kakek berpakaian merah itu juga balas menatap, tak kalah tajam. Tapi sebelum kedua orang ini berbuat sesuatu, terdengar bentakan keras.
"Mau kabur ke mana lagi kau, Raja Racun...?!" Berbareng dengan lenyapnya bentakan itu, tiba-tiba di dekat Arya telah berdiri seorang laki-laki bertubuh tinggi kurus.
"Wikalpa...," desis Arya.
"Malaikat Halilintar...," desah Raja Racun Muka Putih. Ada nada kegentaran dalam nada suaranya. Sepasang matanya menatap penuh rasa tak percaya pada sosok yang berdiri di hadapannya.
"Malaikat Halilintar...?" desis Arya tak percaya.
Dewa Arak memang pernah mendengar julukan itu. Memang, Malaikat Halilintar adalah seorang pendekar yang terkenal memiliki kepandaian amat tinggi. Hanya sayangnya, dia telah mengundurkan diri dari dunia persilatan. Sungguh tidak disangka kalau tokoh itu tiba-tiba ada di sini. Kini Dewa Arak tahu, langkah ringan yang tadi didengarnya adalah langkah kaki Malaikat Halilintar.
"Uruslah pembunuh itu, Arya," ujar Wikalpa alias Malaikat Halilintar. "Biar aku yang mengurus orang ini."
Dewa Arak tidak membantah. Bergegas disusulnya Brajageni, alias Ki Jayus. Dan kedatangannya bertepatan dengan selesainya laki-laki bertubuh tinggi kurus itu berganti pakaian. Brajageni terperanjat, namun sekejap kemudian, sudah bisa menguasai diri. Sambil berteriak keras, laki-laki bertubuh tinggi kurus ini menghunus kerisnya.
Srattt..!
Bulu tengkuk Dewa Arak meremang ketika melihat keris yang digenggam Brajageni, karena memiliki perbawa yang begitu menggiriskan. Jantung Arya berdetak keras tanpa mampu menahannya. Ada hawa dingin yang memancar dari bilah keris itu. Tahu akan keampuhan keris lawan, Dewa Arak tidak berani bersikap main-main lagi. Cepat-cepat guci araknya diangkat, lalu dituangkan ke mulut.
Gluk... gluk... gluk...!
Suara tegukan terdengar ketika arak itu melewati tenggorokan Arya. Baru saja Dewa Arak menurunkan guci itu, Brajageni sudah melompat menerjang. Keris di tangannya ditusukkan cepat ke arah leher Arya. Dewa Arak terperanjat kaget, merasakan hawa dingin yang amat sangat menyambar sebelum serangan-serangan keris itu tiba. Hawa dingin itu membuat sekujur otot-otot tubuh Dewa Arak kaku seperti tak bisa digerakkan. Bahkan giginya pun bergemeletukan.
Begitu serangan itu menyambar dekat, hawa dingin yang menyerang Dewa Arak semakin menjadi-jadi. Buru-buru Arya mengerahkan ilmu 'Tenaga Sakti Inti Matahari'nya untuk menghilangkan pengaruh hawa dingin yang membuatnya sukar bergerak! Untung Dewa Arak bertindak cepat. Kalau tidak, mungkin sudah tersambar keris Brajageni karena otot-ototnya mendadak kaku. Berkat ilmu 'Tenaga Sakti Inti Matahari', pemuda berambut putih keperakan itu mampu menggerakkan ototnya kembali, meskipun masih kaku.
Berbeda dengan biasanya, kali ini Arya tidak berani, mengelak tanpa berpindah tempat. Apalagi tanpa berpindah kaki! Dewa Arak mengelak sejauh-jauhnya, dengan melempar tubuh ke belakang. Dia bersalto beberapa kali di tanah, kemudian hinggap dengan agak terhuyung karena kekakuan yang melanda otot-ototnya.
Sesaat kemudian, pertarungan sengit yang tidak menarik pun terjadi. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Dewa Arak mengalami kesulitan memainkan ilmu 'Belalang Sakti'nya. Ilmu 'Belalang Sakti' adalah ilmu yang mengandalkan kelenturan otot. Tenaga yang terkandung dalam setiap serangan ilmu 'Belalang Sakti', adalah pengerahan tenaga yang teratur dan tiba-tiba. Jadi perubahan yang mendadak seperti yang dialami Dewa Arak ini sungguh menyulitkannya dalam menguasai ilmu 'Belalang Sakti'.
Dan kali ini, Dewa Arak seperti tidak bisa menggunakan ilmu. 'Belalang Sakti' dengan sempurna. Gerakannya kaku dari patah-patah. Menyerang pun kelihatannya hampir tidak pernah. Arya selalu mengajak lawan agar bertarung jarak jauh. Ini dilakukan agar pengaruh keris tidak terlalu menekannya. Beberapa kali Dewa Arak menyerang lawan dengan semburan araknya. Hebatnya, berkat tenaga dalamnya yang telah terlatih baik, semburan arak itu tak kalah dengan serangan senjata rahasia lainnya! Bila terkena, mampu merobek pakaian dan menembus daging!
Menggiriskan sekali akibat pertarungan yang terjadi antara Dewa Arak dan Brajageni. Suasana di sekitar arena pertarungan diliputi hawa dingin menusuk tulang. Sementara dari atas kepala Arya, mengepul uap berwarna putih tebal. Ini karena Dewa Arak mengerahkan ilmu 'Tenaga Sakti Inti Matahari' untuk mengurangi kekakuan yang melanda ototototnya.
"Hiaaat..!" Brajageni yang merasa di atas angin melompat menerjang. Dan dari atas, kerisnya ditusukkan ke arah ubun-ubun Arya.
Kali ini Arya tidak mengelakkan serangan. Dia, memekik keras seraya mengerahkan seluruh tenaga dalam. Dan bersamaan dengan itu, gucinya segera disampirkan di punggung. Lalu, kedua tangannya dihentakkan ke depan. Maka, angin keras berhawa panas menyengat seketika berhembus keras ke arah laki-laki bercaping itu. Memang, Dewa Arak mengerahkan jurus 'Pukulan Belalang'.
Hebat serangan beruntun yang dilakukan Dewa Arak. Akibat teriakan yang dikeluarkannya, tubuh Brajageni yang tengah di udara, kontan menggeliat. Tangan kanannya yang memegang keris nampak menggigil. Dada laki-laki bertubuh tinggi kurus ini terguncang hebat, dan telinganya pun terasa sakit bukan main. Di saat itulah serangan jurus 'Pukulan Belalang' Dewa Arak tiba, telak dan keras sekali menghantam dadanya.
Seketika itu juga tubuh Brajageni terlempar jauh ke belakang, dan kerisnya pun terlepas dari pegangan, terlempar entah ke mana. Dari mulut, hidung, dan telinganya, mengalir darah segar. Sekujur tubuhnya pun hangus. Brajageni tewas seketika sebelum sempat menyentuh tanah.
Brukkk...! Dengan mengeluarkan suara berdebuk keras, tubuh laki-laki tinggi kurus itu jatuh ke tanah.
"Hhh...!" Arya menghela napas lega, kemudian mengusap peluh yang membasahi wajahnya dengan punggung tangan. Ketika mata Dewa Arak melihat keris Brajageni yang terjatuh tadi, dia lalu memungutnya. Kemudian dimasukkan ke dalam sarungnya. Maka kini keris yang telah banyak meminta korban itu diselipkan di pinggangnya. Terpaksa Arya mengambil keris yang menggiriskan itu agar tidak jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Telah dirasakannya sendiri kemukjizatan keris itu. Dia memutuskan untuk menyimpannya di tempat yang aman.
"Sebuah pukulan jarak jauh yang ampuh...."
Tentu saja ucapan itu membuat Arya terperanjat. Cepat dia menoleh ke arah asal suara, dan tampak Malaikat Halilintar tengah memandangnya takjub. "Ah! Kau terlalu memuji, Ki," sahut Arya malu-malu. "O, ya. Bagaimana dengan Raja Racun...?"
"Hhh...!" Malaikat Halilintar menghela napas berat. Diliriknya sebentar pinggang Arya. Memang laki-laki tinggi kurus ini melihat pemuda berpakaian ungu itu menyelipkan keris. Tapi karena dia sendiri tengah dilibat masalah, hal itu tidak dipedulikannya. "Dia kabur."
"Kabur?"
"Benar! Dia telah melemparkan sebuah benda kepadaku, kemudian meledak. Dan dari situ, keluar asap hitam beracun. Di saat itulah dia kabur tanpa aku dapat berbuat apa-apa."
"Kalau boleh kutahu, ada urusan apakah antara kau dengannya, Ki?" tanya Arya hati-hati.
"Dia membunuh muridku. Maka aku harus mencarinya, untuk membalaskan dendam. Setelah bertemu, kami bertarung, dan dia berhasil kukalahkan. Tapi sayang, dia berhasil melarikan diri dan bersembunyi. Bertahun-tahun aku berusaha mencarinya. Sampai akhirnya, kulihat muridnya di Desa Pucung. Aku pun lalu tinggal di sini, berpura-pura menjadi guru silat untuk anak-anak kecil."
Malaikat Halilintar menghentikan ceritanya sejenak. "Dan akhirnya usahaku tidak sia-sia. Aku berhasil bertemu dengannya, hanya sayang... Dia berhasil kabur...."
"Lalu, mengapa waktu itu kau sepertinya tidak menyukai kedatanganku, Ki?" tanya Arya begitu teringat sikap laki-laki bertubuh tinggi kurus ini padanya.
"Aku khawatir, kau mengganggu usahaku. Takutnya pencarianku selama bertahun-tahun akan sia-sia."
Mendadak Malaikat Halilintar menghentikan ucapannya, lalu menoleh. Dewa Arak pun bersikap demikian. Mereka mendengar banyak langkah kaki menuju ke arah mereka yang ternyata penduduk Desa Pucung.
"Aku pergi dulu, Dewa Arak. Aku harus mencari si keparat itu...!" Setelah berkata demikian, Malaikat Halilintar melesat meninggalkan tempat itu.
Arya menatap tubuh laki-laki tinggi kurus itu sebentar, kemudian menatap ke arah penduduk desa. Para penduduk memang tahu kalau dia dan Ki Jayus pergi untuk menumpas pembunuh kejam itu. Setelah menatap tubuh Brajageni sesaat, Dewa Arak kemudian melesat meninggalkan tempat itu. Angin yang tidak lagi dingin menggigilkan, meniup kulit pemuda berambut putih keperakan itu.
Selanjutnya,