Sejuknya Kampung Halaman
Bagian 08
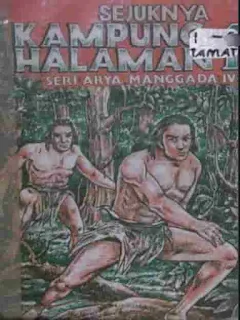
KI RESADANA hanya dapat menggelengkan kepalanya. Sekali lagi ia bergumam, “Anak-anak yang keras kepala...!”
Dalam pada itu, Manggada dan Laksana pun telah pergi ke rumah Ki Jagabaya. Mereka ingin melaporkan hasil pertemuan mereka dengan Wira Sabet. Nampaknya pertemuan antara Wira Sabet dan bebahu padukuhan itu mungkin dilakukan. Namun masih tergantung pada Sura Gentong yang sikapnya lebih keras dari Wira Sabet. Apalagi kesalahan utama pada saat mereka terusir adalah pada Sura Gentong itu.
Demikianlah keduanya telah menyusuri jalan-jalan sepi sebagaimana mereka lihat sehari-hari. jika ada satu dua orang lewat, tentu dengan tergesa-gesa. Bahkan dibayangi oleh perasaan takut dan was-was. Mereka merasa bahwa setiap saat dapat terjadi malapetaka atas diri mereka.
Ketika Manggada dan Laksana memasuki halaman rumah Ki Jagabaya dan kemudian pergi ke pintu seketeng, maka seperti biasanya pintu itu tertutup dan agaknya diselarak. Karena itu, maka Manggadapun telah mengetuk pintu seketeng itu agak keras. Untuk beberapa saat Manggada dan Laksana menunggu. Baru kemudian mereka mendengar langkah kaki seseorang mendekati pintu seketeng.
“Siapa?” terdengar seseorang bertanya.
Manggada dan Laksana segera mengetahui bahwa yang betanya itu Sampurna, anak Ki Jagabaya. Karena itu, maka iapun menjawab, “Aku, Manggada dan Laksana.”
Sampurnapun mengenali suara itu. Karena itu, maka tanpa ragu-ragu iapun telah mengangkat selarak pintu seketeng itu. Demikian pintu itu terbuka, maka Sampurnapun mempersilahkan Manggada dan Laksana masuk. Setelah pintu seketeng itu diselarak lagi, maka Sampurna pun mengajak mereka langsung ke serambi.
Laksana mengerutkan dahinya ketika melihat Wisesa telah duduk di serambi itu pula. Sampurnalah yang kemudian berkata, “Wisesa memenuhi janjinya. Ia membawa bibit pohon kemuning!”
“O“ Manggada mengangguk-angguk. Iapun kemudian bertanya “Apakah kau mempunyai pohon kemuning di halaman rumahmu?”
“Ya...” jawab Wisesa “Kenapa?”
“Karena itulah maka kau dapat membawa bibit pohon kemuning bagi Tantri.” jawab Manggada.
“Jadi kenapa jika aku membawa bibit pohon kemuning bagi Tantri?” nada suara Wisesa semakin tinggi.
“Kenapa?” Manggada justru menjadi bingung. Namun kemudian ia melanjutkan “Maksudku, karena kau mempunyai pohon kemuning di rumah, maka kau dapat mencangkoknya dan membawanya kemari.”
“Jadi apa anehnya. Karena bibit pohon kemuning itu kau anggap sesuatu yang perlu dibicarakan?”
Manggada menarik nafas dalam-dalam. Ia berniat untuk menanggapinya, namun tiba-tiba saja Laksana menjawab, “Maksud kakang Manggada, bibit kemuning itu kau bawa dari rumahmu sendiri. Kau cangkok sendiri, sehingga tidak merugikan orang lain. Tadi paman Wira Sabet mencari bibit kemuning di halaman rumahnya, tetapi sudah hilang. Menilik bekasnya, baru kemarin atau tadi pagi bibit kemuning itu dicungkil orang.”
“Wira Sabet?” bertanya Wisesa. Tiba-tiba saja wajahnya menjadi tegang. “Darimana kau tahu bahwa paman Wira Sabet mencari bibit kemuningnya.”
“Kami baru datang dari rumahnya yang kosong dan kotor itu. Kebetulan paman Wira Sabet tadi datang menengoknya. Maksudnya menengok bibit kemuningnya itu.”
“Bohong...!“ bentak Wisesa.
“Buat apa kami berbohong? Kami sengaja menemuinya, karena kami memang sudah menyediakan diri untuk melakukannya. Kami sudah berjanji kepada Ki Jagabaya.”
“Kalian hanya membual. Tidak seorangpun yang berani menemui Wira Sabet.” geram Wisesa.
“Kami tidak berkeberatan jika kau tidak percaya. Tetapi jika Ki Jagabaya tidak mempercayai kami, kami persilahkan Ki Jagabaya menemui Ki Resa yang tinggal di sebelah rumah Wira Sabet yang kosong.”
Wajah Wisesa benar-benar menjadi tegang. Sementara itu Sampurna berkata, “Aku pecaya kalau Manggada dan Laksana telah menemui dan berbicara dengan Wira Sabet seperti yang kemarin dilakukannya”
“Ya!“ sahut Laksana “Bahkan kami sudah mendapat ijin Wira Sabet untuk memanjat dan memetik duwet atau manggis atau apa saja yang ada di halaman rumah itu, kecuali bibit kemuning. Namun ternyata bibit itu hilang...”
“Apakah Wira Sabet tidak menuduhmu?” bertanya Sampurna.
“Aku masih berada di sana waktu itu. Atau paman Wira Sabet memang mempercayai kami bahwa kami tidak akan melakukannya...” jawab Laksana.
Wajah Wisesa menjadi semakin tegang. Bahkan kemudian menjadi pucat. Dengan gagap ia berkata, “Tetapi, tetapi bibit ini aku bawa dari rumahku. Aku dapat membuktikannya. Pada dahan pohon kemuningku nampak bekas potongan baru di bawah cangkokan.”
“Besok jika paman Wira Sabet bertanya, biarlah aku yang menjawab sebagaimana kau katakan. Tetapi jika paman Wira Sabet tidak bertanya lagi tentang kemuningnya, biarlah kami berdiam diri saja.” sahut Laksana kemudian.
Tetapi pernyataan Laksana telah membuat Wisesa menjadi sangat gelisah. Seolah-olah ia akan dituduh oleh Wira Sabet, bahwa ia telah mengambil bibit pohon kemuning itu dari halaman rumah Wira Sabet. Namun pembicaraan merekapun terhenti. Tantri yang mendengar kehadiran Manggada dan Laksana telah menghidangkan minuman panas dan beberapa potong makanan.
Adalah di luar dugaan, bahwa ketika Tantri menghidangkan minuman itu, Wisesa berkata, “Tantri, jangan kau tanam dahulu bibit pohon kemuning itu. Atau kau tanam saja di longkangan dalam sehingga tidak mudah dilihat dari halaman...”
“Kenapa?” bertanya Tantri.
“Ternyata Wira Sabet juga sedang mencari bibit pohon kemuningnya yang hilang.” jawab Wisesa.
“Kenapa dengan Wira Sabet? Biar saja ia mencari bibit kemuningnya yang hilang. Besok aku akan menanam bibit itu di halaman depan.” jawab Tantri.
“Tetapi jangan besok, Jika Wira Sabet melihatnya, maka ia akan mengira bahwa bibit itu adalah miliknya.” berkata Wisesa dengan cemas.
“Bukankah aku punya mulut untuk menjelaskan, bahwa kemuning itu aku dapat dari kau...”
“Itulah yang aku cemaskan. Wira Sabet akan menuduhku mengambil bibit itu dari halaman rumahnya.”
“Tetapi bukankah itu tidak kau lakukan?” bertanya Tantri.
“Tidak. Aku tidak mengambil bibit itu dari halaman rumahnya. Apalagi mengambil bibit pohon kemuning, lewat pun aku tidak pernah.” jawab Wisesa.
“Jika demikian bukankah kau dapat mengatakannya.” suara Tantri mulai meninggi.
“Orang itu tentu tidak dapat diajak berbicara.” sahut Wisesa dengan wajah tegang.
“Sebaiknya kau pukul saja mulutnya jika ia menuduhmu tanpa alasan.”
“Tantri...“ potong Wisesa dengan serta merta “Jangan berkata begitu. Kata-katamu itu dapat menjeratmu ke dalam kesulitan.”
“Jika terjadi demikian, aku akan minta kau menolongku.”
Wajah Wisesa menjadi semakin tegang. Sementara itu Manggada dan Sampurna yang agaknya mengetahui bahwa Laksana hanya sekedar mengganggunya, tertawa di dalam hati. Tetapi mereka membiarkan Wisesa dicengkam oleh kecemasannya.
Sementara itu Tantri masih memiliki sifat-sifat kerasnya sejak masa kanak-kanak. Katanya selanjutnya, “Jika kau berkeberatan aku menanam pohon kemuning mu di halaman, bawa saja pulang. Maksudku menanam kemuningmu di halaman agar kelak aku selalu dapat memandangi dan menikmati kesejukan dan harum bungannya seandainya satu dua hari kau tidak datang mengunjungiku. Tetapi seleraku sekarang sudah hilang. Ambil dan bawa kembali kemuningmu. Besok aku akan minta kepada Wira Sabet sebatang pohon kemuning.”
Tiba-tiba saja Laksana menyela, “Sebenarnya bukan Wira Sabet sendiri yang memerlukan bibit pohon kemuning itu. Tetapi anaknya, Pideksa yang tadi datang bersama ayahnya di bekas tempat tinggalnya itu.”
“Omong kosong.. “ bentak Wisesa.
“Aku tidak berbohong!” jawab Laksana “Sebelum ini aku belum pernah mengenal anak muda yang namanya Pideksa itu. Baru tadi aku melihat dan mengenalnya. Ia datang bersama paman Wira Sabet.”
“Pideksa...” tiba-tiba saja Tantri menyahui “Apakah ia ikut bersama ayahnya? Sudah lama aku tidak bertemu. Apakah ia sekarang kembali ke rumahnya? Ia tentu telah tumbuh menjadi anak muda yang gagah, kuat dan berani...!”
“Tantri...” potong Wisesa “Tetapi ia anak Wira Sabet.”
“Pideksa adalah kawan kita bermain sejak kanak-kanak, la termasuk satu di antara anak-anak yang berani, kuat dan tampan.”
“Wajah Wisesa menjadi sangat tegang. Namun tiba-tiba saja dahi Laksana berkerut, la menjadi tidak senang mendengar Tantri memuji Pideksa yang memang tumbuh menjadi anak muda yang gagah sebagaimana namanya.
Manggada hampir tidak dapat menahan tertawanya melihat wajah Laksana. Manggada tahu, bahwa ia ingin mengganggu Wisesa. Tetapi ternyata Laksana sendiri terkejut mendengar Tantri memuji anak muda itu. Namun dalam pada itu, pembicaraan merekapun terhenti. Terdengar pintu seketeng diketuk orang.
“Itu ayah datang...” berkata Sampurna yang mengenali cara ayahnya mengetuk pintu.
Sampurna pun kemudian bangkit dan melangkah menuju ke pintu seketeng, sementara Tantri pun bangkit pula sambil menjinjing nampan masuk ke ruang dalam. Tetapi di pintu ia sempat berkata kepada Laksana “Jika kau bertemu lagi dengan Pideksa, katakan, salamku baginya.”
Tantri memang menunggu sejenak, la sempat melihat wajah Wisesa kemerah-merahan. Namun Tantri sendiri tidak memperhatikan bahwa wajah Laksanapun menjadi semakin berkerut. Tetapi Laksana itupun menjawab “Baiklah. Aku akan menyampaikannya.”
Dalam pada itu, sesaat kemudian, Ki Jagabaya pun telah memasuki serambi itu pula. la pun langsung duduk bersama anak-anak muda itu. “Apakah kalian sudah lama duduk disini?” bertanya Ki Jagabaya.
Yang pertama-tama menjawab adalah Wisesa. “Belum paman. Aku datang untuk memenuhi janjiku, membawa bibit pohon kemuning. Tetapi aku minta Tantri tidak segera menanamnya, atau jika ia ingin segera menanam, biarlah ditanam di longkangan.”
“Kenapa?” bertanya Ki Jagabaya.
Wisesapun menceriterakan tentang Wira Sabet yang sedang mencari bibit kemuningnya. Ki Jagabaya tertawa, lapun kemudian bertanya kepada Manggada tanpa menyinggung soal bibit kemuning itu lagi. “Apakah kau sudah bertemu dengan Wira Sabet?”
“Ya, paman...” jawab Manggada.
“Kau sudah mengatakan kepadanya tentang satu kemungkinan untuk membicarakan persoalan yang sedang mencengkam padukuhan Gemawang ini?” bertanya Ki Jagabaya.
“Ya. Aku sudah bertemu dan berbicara dengan paman Wira Sabet. Bahkan paman Wira Sabet tadi datang bersama anaknya, Pideksa, kawan bermain di masa kanak-kanak” jawab Manggada.
Wisesa yang mendengarkan pembicaraan itu justru menjadi semakin yakin, bahwa Pideksa telah mempersoalkan kemuningnya yang hilang.
“Bagaimana hasil pembicaraanmu?” bertanya Ki Jagabaya kemudian.
“Menurut pendapatku...” jawab Manggada “Paman Wira Sabet akan membuka satu kesempatan satu pembicaraan meskipun syaratnya tentu cukup berat. Tetapi aku tidak tahu, bagaimana, pendapat paman Sura Gentong yang nampaknya bersikap lebih keras.”
“Itu dapat dimengerti. Persoalannya memang bersumber dari tingkah laku Sura Gentong.” jawab Ki Jagabaya.
“Ya. Namun paman Wira Sabet masih juga menganggap bahwa Ki Jagabaya mendendamnya karena ketika Wira Sabet berusaha membantu adiknya, ia telah melukai Ki Jagabaya.”
Ki Jagabaya tersenyum. Katanya, “Kita memang saling mencurigai. Tetapi apakah Wira Sabet menentukan satu waktu dan satu tempat untuk pertemuan itu?”
“Belum Ki Jagabaya” jawab Manggada “Paman Wira Sabet masih ingin berbicara dengan adiknya.”
Ki Jagabaya mengangguk-angguk. Sementara Wisesa berkata, “Nah, bukankah pendapatku akan dapat menyelamatkan padukuhan Gemawang ini?”
Ki Jagabaya justru termangu-mangu sejenak. Dipandanginya Wajah anak muda itu dengan tajamnya. Sehingga Wisesapun telah menunduk. Namun kemudian Ki Jagabaya itu berkata, “Ya Wisesa. Aku hargai pendapatmu. Mudah-mudahan pendapatmu nanti memberikan arti bagi padukuhan Gemawang ini”
“Mudah-mudahan paman...“ sahut Wisesa sambil mengangguk-angguk. Kebanggaan telah mulai mekar diliatinya. Jika usaha itu berhasil, maka namanya tentu akan selalu disebut-sebut oleh orang-orang padukuhan Gemawang. Wisesa akan dapat dianggap sebagai seorang yang telah membebaskan Gemawang dari cengkeraman ketakutan kecemasan dan kecurigaan.
Namun dalam pada itu, Ki Jagabaya itupun berkata, “Manggada. Aku tidak bermaksud mengurangi arti dari usahamu. Tetapi kita memang tidak dapat terlalu berpengharapan. Sura Gentong dan apalagi campur tangan Ki Sapa Aruh, akan sangat berpengaruh. Meskipun demikian, kita akan menunggu hasil pertemuanmu kemudian dengan Wira Sabet.”
“Besok mudah-mudahan paman Wira Sabet dapat memberikan keterangan” jawab Manggada.
Ki Jagabaya mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, “Nah, silahkan kalian berbincang sambil minum. Biarlah Tantri membuat minuman hangat lagi. Aku akan beristirahat. Besok, jika aku sudah mendapat keterangan, aku akan menghadap Ki Bekel yang seakan-akan sudah menjadi putus asa sekarang ini”
Demikianlah, maka Ki Jagabaya itupun kemudian meninggalkan anak-anak muda itu yang duduk di serambi itu. Wisesa yang agak kecewa dengan pendapat Ki Jagabaya yang terakhir itu berkata, “Ki Jagabaya kadang-kadang memang menjadi kehilangan harapan. Seharusnya tidak demikian. Tanda-tandanya sudah menjadi semakin jelas, bahwa persoalan padukuhan ini akan dapat dipecahkan. Jika Ki Jagabaya dan kelompok Wira Sabet itu sempat bertemu, maka akan dapat dipastikan dapat dicapai satu persetujuan. Tetapi padukuhan Gemawang memang harus bersedia memberikan pengorbanan sebagai imbalan kepada kelompok Wira Sabet itu. Tanpa kesediaan Gemawang untuk memberikan imbalan sepantasnya, maka memang sulit untuk dapat dicari penyelesaian.”
Manggada, Laksana dan ternyata juga Sampurna mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba Laksana berkata, “Tetapi ternyata kemudian bahwa yang kami lakukan itu sangat berbahaya. Aku jadi ngeri setelah aku sempat memikirkannya. Karena itu sebaiknya niat untuk menemuinya dibatalkan saja”
“Apa?” Wisesa itu hapir berteriak “Apa maksudmu?”
“Tidak ada maksud apa-apa. Tetapi aku menjadi ketakutan.” jawab Laksana.
“Tetapi kau sudah menyatakan kesediaanimu kepada Ki Jagabaya untuk melanjutkan pembicaraan itu."
“Tadi aku tidak merasa takut. Tiba-tiba saja perasaan takut itu seperti tumbuh di dalam hatiku. Semakin lama menjadi semakin besar dan rimbun. Akhirnya seisi hatiku telah dipenuhi oleh perasaan takut itu”
“Tidak. Kau tidak dapat mengurungkannya.“ bentak Wisesa.
Laksana masih akan menjawab, tetapi Manggada telah mendahului, “Baiklah Wisesa. Kami akan tetap berusaha untuk meneruskan tugas kami yang sudah kami rintis ini”
Laksana mengerutkan keningnya. Namun ia masih harus menahan tertawanya. Demikian pula Sampurna. Namun Manggada sendiri telah menjadi letih mendengar Laksana yang selalu mengganggu Wisesa. Dalam pada itu, untuk beberapa saat, anak-anak muda itu masih berbincang-bincang. Wisesa masih juga sempat berkata,
“Kalian tinggal melaksanakan. Mungkin kalian memang mengalami kesulitan atau diperlukan keberanian. Tetapi bagaimanapun juga nilai gagasan yang berarti selalu lebih berharga daripada pelaksanaannya betapapun sulitnya. Gagasan timbul karena kecerdasan penalaran, sedangkan pelaksanaan hanyalah sekedar mewujudkan gagasan itu. betapapun berat dan sulitnya.”
Manggada mengangguk-angguk. Katanya “Ya. Kami memang harus mengakui. Tanpa gagasan yang baik, maka tidak akan ada kerja yang baik dan bernilai tinggi”
“Nah, dengan demikian, maka tidak sewajarnya jika kalian mengurungkan kesediaan kalian untuk berbicara dengan Wira Sabet dan Sura Gentong”
Laksana yang sudah beringsut dan siap untuk menyahut, telah didahului pula oleh Manggada, “Tidak. Kami tidak akan berhenti berusaha. Apalagi karena Wira Sabet mau mengajak anaknya yang telah kita kenal dengan baik. Mudah-mudahan Pideksa dapat menjadi rambatan untuk mendapatkan satu kesamaan sikap untuk menemukan pemecahan bagi kesulitan yang terjadi di padukuhan Gemawang ini”
Wisesa mengangguk-angguk. Katanya “Baiklah. Aku berharap bahwa kalian berhasil. Jika kalian berhasil, maka kalian akan merupakan bagian dari keberhasilan gagasanku”
Laksana hampir tidak dapat menahan diri lagi. Tetapi ketika ia melihat Sampurna tersenyum-senyum, maka lapun menarik nafas dalam-dalam. Namun dalam pada itu, maka Manggada dan Laksana yang sudah merasa cukup lama duduk di serambi rumah Ki Jagabaya itupun telah minta diri. Mereka masih akan berputar-putar, jika mungkin menemui kawan-kawan bermain mereka.
“Aku sudah bertemu dengan Timbang dan Perti.” berkata Manggada.
“Mereka sudah mempunyai anak.” jawab Sampurna.
“Mereka kawin muda.” jawab Manggada.
“Ya. Mereka harus bekerja keras untuk dapat hidup berkeluarga. Ketika mereka mulai merambah jalan yang mulai lancar setelah bekerja keras, tiba-tiba suasana padukuhan ini berubah. Seperti kebanyakan orang, kesejahteraan keluarga yang mereka rintis itu menjadi semakin menyusut lagi.”
Manggada mengangguk-angguk. Namun Sampurna masih berkata “Aku dapat mengerti bahwa Timbang tidak dapat ikut melibatkan diri dalam tugas ini. Ia memerlukan waktu dan perhatian sepenuhnya untuk menghidupi keluarganya meskipun anaknya baru seorang. Tetapi dalam keadaan yang rumit ini, maka waktunya sepenuhnya diberikan kepada keluarganya."
“Lebih dari itu” sahut Wisesa "Jika sesuatu terjadi atasnya, maka keluarganya akan menjadi hancur pula. Orang tua Timbang sebagaimana orang tua Perti tidak termasuk orang tua yang berkecukupan.”
Manggada masih saja mengangguk-angguk. Namun kemudian ia benar-benar telah minta diri. Bahkan Ki Jagabaya. Tantri dan ibunya juga turut melepas mereka sampai ke pintu seketeng.
Sepeninggal Manggada dan Laksana, maka yang duduk di serambi tinggal Sampurna dan Wisesa. Dengan nada tinggi Wisesa itu berkata, “Manggada sekarang menjadi semakin bengal dan bahkan sombong. Apalagi adik sepupunya. Apa sebenarnya yang terjadi atas mereka?”
“Apakah mereka terhitung sombong?” Sampurna justru bertanya “Aku melihat kesungguhan mereka menangani kesulitan yang dialami oleh padukuhan ini”
“Itulah yang aku maksudkan, bahwa mereka terlalu sombong.” jawab Wisesa.
“Bukankah kau juga menganjurkan agar mereka meneruskan tugas yang mereka bebankan atas pundak mereka sendiri?”
“Itu karena mereka sudah mulai melakukannya. Namun pada saatnya, jika usaha itu berhasil, keduanya akan menepuk dada, seakan-akan keberhasilan itu adalah karena gagasan mereka.”
Sampurna tersenyum. Katanya “Betapapun cemerlangnya satu gagasan, tetapi jika gagasan itu tidak dapat mewujud, maka gagasan itu tidak akan berarti sama sekali.”
“Tetapi gagasan itu merupakan pangkal dari satu langkah pelaksanaan. Tanpa gagasan, tidak akan ada apa-apa” jawab Wisesa.
“Ya” Sampurna mengangguk-angguk “Aku tidak menolak pendapatmu itu”
Wisesa termangu-mangu sejenak. Tetapi untuk sesaat ia justru terdiam. Tangannya sajalah yang kemudian menggapai mangkuk minumannya. Setelah minum seteguk maka Wisesa itupun berkata, “Sampurna, tolong katakan kepada Tantri, aku akan minta diri”
“Oh. Begitu tergesa-gesa?”
“Aku sudah lama duduk disini” jawab Wisesa.
Sampurna pun kemudian telah memanggil Tantri, karena Wisesa akan minta diri. Meskipun dengan agak segan, maka Tantri telah menuju ke serambi.
“Aku akan minta diri. Tantri...” berkata Wisesa “Besok aku akan datang lagi.”
Tetapi Tantri itupun justru bertanya “Bagaimana dengan bibit pohon kemuningmu?”
“Kenapa?” Wisesa justru bertanya.
Apakah kau akan membawanya pulang atau akan kau tinggal disini. Jika kau tinggal disini, aku akan menanamnya di halaman depan. Tetapi jika kau berkeberatan, bawa saja bibit itu pulang sekarang.”
“Tantri, seharusnya kau mengucapkan terima kasih kepadaku, bahwa aku telah membawakan bibit itu untukmu. Bukankah kau menginginkannya?”
“Bukankah aku sudah mengucapkan terima kasih itu ketika kau serahkan bibit itu kepadaku?”
“Kenapa kau tidak mau mengerti keadaanku? Aku hanya minta kau menunda untuk tidak segera menanam bibit itu di halaman. Jika kau ingin segera menanamnya, tanam saja di longkangan ini”
“Aku ingin menanamnya di halaman atau tidak sama sekali” jawab Tantri.
Sampurnalah yang kemudian menggamit Tantri. Terbayang di angan-angan Sampurna, Tantri di masa kanak-kanaknya memang sering berkelahi dengan Wisesa Tetapi setelah keduanya dewasa, maka sikap Wisesa mulai mengarah pada bentuk hubungan yang lebih bersunguh-sungguh.
Sampurna sendiri tidak akan mencampuri tanggapan Tantri terhadap Wisesa. Itu adalah hak dan wewenang Tantri sendiri sepenuhnya. Namun menanggapi sikap Tantri sebagaimana masa kanak-kanaknya itu, Sampurna ingin mencegahnya.
Tantri memang berpaling kepada kakaknya. Sementara Sampurna berkata, “Sudahlah, biarlah bibit itu ditinggal disitu.”
“Tetapi Wisesa berkeberatan aku menanam di halaman” berkata Tantri.
“Bukan begitu. Ia hanya minta kau menundanya saja” sahut Sampurna.
Tantri tidak menjawab. Tetapi ia menjadi kesal bahwa kakaknya justru telah membantu Wisesa. Tetapi dalam pada itu, Sampurna harus menahan tertawanya. Ia tahu bahwa Laksana tadi tentu hanya sekedar mengganggu Wisesa. Tetapi karena hati Wisesa memang lemah, maka anak muda itu segera menjadi gelisah dan kebingungan tanpa sempat menilai kebenaran dongeng Laksana itu.
Demikianlah, maka Wisesa itu telah minta diri. Baik kepada Sampurna maupun kepada Tantri. Namun tanggapan Tantri ternyata tidak sehangat yang diharapkan oleh Wisesa. Meskipun demikian Wisesa masih tetap berpengharapan bahwa Tantri akhirnya akan dapat ditundukkannya. Apalagi jika kemudian gagasannya untuk mencari pemecahan terhadap kesulitan yang dihadapi oleh padukuhan itu berhasil. Ia akan menjadi orang yang dianggap penting di padukuhan Gemawang.
Demikian Wisesa keluar dari regol halaman rumah Ki Jagabaya, maka iapun dengan tergesa-gesa melangkah menyusuri jalan pulang. Namun di sepanjang jalan ia masih saja memikirkan sikap Ki Jagabaya. Nampaknya perhatian Ki Jagabaya justru lebih banyak tertuju pada hasil kerja Manggada dan Laksana daripada menilai arti dari gagasannya yang besar itu.
“Nampaknya Ki Jagabaya lebih menghargai tenaga Manggada dan Laksana daripada kecemerlangan penalaranku?” berkata Wisesa di dalam hatinya. Namun kemudian iapun berkata “Tetapi yang penting adalah penilaian terakhir. Rakyat padukuhan ini tentu akan mengakui kebesaran gagasanku daripada sekedar kerja kasar Manggada dan Laksana.”
Sementara itu, Manggada dan Laksana memang masih berjalan mengitari padukuhannya yang sepi. Tidak banyak orang yang dijumpainya. Pada umumnya mereka yang sempal diajak berbincang-bincang meskipun hanya beberapa patah kata. memperingatkan agar Manggada dan Laksana menjadi lebih berhati-hati. Atau bahkan menarik diri sama sekali dari keterlibatannya dengan persoalan Wira Sabet dan Sura Gentong.
Tetapi Manggada dan Laksana hanya dapat mengucapkan terima kasih kepada mereka. Mereka berdua sudah bertekad untuk melibatkan diri mencari penyelesaian segera sehingga tatanan kehidupan di padukuhan Gcmawang dapat berjalan dengan wajar kembali.
Ketika Manggada dan Laksana sampai di rumah, maka merekapun telah menceriterakan apa yang telah mereka alami kepada Ki Kertasana, Ki Citrabawa dan Ki Pandi. Ternyata ketiganya tidak berkeberatan jika kedua anak muda itu meneruskan usaha mereka. Sambil mengangguk-angguk kecil Ki Kertasana berkata,
“Jika kalian berhasil menyelesaikan persoalan ini dengan tanpa kekerasan, maka Ki Bekel dan Ki Jagabaya tentu akan berterima kasih. Namun demikian, kalian tidak boleh lengah bahwa kemungkinan yang lain akan dapat terjadi, menilik sikap dan latar belakang kedua orang itu”
Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Mereka memang tidak boleh lengah meskipun agaknya Wira Sabet dapat diajak berbicara untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi oleh padukuhan Gemawang sehingga padukuhan itu akan dapat menemukan ujud kewajarannya sebagaimana sebelumnya.
Dalam pada itu, agaknya Ki Pandi juga merasa cemas bahwa sesuatu akan dapat terjadi atas kedua orang anak muda itu. Karena itu, maka katanya kepada Manggada dan Laksana,
“Jika kalian berdua tidak berkeberatan, ngger. Biarlah besok aku berada di rumah Ki Resadana selama kau menunggu kedatangan Wira Sabet di halaman rumahnya. Besok kita pergi lebih pagi dari saat-saat Wira Sabet biasanya datang. Mudah-mudahan Ki Resa tidak berkeberatan mengijinkan aku berada di rumahnya”
Ternyata Ki Kertasana dan Ki Citrabawa tidak berkeberatan. Mereka meyakini bahwa Ki Pandi adalah orang yang berilmu tinggi, sehingga kehadirannya akan dapat menjadi pelindung bagi Manggada dan Laksana apabila diperlukan.
Demikianlah, maka merekapun telah mengambil beberapa kesepakatan. Justru karena mereka berhadapan dengan dengan orang-orang yang sifatnya masih belum dimengerti sepenuhnya.
Menjelang malam, Ki Pandi yang terbiasa duduk-duduk di serambi bersama Manggada dan Laksana telah berada di serambi sebagaimana biasanya setelah mereka makan malam. Namun ketika gelap mulai menyelimuti padukuhan Gemawang, Ki Pandi pun berkata kepada kedua orang anak muda itu, “Aku akan melihat halaman rumah Wiira Sabet itu”
“Malam-malam begini?” bertanya Manggada.
“Bukankah lebih aman jika aku melakukannya di malam hari?” Ki Pandi justru bertanya.
“Untuk apa Ki Pandi?” bertanya Laksana pula.
“Aku hanya ingin sekedar melihatnya” jawab Ki Pandi.
“Tidak lebih dari sebuah lingkungan yang luas, kotor dan bagaikan hutan perdu.” berkata Manggada.
Ki Pandi tersenyum. Katanya, “Kalian tidak usah mengatakannya kepada orang tua kalian. Aku tidak terlalu lama”
Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Sementara Ki Pandipun kemudian turun ke halaman dan melangkah keluar pintu regol. Manggada dan Laksana masih berada di serambi. Lampu minyak yang redup masih berkedipan di pendapa.
“Apakah Ki Pandi benar-benar akan melihat rumah Wira Sabet yang telah kosong itu?” desis Laksana.
“Mungkin...” sahut Manggada “mungkin ada sesuatu yang akan dilakukan besok.”
Laksana mengangguk-angguk. Tetapi sulit menebak, apa yang akan dilakukan oleh orang bohgkok itu. Namun keduanya berharap bahwa ki Pandi akan tetap membantu mereka dalam segala keadaan. Ketika malam menjadi semakin dalam, Ki Kertasana yang melihat Manggada dan Laksana masih duduk di serambi telah mendatanginya dan bertanya, “Apakah kalian tidak akan segera pergi tidur?”
“Nanti ayah...” jawab Manggada “Udara di dalam terasa panas. Apalagi kami memang belum mengantuk”
Beruntunglah bahwa Ki Kertasana tidak bertanya tentang Ki Pandi. Sambil melangkah meninggalkan keduanya, Ki Kertasana berkata. “Segera tidur. Mari Midah larut malam”
“Baik ayah. Nanti sebentar kami akan segera tidur setelah udara sedikit menjadi sejuk” jawab Manggada.
Namun Ki Kertasana itupun segera hilang di balik pintu. Sementara itu Manggada dan Laksana masih saja duduk di serambi. Mereka masih saja menunggu Ki Pandi yang menurut keterangannya tidak akan terlalu lama. Tetapi ternyata sampai tengah malam, Ki Pandi masih belum kembali.
“Tetapi aku yakin bahwa ia akan kembali sebelum pagi” desis Manggada.
“Ya. Tetapi apa jawab kami jika paman atau ayah menanyakannya?” desis Laksana.
“Kita akan berkata berterus terang.” jawab Manggada.
Laksana mengangguk-angguk. Dengan demikian, maka Laksana justru tidak menjadi gelisah lagi. Namun ternyata seisi rumah itu telah tertidur, sehingga baik Ki Kertasana maupun Ki Citrabawa tidak lagi keluar dan bertanya apapun lagi kepada kedua orang anak muda itu.
Meskipun demikian, ketika dini hari tiba, kedua anak muda itu menjadi gelisah lagi. Mereka tidak lagi memikirkan pertanyaan-pertanyaan dari orang tua mereka, tetapi mereka benar-benar gelisah tentang Ki Pandi. Apakah Ki Pandi begitu saja meninggalkan mereka.
Namun jantung mereka yang bergejolak rasa-rasanya telah dihembus oleh angin sejuk ketika mereka melihat seorang yang bongkok memasuki regol halaman rumah itu. Berbareng Manggada dan Laksana bangkit berdiri. Sementara Ki Pandi justru mengerutkan dahi.
“Kalian belum tidur?” bertanya Ki Pandi.
“Kami menunggu.” jawab Manggada.
“Kenapa? Apakah kalian menduga bahwa aku tidak akan kembali?” bertanya Ki Pandi.
“Bukan begitu, Ki Pandi. Tetapi rasa-rasanya tidak adil jika kami tidur nyenyak sementara Ki Pandi sibuk sendiri sampai dini hari.” jawab Manggada. Namun ternyata ia tidak dapat menyembunyikan perasaan dan berkata dengan jujur. “Tetapi disamping itu, kami memang merasa cemas justru pada saat-saat yang menjadi semakin gawat.”
Ki Pandi yang kemudian juga duduk di amben di serambi itu tertawa. Katanya, “Kalian sudah bukan anak-anak lagi. Tetapi baiklah. Sekarang tidurlah. Aku juga akan tidur. Bukankah masih ada waktu untuk beristirahat?”
Manggada dan Laksanapun bangkit berdiri pula ketika Ki Pandi kemudian pergi ke biliknya. Namun Manggada dan Laksana masih juga berbicara di antara mereka tentang Ki Pandi yang pergi sampai dini hari. Meskipun Manggada dan Laksana baru tidur setelah dini, namun seperti biasanya mereka bangun pagi-pagi dan melakukan pekerjaan sehari-hari mereka. Mengisi jambangan di pakiwan dan mengisi gentong di dapur.
Seperti yang sudah direncanakan, maka Manggada dan Laksana hari itu berangkat lebih pagi dari hari-hari sebelumnya. Mereka pergi bersama Ki Pandi yang akan berada di rumah Ki Resadana jika Ki Resa tidak berkeberatan. Ketika hal itu disampaikan kepada Ki Resa, maka Ki Resa memang menjadi ragu-ragu.
“Ki Pandi tidak akan keluar dari dalam rumah ini paman...” berkata Manggada meyakinkan.
“Jadi untuk apa Ki Pandi berada disini?” bertanya Ki Resa.
“Ki Pandi hanya ingin meyakinkan ayah dan paman, bahwa yang aku lakukan tidak sangat berbahaya sebagaimana dibayangkan oleh ayah dan paman” jawab Manggada.
“Akulah yang justru memberikan gambaran bahwa yang kalian lakukan itu sangat berbahaya.” berkata Ki Resa kemudian.
“Untuk memberikan pertimbangan, maka ayah telah minta Ki Pandi untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi disini.” jawab Manggada.
Ki Resadana akhirnya berkata sambil menarik nafas dalam-dalam “Baiklah. Tetapi aku minta Ki Pandi tidak menampakkan diri apapun yang terjadi Ia orang asing disini sehingga akan dapat menarik perhatian dan bahkan mungkin menimbulkan persoalan yang berkepanjangan”
Ki Pandipun menyahut sambil mengangguk-angguk “Aku akan tetap berada di dalam Ki Resa. Aku juga tidak akan berani keluar rumah, apalagi jika orang-orang yang ditakuti itu sudah datang, aku hanya ingin mendengarkan dari dalam rumah ini sejauh dapat aku tangkap dengan telinga tuaku”
“Ya. Sebagian pembicaraan di sebelah dinding memang dapat didengar jika kita berdiri melekat di dinding halaman di belakang gandok.” jawab Ki Resa.
“Jika kita berdiri di tempat itu, apakah kita dapat dilihat dari luar halaman ini?”
“Tidak” jawab Ki Resa “Aku juga sering mendengarkan pembicaraaan anak-anak itu dengan Wira Sabet dari belakang dinding justru karena aku mencemaskan keadaan mereka. Tetapi jika orang-orang di halaman sebelah meloncati dinding batas halaman itu, mereka akan melihat bahwa kita sedang memperhatikan dan mendengarkan pembicaraan mereka”
Ki Pandi mengangguk-angguk. Katanya kemudian “Jika demikian aku akan dapat mendengarkan dari balik dinding itu.”
“Tetapi kita harus berhati-hati. Jika nafas kita dapat didengar dari sebelah, maka nasib kita akan menjadi sangat buruk.”
Ki Pandi masih saja mengangguk-angguk. Katanya “Aku akan berhati-hati, karena aku tahu akibat yang terjadi jika mereka mengetahuinya”
Demikianlah, Ki Resadana memang tidak dapat menolak meskipun sebenarnya lebih baik baginya jika tidak ada orang lain di halaman rumahnya. Demikianlah, maka Manggada dan Laksanapun kemudian telah memasuki halaman rumah Wira Sabet yang kotor itu. Seperti kemarin, mereka menunggu Wira Sabet datang untuk memberi keterangan apakah Wira Sabet dan Sura Gentong bersedia untuk berbicara dengan para bebahu padukuhan Gemawang.
Seperti yang dijanjikan, maka Wira Sabet telah datang pada waktunya. Seperti kemarin, Wira Sabet datang bersama Pideksa dan dua orang kawannya. Manggada dan Laksana pun segera menyongsongnya. Dengan nada tinggi Manggada berkata, “Selamat pagi paman. Kami juga baru saja datang...!”
Wira Sabet mengangguk sarnbil menjawab, “Selamat pagi. Kami datang sedikit lebih siang dari kemarin”
“Aku kira tidak paman. Matahari itu baru saja naik sepenggalah. Sinarnya belum menggatalkan kulit”
“Baiklah” berkata Wira Sabet kemudian dengan nada yang justru agak lunak. “Aku akan langsung pada persoalannya”
“Ya, paman. Kami memang menunggu-nunggu...” desis Manggada.
“Aku sudah membicarakan pesan para bebahu padukuhan ini. Aku sudah berbicara dengan Sura Gentong dan Ki Sapa Aruh. Tetapi ternyata mereka berpendapat lain.” jawab Wira Sabet.
“Maksud paman?” bertanya Manggada dengan jantung yang berdebar-debar.
“Aku semula setuju untuk berbicara, mencari kemungkinan-kemungkinannya. Kami akan mengajukan syarat-syarat untuk menapak pada satu keadaan yang lebih baik daripada sekarang. Tetapi banyak yang tidak aku mengerti. Sura Gentong dan Ki Sapa Aruh banyak memberikan pengertian kepadaku, bahwa usaha itu tidak lebih dari satu jebakan dan pengkhianatan.” jawab Wira Sabet.
“Kenapa sebuah jebakan dan pengkhianatan? Apakah paman kira, kami masih mempunyai kemungkinan untuk menjebak paman?” bertanya Manggada.
“Segala kemungkinan dapat terjadi, Manggada....” sahut Pideksa. “Kami sudah membicarakannya dengan panjang lebar. Hampir saja aku terpengaruh oleh kenangan masa kanak-kanakku, sehingga aku mencoba menentang sikap paman Sura Gentong. Namun setelah aku mendapat penjelasan dari paman Sura Gentong dan Ki Sapa Aruh, aku baru menyadari, bahwa pembicaraan tidak akan membuahkan apa-apa bagi kami selain kemungkinan buruk itu. Jebakan dan penghianatan.”
“Paman!“ Manggada berusaha menjelaskan “Kami bersikap jujur. Jika kami menjebak paman, kenapa tidak kami lakukan sekarang atau saat paman memasuki padukuhan ini besok atau lusa atau kapan saja? Tidak paman. Kami tidak mempunyai keberanian untuk itu. Sementara itu, orang-orang padukuhan ini menganggap bahwa melihat paman dari kejauhan saja akan dapat mendatangkan malapetaka baginya dan keluarganya. Siapa yang berani menyebut nama paman dan apalagi mencerca nama paman, maka rasa-rasanya orang itu akan tersuruk ke dalam bencana. Nah, dalam keadaan yang demikian, siapa yang berani menjebak dan berkhianat kepada paman Wira Sabet, paman Sura Gentong dan Ki Sapa Aruh yang belum aku kenal...”
“Luar biasa!“ Pideksalah yang berdesis “Kau adalah anak muda yang sangat berani. Selama ini aku mengamati tingkah laku orang-orang padukuhan ini. Tidak seorangpun yang berani berpapasan dengan ayah dan paman Sura Gentong. Seperti yang kau katakan, siapa yang sempat melihat ayah dan paman dari kejauhan, mereka akan mengalami malapetaka. Tetapi ternyata bahwa kau masih juga berani menemui ayah sekarang ini.”
“Aku terlalu yakin akan maksud baikku Pideksa. Aku yakin pula bahwa paman Wira Sabet masih juga sempat mendengarkan kata nuraninya sebagai anak kampung halaman ini. Dasar itulah yang mendorong aku untuk berani melakukan hal ini sekarang. Seberapa dalam dendam terpahat di hati paman Wira Sabet dan paman Sura Gentong, sedalam dendam yang terukir di hati Ki Jagabaya, namun aku yakin, bahwa lebih dalam lagi hasrat yang mendorong paman dan Ki Jagabaya untuk menemukan satu landasan awal bagi masa depan padukuhan ini.”
Wira Sabet itupun menarik nafas dalam-dalam. Sementara Pideksa itupun berkata “Aku mengerti Manggada. Tetapi ayah tidak berdiri sendiri. Itulah sebabnya, ayah tidak dapat mengambil keputusan sendiri, apalagi yang menyimpang dari rencana yang sudah disusun dengan mapan oleh ayah, paman dan Ki Sapa Aruh.”
Manggada termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba saja Manggada dan Laksana terkejut. Seorang yang berwajah garang memasuki halaman rumah yang kotor itu. Sura Gentong. Dengan wajah yang garang ia memandang Manggada dan Laksana yang sedang berbicara dengan Wira Sabet.
“Paman Sura Gentong...!” sapa Manggada.
Tetapi sikap Sura Gentong memang berbeda dengan Sikap Wira Sabet. Ketika Manggada beringsut untuk mendekat, Sura Gentong berkata lantang. “Tetap di tempatmu, aku akan pancung kepalamu....”
Dalam pada itu, Manggada dan Laksana pun telah pergi ke rumah Ki Jagabaya. Mereka ingin melaporkan hasil pertemuan mereka dengan Wira Sabet. Nampaknya pertemuan antara Wira Sabet dan bebahu padukuhan itu mungkin dilakukan. Namun masih tergantung pada Sura Gentong yang sikapnya lebih keras dari Wira Sabet. Apalagi kesalahan utama pada saat mereka terusir adalah pada Sura Gentong itu.
Demikianlah keduanya telah menyusuri jalan-jalan sepi sebagaimana mereka lihat sehari-hari. jika ada satu dua orang lewat, tentu dengan tergesa-gesa. Bahkan dibayangi oleh perasaan takut dan was-was. Mereka merasa bahwa setiap saat dapat terjadi malapetaka atas diri mereka.
Ketika Manggada dan Laksana memasuki halaman rumah Ki Jagabaya dan kemudian pergi ke pintu seketeng, maka seperti biasanya pintu itu tertutup dan agaknya diselarak. Karena itu, maka Manggadapun telah mengetuk pintu seketeng itu agak keras. Untuk beberapa saat Manggada dan Laksana menunggu. Baru kemudian mereka mendengar langkah kaki seseorang mendekati pintu seketeng.
“Siapa?” terdengar seseorang bertanya.
Manggada dan Laksana segera mengetahui bahwa yang betanya itu Sampurna, anak Ki Jagabaya. Karena itu, maka iapun menjawab, “Aku, Manggada dan Laksana.”
Sampurnapun mengenali suara itu. Karena itu, maka tanpa ragu-ragu iapun telah mengangkat selarak pintu seketeng itu. Demikian pintu itu terbuka, maka Sampurnapun mempersilahkan Manggada dan Laksana masuk. Setelah pintu seketeng itu diselarak lagi, maka Sampurna pun mengajak mereka langsung ke serambi.
Laksana mengerutkan dahinya ketika melihat Wisesa telah duduk di serambi itu pula. Sampurnalah yang kemudian berkata, “Wisesa memenuhi janjinya. Ia membawa bibit pohon kemuning!”
“O“ Manggada mengangguk-angguk. Iapun kemudian bertanya “Apakah kau mempunyai pohon kemuning di halaman rumahmu?”
“Ya...” jawab Wisesa “Kenapa?”
“Karena itulah maka kau dapat membawa bibit pohon kemuning bagi Tantri.” jawab Manggada.
“Jadi kenapa jika aku membawa bibit pohon kemuning bagi Tantri?” nada suara Wisesa semakin tinggi.
“Kenapa?” Manggada justru menjadi bingung. Namun kemudian ia melanjutkan “Maksudku, karena kau mempunyai pohon kemuning di rumah, maka kau dapat mencangkoknya dan membawanya kemari.”
“Jadi apa anehnya. Karena bibit pohon kemuning itu kau anggap sesuatu yang perlu dibicarakan?”
Manggada menarik nafas dalam-dalam. Ia berniat untuk menanggapinya, namun tiba-tiba saja Laksana menjawab, “Maksud kakang Manggada, bibit kemuning itu kau bawa dari rumahmu sendiri. Kau cangkok sendiri, sehingga tidak merugikan orang lain. Tadi paman Wira Sabet mencari bibit kemuning di halaman rumahnya, tetapi sudah hilang. Menilik bekasnya, baru kemarin atau tadi pagi bibit kemuning itu dicungkil orang.”
“Wira Sabet?” bertanya Wisesa. Tiba-tiba saja wajahnya menjadi tegang. “Darimana kau tahu bahwa paman Wira Sabet mencari bibit kemuningnya.”
“Kami baru datang dari rumahnya yang kosong dan kotor itu. Kebetulan paman Wira Sabet tadi datang menengoknya. Maksudnya menengok bibit kemuningnya itu.”
“Bohong...!“ bentak Wisesa.
“Buat apa kami berbohong? Kami sengaja menemuinya, karena kami memang sudah menyediakan diri untuk melakukannya. Kami sudah berjanji kepada Ki Jagabaya.”
“Kalian hanya membual. Tidak seorangpun yang berani menemui Wira Sabet.” geram Wisesa.
“Kami tidak berkeberatan jika kau tidak percaya. Tetapi jika Ki Jagabaya tidak mempercayai kami, kami persilahkan Ki Jagabaya menemui Ki Resa yang tinggal di sebelah rumah Wira Sabet yang kosong.”
Wajah Wisesa benar-benar menjadi tegang. Sementara itu Sampurna berkata, “Aku pecaya kalau Manggada dan Laksana telah menemui dan berbicara dengan Wira Sabet seperti yang kemarin dilakukannya”
“Ya!“ sahut Laksana “Bahkan kami sudah mendapat ijin Wira Sabet untuk memanjat dan memetik duwet atau manggis atau apa saja yang ada di halaman rumah itu, kecuali bibit kemuning. Namun ternyata bibit itu hilang...”
“Apakah Wira Sabet tidak menuduhmu?” bertanya Sampurna.
“Aku masih berada di sana waktu itu. Atau paman Wira Sabet memang mempercayai kami bahwa kami tidak akan melakukannya...” jawab Laksana.
Wajah Wisesa menjadi semakin tegang. Bahkan kemudian menjadi pucat. Dengan gagap ia berkata, “Tetapi, tetapi bibit ini aku bawa dari rumahku. Aku dapat membuktikannya. Pada dahan pohon kemuningku nampak bekas potongan baru di bawah cangkokan.”
“Besok jika paman Wira Sabet bertanya, biarlah aku yang menjawab sebagaimana kau katakan. Tetapi jika paman Wira Sabet tidak bertanya lagi tentang kemuningnya, biarlah kami berdiam diri saja.” sahut Laksana kemudian.
Tetapi pernyataan Laksana telah membuat Wisesa menjadi sangat gelisah. Seolah-olah ia akan dituduh oleh Wira Sabet, bahwa ia telah mengambil bibit pohon kemuning itu dari halaman rumah Wira Sabet. Namun pembicaraan merekapun terhenti. Tantri yang mendengar kehadiran Manggada dan Laksana telah menghidangkan minuman panas dan beberapa potong makanan.
Adalah di luar dugaan, bahwa ketika Tantri menghidangkan minuman itu, Wisesa berkata, “Tantri, jangan kau tanam dahulu bibit pohon kemuning itu. Atau kau tanam saja di longkangan dalam sehingga tidak mudah dilihat dari halaman...”
“Kenapa?” bertanya Tantri.
“Ternyata Wira Sabet juga sedang mencari bibit pohon kemuningnya yang hilang.” jawab Wisesa.
“Kenapa dengan Wira Sabet? Biar saja ia mencari bibit kemuningnya yang hilang. Besok aku akan menanam bibit itu di halaman depan.” jawab Tantri.
“Tetapi jangan besok, Jika Wira Sabet melihatnya, maka ia akan mengira bahwa bibit itu adalah miliknya.” berkata Wisesa dengan cemas.
“Bukankah aku punya mulut untuk menjelaskan, bahwa kemuning itu aku dapat dari kau...”
“Itulah yang aku cemaskan. Wira Sabet akan menuduhku mengambil bibit itu dari halaman rumahnya.”
“Tetapi bukankah itu tidak kau lakukan?” bertanya Tantri.
“Tidak. Aku tidak mengambil bibit itu dari halaman rumahnya. Apalagi mengambil bibit pohon kemuning, lewat pun aku tidak pernah.” jawab Wisesa.
“Jika demikian bukankah kau dapat mengatakannya.” suara Tantri mulai meninggi.
“Orang itu tentu tidak dapat diajak berbicara.” sahut Wisesa dengan wajah tegang.
“Sebaiknya kau pukul saja mulutnya jika ia menuduhmu tanpa alasan.”
“Tantri...“ potong Wisesa dengan serta merta “Jangan berkata begitu. Kata-katamu itu dapat menjeratmu ke dalam kesulitan.”
“Jika terjadi demikian, aku akan minta kau menolongku.”
Wajah Wisesa menjadi semakin tegang. Sementara itu Manggada dan Sampurna yang agaknya mengetahui bahwa Laksana hanya sekedar mengganggunya, tertawa di dalam hati. Tetapi mereka membiarkan Wisesa dicengkam oleh kecemasannya.
Sementara itu Tantri masih memiliki sifat-sifat kerasnya sejak masa kanak-kanak. Katanya selanjutnya, “Jika kau berkeberatan aku menanam pohon kemuning mu di halaman, bawa saja pulang. Maksudku menanam kemuningmu di halaman agar kelak aku selalu dapat memandangi dan menikmati kesejukan dan harum bungannya seandainya satu dua hari kau tidak datang mengunjungiku. Tetapi seleraku sekarang sudah hilang. Ambil dan bawa kembali kemuningmu. Besok aku akan minta kepada Wira Sabet sebatang pohon kemuning.”
Tiba-tiba saja Laksana menyela, “Sebenarnya bukan Wira Sabet sendiri yang memerlukan bibit pohon kemuning itu. Tetapi anaknya, Pideksa yang tadi datang bersama ayahnya di bekas tempat tinggalnya itu.”
“Omong kosong.. “ bentak Wisesa.
“Aku tidak berbohong!” jawab Laksana “Sebelum ini aku belum pernah mengenal anak muda yang namanya Pideksa itu. Baru tadi aku melihat dan mengenalnya. Ia datang bersama paman Wira Sabet.”
“Pideksa...” tiba-tiba saja Tantri menyahui “Apakah ia ikut bersama ayahnya? Sudah lama aku tidak bertemu. Apakah ia sekarang kembali ke rumahnya? Ia tentu telah tumbuh menjadi anak muda yang gagah, kuat dan berani...!”
“Tantri...” potong Wisesa “Tetapi ia anak Wira Sabet.”
“Pideksa adalah kawan kita bermain sejak kanak-kanak, la termasuk satu di antara anak-anak yang berani, kuat dan tampan.”
“Wajah Wisesa menjadi sangat tegang. Namun tiba-tiba saja dahi Laksana berkerut, la menjadi tidak senang mendengar Tantri memuji Pideksa yang memang tumbuh menjadi anak muda yang gagah sebagaimana namanya.
Manggada hampir tidak dapat menahan tertawanya melihat wajah Laksana. Manggada tahu, bahwa ia ingin mengganggu Wisesa. Tetapi ternyata Laksana sendiri terkejut mendengar Tantri memuji anak muda itu. Namun dalam pada itu, pembicaraan merekapun terhenti. Terdengar pintu seketeng diketuk orang.
“Itu ayah datang...” berkata Sampurna yang mengenali cara ayahnya mengetuk pintu.
Sampurna pun kemudian bangkit dan melangkah menuju ke pintu seketeng, sementara Tantri pun bangkit pula sambil menjinjing nampan masuk ke ruang dalam. Tetapi di pintu ia sempat berkata kepada Laksana “Jika kau bertemu lagi dengan Pideksa, katakan, salamku baginya.”
Tantri memang menunggu sejenak, la sempat melihat wajah Wisesa kemerah-merahan. Namun Tantri sendiri tidak memperhatikan bahwa wajah Laksanapun menjadi semakin berkerut. Tetapi Laksana itupun menjawab “Baiklah. Aku akan menyampaikannya.”
Dalam pada itu, sesaat kemudian, Ki Jagabaya pun telah memasuki serambi itu pula. la pun langsung duduk bersama anak-anak muda itu. “Apakah kalian sudah lama duduk disini?” bertanya Ki Jagabaya.
Yang pertama-tama menjawab adalah Wisesa. “Belum paman. Aku datang untuk memenuhi janjiku, membawa bibit pohon kemuning. Tetapi aku minta Tantri tidak segera menanamnya, atau jika ia ingin segera menanam, biarlah ditanam di longkangan.”
“Kenapa?” bertanya Ki Jagabaya.
Wisesapun menceriterakan tentang Wira Sabet yang sedang mencari bibit kemuningnya. Ki Jagabaya tertawa, lapun kemudian bertanya kepada Manggada tanpa menyinggung soal bibit kemuning itu lagi. “Apakah kau sudah bertemu dengan Wira Sabet?”
“Ya, paman...” jawab Manggada.
“Kau sudah mengatakan kepadanya tentang satu kemungkinan untuk membicarakan persoalan yang sedang mencengkam padukuhan Gemawang ini?” bertanya Ki Jagabaya.
“Ya. Aku sudah bertemu dan berbicara dengan paman Wira Sabet. Bahkan paman Wira Sabet tadi datang bersama anaknya, Pideksa, kawan bermain di masa kanak-kanak” jawab Manggada.
Wisesa yang mendengarkan pembicaraan itu justru menjadi semakin yakin, bahwa Pideksa telah mempersoalkan kemuningnya yang hilang.
“Bagaimana hasil pembicaraanmu?” bertanya Ki Jagabaya kemudian.
“Menurut pendapatku...” jawab Manggada “Paman Wira Sabet akan membuka satu kesempatan satu pembicaraan meskipun syaratnya tentu cukup berat. Tetapi aku tidak tahu, bagaimana, pendapat paman Sura Gentong yang nampaknya bersikap lebih keras.”
“Itu dapat dimengerti. Persoalannya memang bersumber dari tingkah laku Sura Gentong.” jawab Ki Jagabaya.
“Ya. Namun paman Wira Sabet masih juga menganggap bahwa Ki Jagabaya mendendamnya karena ketika Wira Sabet berusaha membantu adiknya, ia telah melukai Ki Jagabaya.”
Ki Jagabaya tersenyum. Katanya, “Kita memang saling mencurigai. Tetapi apakah Wira Sabet menentukan satu waktu dan satu tempat untuk pertemuan itu?”
“Belum Ki Jagabaya” jawab Manggada “Paman Wira Sabet masih ingin berbicara dengan adiknya.”
Ki Jagabaya mengangguk-angguk. Sementara Wisesa berkata, “Nah, bukankah pendapatku akan dapat menyelamatkan padukuhan Gemawang ini?”
Ki Jagabaya justru termangu-mangu sejenak. Dipandanginya Wajah anak muda itu dengan tajamnya. Sehingga Wisesapun telah menunduk. Namun kemudian Ki Jagabaya itu berkata, “Ya Wisesa. Aku hargai pendapatmu. Mudah-mudahan pendapatmu nanti memberikan arti bagi padukuhan Gemawang ini”
“Mudah-mudahan paman...“ sahut Wisesa sambil mengangguk-angguk. Kebanggaan telah mulai mekar diliatinya. Jika usaha itu berhasil, maka namanya tentu akan selalu disebut-sebut oleh orang-orang padukuhan Gemawang. Wisesa akan dapat dianggap sebagai seorang yang telah membebaskan Gemawang dari cengkeraman ketakutan kecemasan dan kecurigaan.
Namun dalam pada itu, Ki Jagabaya itupun berkata, “Manggada. Aku tidak bermaksud mengurangi arti dari usahamu. Tetapi kita memang tidak dapat terlalu berpengharapan. Sura Gentong dan apalagi campur tangan Ki Sapa Aruh, akan sangat berpengaruh. Meskipun demikian, kita akan menunggu hasil pertemuanmu kemudian dengan Wira Sabet.”
“Besok mudah-mudahan paman Wira Sabet dapat memberikan keterangan” jawab Manggada.
Ki Jagabaya mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, “Nah, silahkan kalian berbincang sambil minum. Biarlah Tantri membuat minuman hangat lagi. Aku akan beristirahat. Besok, jika aku sudah mendapat keterangan, aku akan menghadap Ki Bekel yang seakan-akan sudah menjadi putus asa sekarang ini”
Demikianlah, maka Ki Jagabaya itupun kemudian meninggalkan anak-anak muda itu yang duduk di serambi itu. Wisesa yang agak kecewa dengan pendapat Ki Jagabaya yang terakhir itu berkata, “Ki Jagabaya kadang-kadang memang menjadi kehilangan harapan. Seharusnya tidak demikian. Tanda-tandanya sudah menjadi semakin jelas, bahwa persoalan padukuhan ini akan dapat dipecahkan. Jika Ki Jagabaya dan kelompok Wira Sabet itu sempat bertemu, maka akan dapat dipastikan dapat dicapai satu persetujuan. Tetapi padukuhan Gemawang memang harus bersedia memberikan pengorbanan sebagai imbalan kepada kelompok Wira Sabet itu. Tanpa kesediaan Gemawang untuk memberikan imbalan sepantasnya, maka memang sulit untuk dapat dicari penyelesaian.”
Manggada, Laksana dan ternyata juga Sampurna mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba Laksana berkata, “Tetapi ternyata kemudian bahwa yang kami lakukan itu sangat berbahaya. Aku jadi ngeri setelah aku sempat memikirkannya. Karena itu sebaiknya niat untuk menemuinya dibatalkan saja”
“Apa?” Wisesa itu hapir berteriak “Apa maksudmu?”
“Tidak ada maksud apa-apa. Tetapi aku menjadi ketakutan.” jawab Laksana.
“Tetapi kau sudah menyatakan kesediaanimu kepada Ki Jagabaya untuk melanjutkan pembicaraan itu."
“Tadi aku tidak merasa takut. Tiba-tiba saja perasaan takut itu seperti tumbuh di dalam hatiku. Semakin lama menjadi semakin besar dan rimbun. Akhirnya seisi hatiku telah dipenuhi oleh perasaan takut itu”
“Tidak. Kau tidak dapat mengurungkannya.“ bentak Wisesa.
Laksana masih akan menjawab, tetapi Manggada telah mendahului, “Baiklah Wisesa. Kami akan tetap berusaha untuk meneruskan tugas kami yang sudah kami rintis ini”
Laksana mengerutkan keningnya. Namun ia masih harus menahan tertawanya. Demikian pula Sampurna. Namun Manggada sendiri telah menjadi letih mendengar Laksana yang selalu mengganggu Wisesa. Dalam pada itu, untuk beberapa saat, anak-anak muda itu masih berbincang-bincang. Wisesa masih juga sempat berkata,
“Kalian tinggal melaksanakan. Mungkin kalian memang mengalami kesulitan atau diperlukan keberanian. Tetapi bagaimanapun juga nilai gagasan yang berarti selalu lebih berharga daripada pelaksanaannya betapapun sulitnya. Gagasan timbul karena kecerdasan penalaran, sedangkan pelaksanaan hanyalah sekedar mewujudkan gagasan itu. betapapun berat dan sulitnya.”
Manggada mengangguk-angguk. Katanya “Ya. Kami memang harus mengakui. Tanpa gagasan yang baik, maka tidak akan ada kerja yang baik dan bernilai tinggi”
“Nah, dengan demikian, maka tidak sewajarnya jika kalian mengurungkan kesediaan kalian untuk berbicara dengan Wira Sabet dan Sura Gentong”
Laksana yang sudah beringsut dan siap untuk menyahut, telah didahului pula oleh Manggada, “Tidak. Kami tidak akan berhenti berusaha. Apalagi karena Wira Sabet mau mengajak anaknya yang telah kita kenal dengan baik. Mudah-mudahan Pideksa dapat menjadi rambatan untuk mendapatkan satu kesamaan sikap untuk menemukan pemecahan bagi kesulitan yang terjadi di padukuhan Gemawang ini”
Wisesa mengangguk-angguk. Katanya “Baiklah. Aku berharap bahwa kalian berhasil. Jika kalian berhasil, maka kalian akan merupakan bagian dari keberhasilan gagasanku”
Laksana hampir tidak dapat menahan diri lagi. Tetapi ketika ia melihat Sampurna tersenyum-senyum, maka lapun menarik nafas dalam-dalam. Namun dalam pada itu, maka Manggada dan Laksana yang sudah merasa cukup lama duduk di serambi rumah Ki Jagabaya itupun telah minta diri. Mereka masih akan berputar-putar, jika mungkin menemui kawan-kawan bermain mereka.
“Aku sudah bertemu dengan Timbang dan Perti.” berkata Manggada.
“Mereka sudah mempunyai anak.” jawab Sampurna.
“Mereka kawin muda.” jawab Manggada.
“Ya. Mereka harus bekerja keras untuk dapat hidup berkeluarga. Ketika mereka mulai merambah jalan yang mulai lancar setelah bekerja keras, tiba-tiba suasana padukuhan ini berubah. Seperti kebanyakan orang, kesejahteraan keluarga yang mereka rintis itu menjadi semakin menyusut lagi.”
Manggada mengangguk-angguk. Namun Sampurna masih berkata “Aku dapat mengerti bahwa Timbang tidak dapat ikut melibatkan diri dalam tugas ini. Ia memerlukan waktu dan perhatian sepenuhnya untuk menghidupi keluarganya meskipun anaknya baru seorang. Tetapi dalam keadaan yang rumit ini, maka waktunya sepenuhnya diberikan kepada keluarganya."
“Lebih dari itu” sahut Wisesa "Jika sesuatu terjadi atasnya, maka keluarganya akan menjadi hancur pula. Orang tua Timbang sebagaimana orang tua Perti tidak termasuk orang tua yang berkecukupan.”
Manggada masih saja mengangguk-angguk. Namun kemudian ia benar-benar telah minta diri. Bahkan Ki Jagabaya. Tantri dan ibunya juga turut melepas mereka sampai ke pintu seketeng.
Sepeninggal Manggada dan Laksana, maka yang duduk di serambi tinggal Sampurna dan Wisesa. Dengan nada tinggi Wisesa itu berkata, “Manggada sekarang menjadi semakin bengal dan bahkan sombong. Apalagi adik sepupunya. Apa sebenarnya yang terjadi atas mereka?”
“Apakah mereka terhitung sombong?” Sampurna justru bertanya “Aku melihat kesungguhan mereka menangani kesulitan yang dialami oleh padukuhan ini”
“Itulah yang aku maksudkan, bahwa mereka terlalu sombong.” jawab Wisesa.
“Bukankah kau juga menganjurkan agar mereka meneruskan tugas yang mereka bebankan atas pundak mereka sendiri?”
“Itu karena mereka sudah mulai melakukannya. Namun pada saatnya, jika usaha itu berhasil, keduanya akan menepuk dada, seakan-akan keberhasilan itu adalah karena gagasan mereka.”
Sampurna tersenyum. Katanya “Betapapun cemerlangnya satu gagasan, tetapi jika gagasan itu tidak dapat mewujud, maka gagasan itu tidak akan berarti sama sekali.”
“Tetapi gagasan itu merupakan pangkal dari satu langkah pelaksanaan. Tanpa gagasan, tidak akan ada apa-apa” jawab Wisesa.
“Ya” Sampurna mengangguk-angguk “Aku tidak menolak pendapatmu itu”
Wisesa termangu-mangu sejenak. Tetapi untuk sesaat ia justru terdiam. Tangannya sajalah yang kemudian menggapai mangkuk minumannya. Setelah minum seteguk maka Wisesa itupun berkata, “Sampurna, tolong katakan kepada Tantri, aku akan minta diri”
“Oh. Begitu tergesa-gesa?”
“Aku sudah lama duduk disini” jawab Wisesa.
Sampurna pun kemudian telah memanggil Tantri, karena Wisesa akan minta diri. Meskipun dengan agak segan, maka Tantri telah menuju ke serambi.
“Aku akan minta diri. Tantri...” berkata Wisesa “Besok aku akan datang lagi.”
Tetapi Tantri itupun justru bertanya “Bagaimana dengan bibit pohon kemuningmu?”
“Kenapa?” Wisesa justru bertanya.
Apakah kau akan membawanya pulang atau akan kau tinggal disini. Jika kau tinggal disini, aku akan menanamnya di halaman depan. Tetapi jika kau berkeberatan, bawa saja bibit itu pulang sekarang.”
“Tantri, seharusnya kau mengucapkan terima kasih kepadaku, bahwa aku telah membawakan bibit itu untukmu. Bukankah kau menginginkannya?”
“Bukankah aku sudah mengucapkan terima kasih itu ketika kau serahkan bibit itu kepadaku?”
“Kenapa kau tidak mau mengerti keadaanku? Aku hanya minta kau menunda untuk tidak segera menanam bibit itu di halaman. Jika kau ingin segera menanamnya, tanam saja di longkangan ini”
“Aku ingin menanamnya di halaman atau tidak sama sekali” jawab Tantri.
Sampurnalah yang kemudian menggamit Tantri. Terbayang di angan-angan Sampurna, Tantri di masa kanak-kanaknya memang sering berkelahi dengan Wisesa Tetapi setelah keduanya dewasa, maka sikap Wisesa mulai mengarah pada bentuk hubungan yang lebih bersunguh-sungguh.
Sampurna sendiri tidak akan mencampuri tanggapan Tantri terhadap Wisesa. Itu adalah hak dan wewenang Tantri sendiri sepenuhnya. Namun menanggapi sikap Tantri sebagaimana masa kanak-kanaknya itu, Sampurna ingin mencegahnya.
Tantri memang berpaling kepada kakaknya. Sementara Sampurna berkata, “Sudahlah, biarlah bibit itu ditinggal disitu.”
“Tetapi Wisesa berkeberatan aku menanam di halaman” berkata Tantri.
“Bukan begitu. Ia hanya minta kau menundanya saja” sahut Sampurna.
Tantri tidak menjawab. Tetapi ia menjadi kesal bahwa kakaknya justru telah membantu Wisesa. Tetapi dalam pada itu, Sampurna harus menahan tertawanya. Ia tahu bahwa Laksana tadi tentu hanya sekedar mengganggu Wisesa. Tetapi karena hati Wisesa memang lemah, maka anak muda itu segera menjadi gelisah dan kebingungan tanpa sempat menilai kebenaran dongeng Laksana itu.
Demikianlah, maka Wisesa itu telah minta diri. Baik kepada Sampurna maupun kepada Tantri. Namun tanggapan Tantri ternyata tidak sehangat yang diharapkan oleh Wisesa. Meskipun demikian Wisesa masih tetap berpengharapan bahwa Tantri akhirnya akan dapat ditundukkannya. Apalagi jika kemudian gagasannya untuk mencari pemecahan terhadap kesulitan yang dihadapi oleh padukuhan itu berhasil. Ia akan menjadi orang yang dianggap penting di padukuhan Gemawang.
Demikian Wisesa keluar dari regol halaman rumah Ki Jagabaya, maka iapun dengan tergesa-gesa melangkah menyusuri jalan pulang. Namun di sepanjang jalan ia masih saja memikirkan sikap Ki Jagabaya. Nampaknya perhatian Ki Jagabaya justru lebih banyak tertuju pada hasil kerja Manggada dan Laksana daripada menilai arti dari gagasannya yang besar itu.
“Nampaknya Ki Jagabaya lebih menghargai tenaga Manggada dan Laksana daripada kecemerlangan penalaranku?” berkata Wisesa di dalam hatinya. Namun kemudian iapun berkata “Tetapi yang penting adalah penilaian terakhir. Rakyat padukuhan ini tentu akan mengakui kebesaran gagasanku daripada sekedar kerja kasar Manggada dan Laksana.”
Sementara itu, Manggada dan Laksana memang masih berjalan mengitari padukuhannya yang sepi. Tidak banyak orang yang dijumpainya. Pada umumnya mereka yang sempal diajak berbincang-bincang meskipun hanya beberapa patah kata. memperingatkan agar Manggada dan Laksana menjadi lebih berhati-hati. Atau bahkan menarik diri sama sekali dari keterlibatannya dengan persoalan Wira Sabet dan Sura Gentong.
Tetapi Manggada dan Laksana hanya dapat mengucapkan terima kasih kepada mereka. Mereka berdua sudah bertekad untuk melibatkan diri mencari penyelesaian segera sehingga tatanan kehidupan di padukuhan Gcmawang dapat berjalan dengan wajar kembali.
Ketika Manggada dan Laksana sampai di rumah, maka merekapun telah menceriterakan apa yang telah mereka alami kepada Ki Kertasana, Ki Citrabawa dan Ki Pandi. Ternyata ketiganya tidak berkeberatan jika kedua anak muda itu meneruskan usaha mereka. Sambil mengangguk-angguk kecil Ki Kertasana berkata,
“Jika kalian berhasil menyelesaikan persoalan ini dengan tanpa kekerasan, maka Ki Bekel dan Ki Jagabaya tentu akan berterima kasih. Namun demikian, kalian tidak boleh lengah bahwa kemungkinan yang lain akan dapat terjadi, menilik sikap dan latar belakang kedua orang itu”
Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Mereka memang tidak boleh lengah meskipun agaknya Wira Sabet dapat diajak berbicara untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi oleh padukuhan Gemawang sehingga padukuhan itu akan dapat menemukan ujud kewajarannya sebagaimana sebelumnya.
Dalam pada itu, agaknya Ki Pandi juga merasa cemas bahwa sesuatu akan dapat terjadi atas kedua orang anak muda itu. Karena itu, maka katanya kepada Manggada dan Laksana,
“Jika kalian berdua tidak berkeberatan, ngger. Biarlah besok aku berada di rumah Ki Resadana selama kau menunggu kedatangan Wira Sabet di halaman rumahnya. Besok kita pergi lebih pagi dari saat-saat Wira Sabet biasanya datang. Mudah-mudahan Ki Resa tidak berkeberatan mengijinkan aku berada di rumahnya”
Ternyata Ki Kertasana dan Ki Citrabawa tidak berkeberatan. Mereka meyakini bahwa Ki Pandi adalah orang yang berilmu tinggi, sehingga kehadirannya akan dapat menjadi pelindung bagi Manggada dan Laksana apabila diperlukan.
Demikianlah, maka merekapun telah mengambil beberapa kesepakatan. Justru karena mereka berhadapan dengan dengan orang-orang yang sifatnya masih belum dimengerti sepenuhnya.
Menjelang malam, Ki Pandi yang terbiasa duduk-duduk di serambi bersama Manggada dan Laksana telah berada di serambi sebagaimana biasanya setelah mereka makan malam. Namun ketika gelap mulai menyelimuti padukuhan Gemawang, Ki Pandi pun berkata kepada kedua orang anak muda itu, “Aku akan melihat halaman rumah Wiira Sabet itu”
“Malam-malam begini?” bertanya Manggada.
“Bukankah lebih aman jika aku melakukannya di malam hari?” Ki Pandi justru bertanya.
“Untuk apa Ki Pandi?” bertanya Laksana pula.
“Aku hanya ingin sekedar melihatnya” jawab Ki Pandi.
“Tidak lebih dari sebuah lingkungan yang luas, kotor dan bagaikan hutan perdu.” berkata Manggada.
Ki Pandi tersenyum. Katanya, “Kalian tidak usah mengatakannya kepada orang tua kalian. Aku tidak terlalu lama”
Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Sementara Ki Pandipun kemudian turun ke halaman dan melangkah keluar pintu regol. Manggada dan Laksana masih berada di serambi. Lampu minyak yang redup masih berkedipan di pendapa.
“Apakah Ki Pandi benar-benar akan melihat rumah Wira Sabet yang telah kosong itu?” desis Laksana.
“Mungkin...” sahut Manggada “mungkin ada sesuatu yang akan dilakukan besok.”
Laksana mengangguk-angguk. Tetapi sulit menebak, apa yang akan dilakukan oleh orang bohgkok itu. Namun keduanya berharap bahwa ki Pandi akan tetap membantu mereka dalam segala keadaan. Ketika malam menjadi semakin dalam, Ki Kertasana yang melihat Manggada dan Laksana masih duduk di serambi telah mendatanginya dan bertanya, “Apakah kalian tidak akan segera pergi tidur?”
“Nanti ayah...” jawab Manggada “Udara di dalam terasa panas. Apalagi kami memang belum mengantuk”
Beruntunglah bahwa Ki Kertasana tidak bertanya tentang Ki Pandi. Sambil melangkah meninggalkan keduanya, Ki Kertasana berkata. “Segera tidur. Mari Midah larut malam”
“Baik ayah. Nanti sebentar kami akan segera tidur setelah udara sedikit menjadi sejuk” jawab Manggada.
Namun Ki Kertasana itupun segera hilang di balik pintu. Sementara itu Manggada dan Laksana masih saja duduk di serambi. Mereka masih saja menunggu Ki Pandi yang menurut keterangannya tidak akan terlalu lama. Tetapi ternyata sampai tengah malam, Ki Pandi masih belum kembali.
“Tetapi aku yakin bahwa ia akan kembali sebelum pagi” desis Manggada.
“Ya. Tetapi apa jawab kami jika paman atau ayah menanyakannya?” desis Laksana.
“Kita akan berkata berterus terang.” jawab Manggada.
Laksana mengangguk-angguk. Dengan demikian, maka Laksana justru tidak menjadi gelisah lagi. Namun ternyata seisi rumah itu telah tertidur, sehingga baik Ki Kertasana maupun Ki Citrabawa tidak lagi keluar dan bertanya apapun lagi kepada kedua orang anak muda itu.
Meskipun demikian, ketika dini hari tiba, kedua anak muda itu menjadi gelisah lagi. Mereka tidak lagi memikirkan pertanyaan-pertanyaan dari orang tua mereka, tetapi mereka benar-benar gelisah tentang Ki Pandi. Apakah Ki Pandi begitu saja meninggalkan mereka.
Namun jantung mereka yang bergejolak rasa-rasanya telah dihembus oleh angin sejuk ketika mereka melihat seorang yang bongkok memasuki regol halaman rumah itu. Berbareng Manggada dan Laksana bangkit berdiri. Sementara Ki Pandi justru mengerutkan dahi.
“Kalian belum tidur?” bertanya Ki Pandi.
“Kami menunggu.” jawab Manggada.
“Kenapa? Apakah kalian menduga bahwa aku tidak akan kembali?” bertanya Ki Pandi.
“Bukan begitu, Ki Pandi. Tetapi rasa-rasanya tidak adil jika kami tidur nyenyak sementara Ki Pandi sibuk sendiri sampai dini hari.” jawab Manggada. Namun ternyata ia tidak dapat menyembunyikan perasaan dan berkata dengan jujur. “Tetapi disamping itu, kami memang merasa cemas justru pada saat-saat yang menjadi semakin gawat.”
Ki Pandi yang kemudian juga duduk di amben di serambi itu tertawa. Katanya, “Kalian sudah bukan anak-anak lagi. Tetapi baiklah. Sekarang tidurlah. Aku juga akan tidur. Bukankah masih ada waktu untuk beristirahat?”
Manggada dan Laksanapun bangkit berdiri pula ketika Ki Pandi kemudian pergi ke biliknya. Namun Manggada dan Laksana masih juga berbicara di antara mereka tentang Ki Pandi yang pergi sampai dini hari. Meskipun Manggada dan Laksana baru tidur setelah dini, namun seperti biasanya mereka bangun pagi-pagi dan melakukan pekerjaan sehari-hari mereka. Mengisi jambangan di pakiwan dan mengisi gentong di dapur.
Seperti yang sudah direncanakan, maka Manggada dan Laksana hari itu berangkat lebih pagi dari hari-hari sebelumnya. Mereka pergi bersama Ki Pandi yang akan berada di rumah Ki Resadana jika Ki Resa tidak berkeberatan. Ketika hal itu disampaikan kepada Ki Resa, maka Ki Resa memang menjadi ragu-ragu.
“Ki Pandi tidak akan keluar dari dalam rumah ini paman...” berkata Manggada meyakinkan.
“Jadi untuk apa Ki Pandi berada disini?” bertanya Ki Resa.
“Ki Pandi hanya ingin meyakinkan ayah dan paman, bahwa yang aku lakukan tidak sangat berbahaya sebagaimana dibayangkan oleh ayah dan paman” jawab Manggada.
“Akulah yang justru memberikan gambaran bahwa yang kalian lakukan itu sangat berbahaya.” berkata Ki Resa kemudian.
“Untuk memberikan pertimbangan, maka ayah telah minta Ki Pandi untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi disini.” jawab Manggada.
Ki Resadana akhirnya berkata sambil menarik nafas dalam-dalam “Baiklah. Tetapi aku minta Ki Pandi tidak menampakkan diri apapun yang terjadi Ia orang asing disini sehingga akan dapat menarik perhatian dan bahkan mungkin menimbulkan persoalan yang berkepanjangan”
Ki Pandipun menyahut sambil mengangguk-angguk “Aku akan tetap berada di dalam Ki Resa. Aku juga tidak akan berani keluar rumah, apalagi jika orang-orang yang ditakuti itu sudah datang, aku hanya ingin mendengarkan dari dalam rumah ini sejauh dapat aku tangkap dengan telinga tuaku”
“Ya. Sebagian pembicaraan di sebelah dinding memang dapat didengar jika kita berdiri melekat di dinding halaman di belakang gandok.” jawab Ki Resa.
“Jika kita berdiri di tempat itu, apakah kita dapat dilihat dari luar halaman ini?”
“Tidak” jawab Ki Resa “Aku juga sering mendengarkan pembicaraaan anak-anak itu dengan Wira Sabet dari belakang dinding justru karena aku mencemaskan keadaan mereka. Tetapi jika orang-orang di halaman sebelah meloncati dinding batas halaman itu, mereka akan melihat bahwa kita sedang memperhatikan dan mendengarkan pembicaraan mereka”
Ki Pandi mengangguk-angguk. Katanya kemudian “Jika demikian aku akan dapat mendengarkan dari balik dinding itu.”
“Tetapi kita harus berhati-hati. Jika nafas kita dapat didengar dari sebelah, maka nasib kita akan menjadi sangat buruk.”
Ki Pandi masih saja mengangguk-angguk. Katanya “Aku akan berhati-hati, karena aku tahu akibat yang terjadi jika mereka mengetahuinya”
Demikianlah, Ki Resadana memang tidak dapat menolak meskipun sebenarnya lebih baik baginya jika tidak ada orang lain di halaman rumahnya. Demikianlah, maka Manggada dan Laksanapun kemudian telah memasuki halaman rumah Wira Sabet yang kotor itu. Seperti kemarin, mereka menunggu Wira Sabet datang untuk memberi keterangan apakah Wira Sabet dan Sura Gentong bersedia untuk berbicara dengan para bebahu padukuhan Gemawang.
Seperti yang dijanjikan, maka Wira Sabet telah datang pada waktunya. Seperti kemarin, Wira Sabet datang bersama Pideksa dan dua orang kawannya. Manggada dan Laksana pun segera menyongsongnya. Dengan nada tinggi Manggada berkata, “Selamat pagi paman. Kami juga baru saja datang...!”
Wira Sabet mengangguk sarnbil menjawab, “Selamat pagi. Kami datang sedikit lebih siang dari kemarin”
“Aku kira tidak paman. Matahari itu baru saja naik sepenggalah. Sinarnya belum menggatalkan kulit”
“Baiklah” berkata Wira Sabet kemudian dengan nada yang justru agak lunak. “Aku akan langsung pada persoalannya”
“Ya, paman. Kami memang menunggu-nunggu...” desis Manggada.
“Aku sudah membicarakan pesan para bebahu padukuhan ini. Aku sudah berbicara dengan Sura Gentong dan Ki Sapa Aruh. Tetapi ternyata mereka berpendapat lain.” jawab Wira Sabet.
“Maksud paman?” bertanya Manggada dengan jantung yang berdebar-debar.
“Aku semula setuju untuk berbicara, mencari kemungkinan-kemungkinannya. Kami akan mengajukan syarat-syarat untuk menapak pada satu keadaan yang lebih baik daripada sekarang. Tetapi banyak yang tidak aku mengerti. Sura Gentong dan Ki Sapa Aruh banyak memberikan pengertian kepadaku, bahwa usaha itu tidak lebih dari satu jebakan dan pengkhianatan.” jawab Wira Sabet.
“Kenapa sebuah jebakan dan pengkhianatan? Apakah paman kira, kami masih mempunyai kemungkinan untuk menjebak paman?” bertanya Manggada.
“Segala kemungkinan dapat terjadi, Manggada....” sahut Pideksa. “Kami sudah membicarakannya dengan panjang lebar. Hampir saja aku terpengaruh oleh kenangan masa kanak-kanakku, sehingga aku mencoba menentang sikap paman Sura Gentong. Namun setelah aku mendapat penjelasan dari paman Sura Gentong dan Ki Sapa Aruh, aku baru menyadari, bahwa pembicaraan tidak akan membuahkan apa-apa bagi kami selain kemungkinan buruk itu. Jebakan dan penghianatan.”
“Paman!“ Manggada berusaha menjelaskan “Kami bersikap jujur. Jika kami menjebak paman, kenapa tidak kami lakukan sekarang atau saat paman memasuki padukuhan ini besok atau lusa atau kapan saja? Tidak paman. Kami tidak mempunyai keberanian untuk itu. Sementara itu, orang-orang padukuhan ini menganggap bahwa melihat paman dari kejauhan saja akan dapat mendatangkan malapetaka baginya dan keluarganya. Siapa yang berani menyebut nama paman dan apalagi mencerca nama paman, maka rasa-rasanya orang itu akan tersuruk ke dalam bencana. Nah, dalam keadaan yang demikian, siapa yang berani menjebak dan berkhianat kepada paman Wira Sabet, paman Sura Gentong dan Ki Sapa Aruh yang belum aku kenal...”
“Luar biasa!“ Pideksalah yang berdesis “Kau adalah anak muda yang sangat berani. Selama ini aku mengamati tingkah laku orang-orang padukuhan ini. Tidak seorangpun yang berani berpapasan dengan ayah dan paman Sura Gentong. Seperti yang kau katakan, siapa yang sempat melihat ayah dan paman dari kejauhan, mereka akan mengalami malapetaka. Tetapi ternyata bahwa kau masih juga berani menemui ayah sekarang ini.”
“Aku terlalu yakin akan maksud baikku Pideksa. Aku yakin pula bahwa paman Wira Sabet masih juga sempat mendengarkan kata nuraninya sebagai anak kampung halaman ini. Dasar itulah yang mendorong aku untuk berani melakukan hal ini sekarang. Seberapa dalam dendam terpahat di hati paman Wira Sabet dan paman Sura Gentong, sedalam dendam yang terukir di hati Ki Jagabaya, namun aku yakin, bahwa lebih dalam lagi hasrat yang mendorong paman dan Ki Jagabaya untuk menemukan satu landasan awal bagi masa depan padukuhan ini.”
Wira Sabet itupun menarik nafas dalam-dalam. Sementara Pideksa itupun berkata “Aku mengerti Manggada. Tetapi ayah tidak berdiri sendiri. Itulah sebabnya, ayah tidak dapat mengambil keputusan sendiri, apalagi yang menyimpang dari rencana yang sudah disusun dengan mapan oleh ayah, paman dan Ki Sapa Aruh.”
Manggada termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba saja Manggada dan Laksana terkejut. Seorang yang berwajah garang memasuki halaman rumah yang kotor itu. Sura Gentong. Dengan wajah yang garang ia memandang Manggada dan Laksana yang sedang berbicara dengan Wira Sabet.
“Paman Sura Gentong...!” sapa Manggada.
Tetapi sikap Sura Gentong memang berbeda dengan Sikap Wira Sabet. Ketika Manggada beringsut untuk mendekat, Sura Gentong berkata lantang. “Tetap di tempatmu, aku akan pancung kepalamu....”
Selanjutnya,