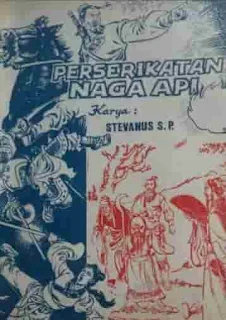Perserikatan Naga Api Jilid 05
MAU tidak mau Wi-hong dan adiknya jadi geleng-geleng kepala melihat keampuhan tongkat bambu itu. Menurut cerita ayah mereka, memang tongkat bambu Hong-koan Hweshio itu mengandung semacam kekuatan gaib yang sulit dicerna dengan akal. Perkembangan ilmu silat di India tidak sepesat di Tiongkok, tetapi orang India adalah orang-orang yang terkenal menyukai ilmu-ilmu sihir dan hal-hal yang bersifat gaib lainnya sehingga di bidang ini mereka dapat dikatakan bangsa yang paling unggul di dunia.
Tidak mengherankan pula kalau tongkat bambu butut milik Hong-koan Hwesio itupun mengandung kekuatan-kekuatan demikian. Jika digabungkan dengan ilmu silatnya yang tinggi, maka jadilah Hong-koan Hwesio Harimau Yang Tumbuh Sayapnya.
Kini Tong Wi-hong dan adiknya tidak ragu-ragu lagi. Cepat mereka berlutut di depan rahib itu sambil memanggil “pek-hu” (uwa).
“Nah, sekarang kalian percaya bukan?” kata Hong-koan Hwesio.
Tiba-tiba rahib itu mengibaskan lengan jubahnya yang kedodoran itu ke arah Wi-hong berdua yang berjarak berapa langkah dari padanya. Ternyata kebasan yang nampak sederhana itu telah menunjukkan ketinggian ilmu rahib kumal itu, sebab dalam satu gerakan sekaligus mengandung dua macam tenaga yang berbeda. Wi-hong dan Wi-lan terdorong oleh angin kebasan itu sehingga jatuh bergulingan di lantai yang berdebu, sebaliknya tongkat bambu yang mereka pegang itu justru “tersedot” dan melayang ke arah pemiliknya.
Rahib itu tertawa terbahak-bahak melihat kakak beradik itu menjadi tidak keruan macamnya karena tubuh dan muka mereka penuh debu. Biarpun dalam keadaan serba runyam, Wi-hong dan adiknya tidak marah namun justru ikut-ikutan tertawa. Julukan “rahib gila” yang diberikan oleh orang-orang dunia persilatan kepada Hong-koan Hwesio memang bukan nama kosong belaka dan cocok dengan sifat-sifatnya.
Sementara itu Hong-koan Hwesio telah melemparkan dua potong daging menjangan panggang itu kepada kakak beradik itu, sambil berkata, “Isilah perut kalian, jangan sampai masuk angin dan menjadi sakit.”
Sekarang Wi-hong dan Wi-lian mengerti bahwa rahib kumal ini tidak menyukai segala macam hal yang bertele-tele, termasuk segala macam basa-basi. Maka tanpa disuruh untuk kedua kalinya, kakak beradik itu segera menyambar daging yang dilemparkan itu dan langsung melahapnya, meskipun daging itu agaknya hangus sedikit.
Sedangkan Hong-koan Hwesio lalu bangkit sambil mengebas-ngebaskan jubahnya. “Aku merasa lega sekali bahwa kalian mempercayai aku. Kini kalian tunggu dulu di tempat ini. Aku akan pergi sebentar untuk mencarikan bekal serta dua ekor kuda untuk kalian, sebab kalian harus segera meninggalkan tempat ini. Semakin jauh meninggalkan paman Ting kalian itu, semakin baik buat kalian,” katanya.
Sahut Wi-hong, “Mana berani kami membikin repot pek-hu? Meskipun kami harus meninggalkan Pak-khia tetapi tidak perlu pek-hu yang bersusah payah mencarikan keperluan kami.”
Rahib kumal itu tertawa, “Maksudmu kalian akan mencari sendiri kuda dan bekal itu? Hemm, dengan kepandaianmu yang serendah itu mungkin kau akan tertangkap oleh kuku garuda atau oleh begundal-begundalnya paman Ting mu. Dengan demikian kalian justru akan semakin merepotkan aku untuk membebaskan kalian kembali.”
Keruan muka Tong Wi-hong menjadi merah mendengar sentilan tajam itu. Tapi ia tidak marah, karena hal itu memang kenyataan. Di kota kecil An-yang-shia, ia memang termasuk anak muda yang menonjol dalam hal ilmu silat. Tapi setelah melihat di dunia yang lebih luas, ternyata bahwa kepandaiannya itu belum berarti apa-apa dibandingkan dengan tokoh-tokoh dunia persilatan saat itu.
Dengan beberapa kali lompatan saja, Hong-koan Hwesio sudah pergi jauh. Meskipun tubuhnya tinggi besar, namun kelincahannya ternyata cukup mengagumkan. Bahkan Wi-hong dan adiknya menaksir bahwa kepandaian rahib kumal itu tentu tidak di sebelah bawah dari su-siok-co mereka, yaitu Soat-san-kiam-sian Oh Yu-thian.
Sementara rahib itu pergi, kakak beradik itu mulai merenungkan apa yang telah diucapkan oleh Hong-koan Hwesio mengenai diri Ting Ciau-kun. Benarkah Ting Ciau-kun berjiwa sebejat itu? Diam-diam timbul perasaan masygul yang sangat dalam di hati kakak beradik itu. Jika itu benar, maka rasanya dunia ini tidak sehangat yang mereka duga. Di balik muka yang manis belum tentu terdapat hati yang manis pula, bahkan mungkin terdapat ancaman yang keji.
Meskipun hati sedang gundah, tak urung gumpalan besar daging kijang itu lenyap juga ke dalam mulut mereka. Maklumlah, mereka belum sempat mengisi perut sejak kemarin sore, dan hari itu sudah cukup siang.
Tidak lama kemudian, dari kejauhan terdengar derap kaki kuda menuju ke arah kuil rusak tempat mereka berada itu. Didengarkan dari suara derapnya yang cepat dan mantap, nampaknya kuda yang sedang mendatangi itu merupakan kuda-kuda pilihan. Tong Wi-hong tetap santai saja mendengar suara itu, sebaliknya adiknya yang bersifat lebih cermat dari kakaknya segera menjadi tegang mukanya. Katanya,
“A-hong, kau dengar derap kaki kuda itu?”
“Aku dengar, memangnya ada apa?”
“Kau benar-benar ceroboh dan malas menggunakan otak,” demikian Wi-lian menggerutui kakaknya. “Coba kau dengar lebih cermat lagi. Derapnya cepat dan mantap, jelas merupakan kuda-kuda padang rumput yang terpilih. Orang yang menunggang kuda macam itu biasanya adalah kaum kuku garuda, lagipula tempat inipun belum jauh dari Pak-khia. Kau harus ingat, bahwa kita adalah resmi sebagai buronan pemerintah kerajaan.”
Mendengar itu Tong Wi-hong lalu melompat bangkit dengan beringas. Serunya, “Kebetulan sekali kalau yang datang ini adalah anjing-anjing Kaisar, biarlah kita hajar mereka untuk melampiaskan sakit hati keluarga kita. A-lian, bersiap!”
Namun adiknya kelihatannya tidak begitu bersemangat untuk berkelahi saat itu. Serunya, “Kakakku, kau harus ingat bahwa pada umumnya para perwira kerajaan itu berilmu cukup tinggi. Mampukah kita yang hanya berdua ini menghadapi mereka? Masih ingatkah kau akan kejadian di rumah kita pada waktu diserbu orang-orangnya Thio Ban-kiat? Waktu itu, bahkan dengan bantuan seorang tokoh selihai Su-siok-co Oh Yu-thian saja kita masih kewalahan menghadapi kerubutan mereka. Itu baru perwira-perwira daerah Kiang-se, dan perwira-perwira di ibukota kerajaan ini tentu memiliki kemampuan yang lebih baik daripada perwira-perwira daerah. Nah, apakah kita akan nekat berkelahi sehingga mampus dan tidak dapat lagi membalaskan sakit hati keluarga kita?”
Tong Wi-hong tidak menyahut, tapi uraian adiknya itu cukup masuk akal. Agaknya setelah peristiwa pemukulan Cia bok di An-yang-shia itu Tong Wi-lian berubah menjadi lebih sabar dan lebih cermat. Memang bukan mustahil bahwa Thio Ban-kiat atau Cia To-bun telah melaporkan tentang “pemberontakan” keluarga Tong itu ke pemerintah pusat, sehingga orang-orang keluarga Tong itu bukan saja akan menjadi buronan di daerah Kiang-se, tapi juga di seluruh wilayanh Kerajaan Beng yang luas itu.
“Kalau begitu, marilah kita hindari mereka,” kata Wi-hong.
Tetapi derap kaki kuda itu terlalu cepat datangnya, dan dalam sekejap saja sudah tiba didepan kuil kosong itu. Namun yang datang ternyata bukanlah kaum kuku garuda seperti yang diduga oleh Tong Wi-hong dan adiknya, melainkan rahib Hong-koan. Ia melangkah masuk ke dalam kuil dengan membawa dua buah bungkusan kain.
Sambil menarik napas lega, Tong Wi-hong dan adiknya batal untuk bersembunyi. Kata Wi-lian, “Kiranya pek-hu yang datang. Tadinya kami kira kawanan kuku garuda yang hendak menangkap kami.”
Rahib itu berkata, “Pakaian dan bekal uang sekedarnya ini aku ambil dari seorang tuan tanah kejam yang tinggal di dekat Pak-khia. Sedangkan kedua ekor kuda yang cukup bagus itu aku rampas dari serombongan anjing Kaisar yang tengah mengganas terhadap rakyat. Keponakanku berdua, kukira kalian tidak boleh membuang waktu lagi. Berangkatlah sekarang juga, makin cepat dan makin jauh makin baik, sebab di daerah ini Ting Ciau-kun punya pengaruh kuat dan baginya bukan urusan sulit untuk menemukan kalian kembali. Kuanjurkan kalian menuju ke arah selatan saja.”
Tong Wi-hong dan adiknya tercengang mendengar anjuran itu, “Ke selatan?”
Bukankah mereka meninggalkan daerah selatan lari ke utara justru untuk menghindari pengejaran Cia To-bun dan Thio Ban-kiat? Kenapa sekarang mereka harus ke selatan lagi dan seolah-olah kembali masuk ke mulut harimau?
“Ya, ke selatan,” Hong-koan Hwesio menegaskannya dengan wajah bersungguh-sungguh. Katanya lebih lanjut, “Di utara sini, jelas kalian tidak aman karena ada Ting Ciau-kun yang gila pangkat dan pujian, yang tidak akan segan-segan menyerahkan kalian kepada pihak pemerintah. Sedang daerah barat dan timur merupakan daerah-daerah yang ganas dan tempat bersembunyinya banyak tokoh-tokoh golongan hitam. Ke selatanpun cukup berbahaya, tapi bahaya itu tidak sebesar jika berada di tempat lain. Di selatan, nama besar ayah kalian masih punya cukup pengaruh untuk menggerakkan hati sahabat-sahabatnya dalam melindungi kalian.”
Penjelasan Hong-koan Hwesio itu sebenarnya cukup jelas, tapi kedua kakak beradik she Tong itu bahkan terlongong seperti orang kehilangan pegangan. Maklumlah, mereka baru saja terlempar dari sebuah dunia yang dirasa indah dan tenteram, ke sebuah dunia lain yang penuh kekerasan dimana bahaya mengancam dari segala sudut.
Mereka masih belum percaya sepenuhnya bahwa paman Ting yang baik hati itu ternyata hanya seorang munafik seperti yang dikatakan oleh Siau-lim-hong-ceng itu. Tapi semua kenyataan di depan mata memaksa mereka mau tidak mau harus waspada.
Kini mereka akan menuju ke selatan kembali. Tapi kemana? Mereka sudah tidak punya sanak keluarga atau kenalan seorangpun di daerah itu. Haruskah mereka menjadi gelandangan? Sesaat Tong Wi-hong dan adiknya menjadi kebingungan menghadapi perkembangan keadaan yang berkembang terlalu cepat itu.
Meskipun digelari si rahib sinting, sebenarnya Hong-koan Hwesio berhati baik. Jalan pikirannya pun tidak sesinting tingkah lakunya, bahkan tidak jarang ia berpikiran lebih cermat dari orang-orang yang mengaku waras. Ia menjadi iba ketika melihat kakak beradik itu menjadi kebingungan. Tetapi ia sendiripun belum dapat memberikan arah yang pasti, yang dia tahu hanyalah menjauhkan kedua anak yang masih polos itu sejauh-jauhnya dari Ting Ciau-kun, serigala berbulu domba itu.
Sementara itu, di dalam kebingungannya tiba-tiba Tong Wi-hong menemukan akal yang dianggapnya bagus. Katanya, “Pek-hu, bagaimana kalau kami berdua mengikuti pek-hu berkelana saja? Selain untuk belajar ilmu silat pek-hu yang tinggi, juga untuk menambah pengalaman dalam dunia persilatan.”
Dan sebelum Siau-lim-hong-ceng menyahut, Tong Wi-lian telah lebih dulu menyambutnya dengan sorakan gembira. Namun kakak beradik itu menjadi kecewa bukan main setelah melihat Hong-koan Hwesio menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata,
“Tidak bisa jadi, haruslah kalian ketahui bahwa musuh-musuhku sangat banyak, boleh dikatakan bahwa di segenap sudut negeri ini terdapat musuh-musuhku sebab sifatku yang gemar berkelahi. Jika kalian berdua mengikuti aku, maka keselamatan kalian pun ikut terancam, dan aku tidak akan membiarkan kalian ikut menyerempet-nyerempet bahaya bersama aku.”
Sebenarnya Hong-koan Hwesio sangat kasihan melihat kakak beradik yang kecewa itu, namun apa yang telah dikatakannya itu memang sebenarnya. Akhirnya rahib kumal itu menghiburnya, “Aku paham sekali akan hasrat hati kalian yang ingin mencari guru yang pandai dan mempelajari ilmu silat yang tinggi. Karena itu kuanjurkan kalian mencari guru di daerah selatan saja, sebab kebanyakan tokoh-tokoh lihai di daerah utara ini sudah menjadi kaki tangan Kaisar.”
“Dapatkah pek-hu menyebutkan ke mana kami harus menuju dan kepada siapa kami harus berguru?”
Sahut Hong-koan Hwesio, “Banyak sekali tokoh-tokoh di selatan yang pantas menjadi guru kalian. Pertama-tama kalian dapat mencari kakak seperguruanku, Hong-pek atau Hong-tay Hwesio, yang berdiam di kuil Siau-lim-si di Siong-san. Masih ada lagi Ketua kuil Giok-hi-koan di Bu-tong-san, yaitu Kim-hian Tojin, Liu Tay-liong di Kay-hong yang terkenal sebagai ahli menotok jalan darah nomor satu di dunia, atau Tiam-jong-lo-sia (si sesat tua dari tiam-jong-san) di Hun-lam. Tetapi kepada Tiam-jong-lo-sia ini kalian harus agak hati-hati, jangan sampai jika kalian berguru kepadanya lalu ketularan sifat-sifat gilanya.”
Tong Wi-hong dan adiknya mengangguk-anggukkan kepalanya dan mencatat nama-nama itu di dalam hati mereka. Sedangkan Hong-koan Hwesio bukan saja memberikan daftar nama-nama tokoh terkenal, tapi juga menyebutkan beberapa nama yang lebih baik dihindari daripada didekati. Antara lain adalah Lam-gak-su-koay (Empat Siluman dari Gunung Selatan) yang bersimaharajalela di Ou-lam.
Lalu Co-siang-hui-mo (Iblis Terbang di Padang Rumput) si dedengkot penjahat di Su-coan, Thi- jiau-tho-wan (Monyet Bungkuk Berkuku Besi) di Ho-lam dan sebagainya. Tokoh yang disebut terakhir ini, menurut Hong-koan Hwesio, bukan tokoh yang terlalu jahat tetapi juga bukan orang baik-baik. Setelah memberikan pesan-pesan seperlunya, rahib pengembara itupun lalu pergi meninggalkan kedua orang keponakan angkatnya itu.
Sayup-sayup masih terdengar suara nyanyiannya yang sumbang itu makin lama makin jauh sampai akhirnya tidak terdengar lagi. Sikap dan gerak-geriknya melambangkan kebebasan hidupnya, sebebas seekor burung yang terbang di udara. Tapi dibalik sikap bebasnya itu ia masih merasa dibebani sikap bertanggung-jawab untuk mengamankan dunia dari segala perbuatan busuk dan ketidak-adilan.
Tong Wi-hong dan adiknya pun merasa tidak ada lagi yang mereka tunggu di kuil kosong itu. Setelah membenahi diri, merekapun menaiki kuda mereka dan membawa bekal mereka untuk meninggalkan tempat itu menuju ke selatan. Mereka bagaikan dua ekor domba gemuk yang tersesat di padang luas dunia persilatan, dimana kelompok-kelompok serigala bertebaran di mana-mana. Tetapi kedua ekor domba gemuk itu punya tekad kuat dalam hati masing-masing bahwa mereka akan menjadikan diri mereka harimau, sehingga tidak lagi menjadi sekedar mangsa serigala.
“A-lian, kau kelihatannya lesu dan kurang bersemangat dalam melanjutkan perjalanan ini,” Tong Wi-hong menegur adiknya yang berada di sebelahnya. “Apakah kau merasa kurang enak badan?”
Gadis itu tidak menyahut. Hanya mukanya yang tertunduk seakan-akan sedang menghitung langkah-langkah kaki kuda tunggangannya. Sikap itu membuat akaknya jadi menduga-duga, apa gerangan yang telah terjadi atas diri adiknya? Tiba-tiba Tong Wi-hong berkata sambil tertawa lebar,
“Ah, alangkah bodohnya aku. Tapi sekarang aku tahu yang membuat kau tidak bersemangat meninggalkan Pak-khia!”
Kali ini Wi-lian mengangkat wajahnya memandang kakaknya. Dan terdengarlah sang kakak meneruskan ucapannya tadi, “A-lian, mengaku terus teranglah kepadaku, kau berat meninggalkan Ting Bun bukan?”
Seketika merah padamlah wajah si gadis she Tong itu, sebab isi hatinya dapat ditebak tepat oleh kakaknya. Tinjunya yang kecil itu segera terayun hendak memukul pundak kakaknya, namun Wi-hong sempat mengelakkannya sambil tertawa semakin keras.
“Nampaknya tebakanku tidak meleset,” kata Tong Wi-hong sambil mengendorkan lari kudanya.
Akhirnya Tong Wi-lian Cuma bisa menarik napas panjang sambil menundukkan kepalanya. Jauh di dasar hatinya, gadis itu memang sangat mengagumi Ting Bun. Dalam usia yang masih muda, Ting Bun telah menampakkan kepribadian yang begitu kuat mempesona, berwibawa, bertanggung jawab, jujur, dan tidak munafik. Tadinya Wi-lan menganggap perasaannya sendiri itu tidak lebih dari perasaan kagum dan hormat saja.
Tetapi setelah ia dan kakaknya berjarak puluhan li dari Pak-khia, mulai terasa bahwa perasaan yang berkembang di dalam hati mudanya itu bukan sekedar perasaan kagum dan hormat saja, tetapi jauh lebih indah dari pada itu. Tubuhnya meninggalkan Pak-khia, tetapi sebenarnya hati gadis itu telah tertambat di kota itu. Perasaan yang tengah dialaminya adalah perasaan yang paling indah, yang harus dialami oleh semua manusia.
Sedang Tong Wi-hong agaknya masih saja berniat mengganggu adiknya itu, “Aku lupa bahwa kau bukan anak kecil lagi, bahkan tahun ini usiamu sudah delapanbelas tahun lebih. Lagipula Ting Bun itu nampaknya juga... memperhatikan kepadamu....”
Wi-lian menjadi semakin tersipu, dengan gemas ia mengangkat cambuk kuda di tangannya untuk dipukulkan ke punggung kakaknya, tapi dapat dihindari oleh kakaknya. Wi-lian jadi semakin jengkel dan berseru, “A-hong, sudahlah, kenapa kau selalu mengolok aku? Bila ada kesempatan ingin kuhajar babak-belur pantatmu itu!”
Wi-hong tertawa keras, “Aduh galaknya menantu keluarga Ting ini!”
Gadis itu menjadi semakin gemas kepada kakaknya, tetapi sebenarnya jauh di dasar hatinya terselip juga sepercik rasa bahagia yang hangat. Ucapan kakaknya yang menyatakan bahwa sebenarnya Ting Bun juga menaruh perhatian kepadanya itu memang bukan ucapan ngawur, tapi kenyataan. Wi-lian sendiri juga merasakan hal itu. Hanya saja dia adalah seorang gadis, sehingga merasa malu untuk menampakkan perasaannya secara terbuka. Namun alangkah pahitnya bahwa kini ia harus berpisah sebelum sempat saling mengutarakan isi hati.
Merasa telah cukup menggoda adiknya, Wi-hong segera mendekatkan kembali kudanya dan berkata, “Baiklah, aku tidak akan mengolokmu lagi. Aku minta ampun padamu.”
Mau tidak mau Wi-lian tertawa melihat sikap kakaknya itu. Omelnya, “Dasar kau memang jahil, agaknya mulutmu gatal jika tidak menggodaku? Sedangkan di pundak kita masih terbeban beberapa kewajiban berat. Sakit hati ayah belum terbalas, lagipula ibu dan A-siang masih harus kita cari entah kemana. Bagaimana aku berani mendahulukan kepentingan pribadi dan menyampingkan kewajiban keluarga?”
Diingatkan akan kewjiban-kewajiban keluarga yang masih membebaninya, Tong Wi-hong tidak berani bergurau lagi. Demikianlah kakak beradik itu melanjutkan perjalanannya ke arah selatan. Karena mereka tidak pernah melarikan kudanya dengan cepat maka setelah menempuh perjalanan tiga hari, mereka baru mencapai kurang lebih 200 li dari Ibukota Kerajaan. Bahkan di tempat-tempat di mana ada pemandangan yang indah, kakak beradik itu sering berhenti untuk menikmati pemandangan atau untuk melatih ilmu silat mereka.
Hari keempat, mereka memasuki sebuah jalan yang sunyi dan yang terletak di pinggir sebuah hutan yang tidak begitu lebat. Tengah kedua kakak beradik itu berkuda dengan santai sambil bercakap-cakap, tiba-tiba dari arah belakang mereka terdengar derap seekor kuda yang dilarikan dengan kencangnya. Cepat Tong Wi-hong dan adiknya meminggirkan kuda mereka agar tidak tertabrak penunggang kuda itu.
Penunggang kuda itu ternyata adalah seorang lelaki yang bertubuh tegap dan bertampang kasar, di punggungnya tergendong sebatang golok besar. Ketika ia mendahului kedua kakak beradik she Tong itu, ia sengaja melambatkan kudanya dan matanya sempat melirik serta memperhatikan wajah kedua kakak beradik itu dengan seksama. Setelah merasa yakin, ia mempercepat kembali lari kudanya, dan sebentar saja sudah tidak terlihat bayangannya lagi.
Wi-hong dan Wi-lian adalah anak-anak muda yang hijau dalam pengalaman. Tingkah laku si lelaki penunggang kuda itu sama sekali tidak menimbulkan rasa curiga mereka, dianggapnya hal biasa sebab wajah Wi-lian memang cukup cantik untuk menarik perhatian kaum lelaki. Mereka tetap tenang saja dan melanjutkan perjalanan sambil bercakap-cakap.
Tetapi alangkah terkejutnya, ketika kuda mereka tiba-tiba meringkik dan roboh ke tanah, karena kaki binatang-binatang itu terjerat oleh seutas tali yang dipasang melintang di atas tanah. Rupanya tali itu memang sengaja dipasang untuk menjerat kuda yang lewat. Untunglah, biarpun Tong Wi-hong berdua tidak mengira akan kejadian itu, namun sebagai pemuda-pemudi yang terdidik ilmu silat sejak kecil, mereka dapat dengan tangkas melompat dari kudanya tanpa jatuh terbanting.
Namun muka mereka nampak pucat karena terkejutnya. Belum lagi tenang debaran jantung mereka, telah terdengar suara daun-daun tersibak dan rerumputan terinjak, lalu muncullah belasan lelaki bertubuh kekar dan bermuka garang yang langsung bersikap mengurung Tong W-hong dan adiknya. Diantara mereka, nampaklah si penunggang kuda yang tadi hampir menabrak Tong Wi-hong dan adiknya.
Jumlah para penghadang itu ada limabelas orang, semuanya nampak tangkas. Disimpulkan bahwa mereka adalah kawanan manusia yang mencari nafkah dengan senjata. Ada pula yang bertangan kosong, namun agaknya tidak kalah berbahayanya dengan kawan-kawannya yang bersenjata.
Melihat itu diam-diam Tong Wi-hong dan adiknya mengeluh di dalam hati. Ketika mereka dibawa dari rumah Ting Ciau-kun oleh Hong- koan Hwesio, pedang mereka telah tertinggal di rumah paman Ting, dan sampai sekarang mereka belum sempat mendapat gantinya! Menghadapi lima belas orang berandal tangguh itu tanpa pedang adalah pekerjaan yang cukup berat buat orang-orang yang berkepandaian setaraf dengan Wi-hong dan Wi-lian.
Salah seorang dari berandal-berandal itu segera bertanya kepada Tong Wi-hong dengan suaranya yang berat, “He, kau tentu yang bernama Tong Wi-hong? Dan gadis itu tentu yang bernama Wi-lian bukan?”
Wi-hong dan adiknya saling bertukar pandang dengan herannya karena ternyata orang-orang ini dapat mengenali nama-nama mereka. Diam-diam mereka mulai merasakan adanya gelagat kurang baik. Kemudian Wi-hong memberi hormat sambil balas bertanya, “Siapakah tuan-tuan ini? Ada keperluan apa dengan diri kami?”
Lelaki tadi tertawa pendek sambil memegang-megang kumisnya, “He-he, ditanya belum menjawab tapi malah balas bertanya. He, bocah dungu! Jawab dulu pertanyaanku tadi!"
Tong Wi-hong mengerutkan keningnya, dan hatinya mulai menjadi tidak senang melihat sikap orang yang sok jagoan itu. Tapi mengingat kekuatan mereka sendiri yang terbatas, terpaksa ia menyabarkan diri dan menekan kemarahannya. Katanya, “Kami memang benar Tong Wi-hong dan Tong Wi-lian dari An-yang-shia. Ada urusan apakah kalian mencari kami?”
Seorang berandal lainnya yang bersenjata kampak bertangkai panjang, segera mendengus, “Hah, benar-benar bernyali besar, begitu ditanya langsung mengaku. Tidak mengecewakan kalian sebagai putera-puteri Kiang-se-tay-hiap yang tersohor itu. He, anak muda yang berani, ketahuilah, bahwa kami sudah menyetorkan delapanbelas batok kepala ke hadapan si gemuk Cia To-bun, tetapi tidak sebutir batok kepala pun yang cocok sehingga upah yang dia janjikan pun belum kami terima. Tapi berdasarkan pengakuanmu tadi, agaknya kini kami tidak akan salah penggal lagi. Jadi terima kasih atas pengakuanmu.”
Hati Wi-hong dan Wi-lian bergejolak hebat mendengar ucapan berandal itu. ternyata para berandal itu bekerja demi upah yang dijanjikan oleh Cia To-bun untuk memburu dan membunuh sisa-sisa keluarga Tong. Agaknya Cia To-bun benar-benar menjalankan pedoman “membabat rumput seakar-akarnya”.
Sementara berandal berkumis itu telah berkata lagi, “Benar, kali ini orang she Cia itu pasti akan membayar upah kita, seratus tahil perak untuk tiap batok kepala. Setelah itu tinggallah kita mencari di mana isteri Tong Tian dan anak tertuanya yang benama Tong Wi-siang itu, dan setelah itu kita punya cukup banyak uang untuk berfoya-foya.”
Kemarahan telah meluap dalam diri Wi-hong dan adiknya setelah tahu bahwa berandal-berandal itu bekerja untuk Cia To-bun. Bentak Wi-lian, “Bagus! Jadi kalian ini adalah anjing-anjingnya si keparat itu?”
Berandal berkumis itu masih saja tertawa-tawa sambil memegang-megang kumisnya, sahutnya, “Begitulah, berhubung kantong kami sedang kosong, terpaksa akan kami pinjam kepala kalian untuk ditukarkan dengan uang si gendut she Cia itu. kami berjanji jika ada uang akan menyelenggarakan sembahyang sederhana untuk menghormati arwah kalian.”
Kawanan berandal itu serempak tertawa ketika mendengar kelakar kawannya yang berkumis itu. bahkan ada seorang berandal muda yang menimbrung kurang ajar, “Gadis anak Tong Tian ini boleh juga. Sebelum kita jual kepalanya, baiklah kita kerjakan dulu, sebab kurang enak kalau bermesraan dengan gadis tanpa kepala.”
Sekali lagi hutan itu bagaikan tergetar oleh suara tertawa para berandal itu. Sedang Wi-hong dan Wi-lian menjadi merah mukanya karena marahnya. Merekapun sudah menyadari bahwa sulit untuk meloloskan diri dari kepungan ke limabelas orang berandal bersenjata ini, namun mereka lebih suka bertempur mati-matian daripada menodai nama Keluarga Tong.
Mendadak Tong Wi-hong melompat ke arah si berandal muda yang berdiri tiga langkah dari tempatnya. Dengan sebuah pukulan dan tendangan kilat ia membuat si berandal muda itu roboh terkapar sambil memuntahkan darah. Rupanya Wi-hong ingin membuat kawanan berandal yang sedang mabuk kegirangan itu untuk mengurangi jumlahnya, dan ternyata ia berhasil.
Wi-lian cukup cerdas untuk menangkap maksud kakaknya, diapun segera menirunya dengan menyerang berandal terdekat secara mendadak. Tapi gebrakan pertama dari kakaknya tadi telah membuat para berandal bersiaga, sehingga serangan mendadak Wi-lian itu kurang berhasil.
Berandal yang bersenjata kampak bergagang panjang itu agaknya merupakan pimpinan dari kelompok berandal itu. Melihat kakak beradik itu mulai bergerak, ia segera memerintahkan kepada anak buahnya, “Bunuh yang lelaki! Usahakan tangkap hidup-hidup yang perempuan!”
Tetapi putera-puteri Kiang-se-tay-hiap itu justru lebih dahulu menerjang lawan-lawan mereka dengan kemarahan meluap. Dalam waktu sekejap saja terjadilah perkelahian sengit dua lawan empatbelas di tempat yang sunyi itu. Para penjahat itu ternyata bukan manusia-manusia lemah, mereka cukup punya bekal dalam menjalankan kejahatan-kejahatan mereka. Mereka juga sudah menang pengalaman dan mampu bekerja sama dengan rapi dalam menghadapi kakak beradik she Tong yang mengamuk seperti harimau terluka.
Sebentar saja Wi-hong dan Wi-lian mulai merasakan tekanan berat dari lawan-lawan mereka, apalagi mereka berdua cuma bersenjata cambuk kuda, sedang lawan-lawan mereka bersenjata tombak panjang, toya, golok, dan sebagainya. Apalagi si pemimpin berandal yang bersenjata kampak bergagang panjang itu benar-benar tidak dapat dipandang ringan, dialah yang ilmu silatnya paling tangguh.
Dalam keadaan yang semakin gawat buat dirinya dan adiknya itu, sekonyong-konyong Tong Wi-hong ingat ajaran ayahnya bahwa “membekuk ular harus menangkap kepalanya lebih dulu”. Maka diam-diam Tong Wi-hong mulai berusaha bergeser mendekati si pemimpin berandal, dan mempersiapkan tindakan-tindakan kilat untuk menjalankan rencananya.
Suatu ketika Tong Wi-hong merasa sudah tiba waktunya. Dengan disertai bentakan menggeledek ia berhasil merobohkan salah seorang berandal dengan tendangan ke bawah perutnya sehingga si berandal roboh dengan perut mulas. Setelah itu sambil memutar cambuk kudanya secepat angin puyuh, Tong Wi-hong menerjang ke arah pemimpin berandal.
Si pemimpin berandal itupun bukan manusia keroco yang tak berguna, ia membabatkan kampaknya ke kepala Wi-hong. Wi-hong terpaksa menjatuhkan diri dan bergulingan untuk menghindarkan diri dari sambaran maut itu, dengan demikian, gagallah maksud Tong Wi-hong untuk menjalankan tipu “membekuk ular menangkap kepalanya dulu" itu. Bahkan kini si pemimpin berandal yang cukup berpengalaman itu sudah dapat menebak maksudnya.
Baru saja Tong Wi-hong melompat bangun, dua orang berandal yang masing-masing bersenjata golok dan tombak panjang telah menyergap serempak. Dengan sabetan cambuknya ke samping, Tong Wi-hong berhasil melibat dan membelokkan arah bacokan golok lawan. Sedang kaki kirinya melakukukan gerakan kaki Pay-lian-ka (Tendangan Teratai Tertembus Angin) dan berhasil pula menendang tombak lawan sehingga meleset jauh dari sasarannya.
Untuk sementara dia masih bisa membela diri, tetapi Wi-hong sadar bahwa keadaannya yang seperti itu tidak dapat dipertahankan terus. Kekalahan baginya hanya soal waktu. Dia dan adiknya ibarat dua ekor binatang buruan yang sudah masuk dalam perangkap, biarpun sudah meronta bagaimanapun pasti akan mati di ujung senjata lawan-lawan mereka, kecuali datangnya suatu keajaiban.
Keadaan Wi-lian juga tidak kalah payah dari kakaknya. Sebenarnya gadis itu punya niat untuk mencapai kudanya dan naik ke atas punggung kuda. Dia berharap akan lebih mendapat keuntungan jika berkelahi di atas kuda. Dan dia memang pernah berhasil hampir menduduki punggung kuda, tapi seorang lawan berhasil menarik kakinya sehingga terpaksa ia berkelahi di atas tanah kembali.
Satu-satunya keuntungan Tong Wi-lian dibandingkan dengan kakaknya hanyalah bahwa berandal-berandal itu agaknya tidak ingin melukai kulit gadis itu. mereka ingin menjadikan gadis itu sebagai pelampiasan hawa nafsu lebih dulu, sebelum memotong batok kepalanya dan membawanya kepada Cia Tong-bun. Mereka menggunakan tipu hanya mengurung untuk menghabiskan tenaga Wi-lian, dan jika sudah kelelahan barulah akan ditangkap hidup-hidup.
Tiba-tiba si pemimpin berandal yang bersenjata kampak panjang itu berteriak kepada anak buahnya yang tengah mengurung Wi-lian, “He, pusatkan kekuatan kalian untuk menghabisi si bocah lelaki yang bandel itu. Anak gadis yang mulus ini biarlah kutangani sendiri!”
Sebenarnya berandal-berandal itu lebih senang berkelahi melawan Tong Wi-lian yang cantik, tapi mereka pun tidak berani menentang perintah pemimpinnya. Beberapa orang berandal yang mengepung Wi-lian segera berlompatan meninggalkan lawanny dan beralih mengepung Wi- hong yang sedang kepayahan. Meskipun dalam hati kawanan berandal itu memaki pemimpin mereka yang mau enaknya sendiri saja.
Kawanan berandal itu memang hanya menguasai ilmu silat kasaran saja, namun kekuatan tubuh mereka rata-rata justru cukup tangguh, begitu pula kekasaran dan kelicikan mereka. Mereka adalah petualang-petualang yang kenyang dengan pengalaman tempur, dan sanggup berkelahi sehari suntuk tanpa beristirahat. Sebaliknya, meskipun Tong Wi-hong memiliki ilmu silat yang lebih baik, tapi dalam masalah ketahanan tubuh dan pengalaman justru tidak dapat menandingi berandal-berandal itu.
Sementara itu si pemimpin berandal telah melemparkan kampaknya dan menempur W-lian dengan tangan kosong. Gerakannya mantap dan kuat, dan nampaknya dia cukup mahir dalam ilmu gulat Mongol. Tingkat kepandaiannya pun mengungguli Wi-lian. Bukan itu saja, pemimpin berandal itu ternyata cukup kuat kulitnya, sehingga cambuk Wi-lian yang berkali-kali menghantam tubuhnya itu seakan-akan dianggapnya hanya gigitan nyamuk yang tidak berarti.
Malahan beberapa kali gadis itu hampir saja terpegang oleh tangan yang kekar dan berbulu lebat itu. makin lama makin terdesaklah Wi-lian. Dalam keadaan genting itu, sadarlah Wi-lian bahwa dia harus memilih sasaran dalam mencambuk lawan, sebab kulit lawan ternyata cukup tebal dan liat. Maka selanjutnya gadis itu mulai mengarahkan ayunan-ayunan cambuknya ke bagian-bagian lemah seperti mata, tenggorokan, dan bahkan ke bagian terlarang seorang lelaki.
Meskipun hal itu dilakukan dengan muka merah karena malu sendiri, tapi akhirnya gadis itu menekan jauh-jauh semua perasaannya. Demi kehormatan yang dipertahankannya ia tak segan-segan berbuat apa saja. Siasatnya itu ternyata cukup ampuh juga, sebab kini si pemimpin berandal tidak berani lagi mengabaikan cambukan-cambukan gadis itu, dan desakannya pun berkurang tidak segarang tadinya.
Namun kemarahannya justru semakin meningkat, geramnya, “Bagus, gadis binal, sekarang kau boleh melihat kelihaianku!”
Begitu selesai dengan kalimatnya, ia merapat maju dan kedua tangannya secara bergantian menangkap dan mencengkeram secara gencar dengan ilmu gulat Mongol. Didesak semacam itu, cambuk Wi-lian jadi agak kehilangan daya gunanya. Setiap kali Wi-lian mencoba mengatur jarak dengan lawannya, tapi lawannya yang lebih berpengalaman itu malah berhasil mendesaknya bagaikan bayangannya. Meskipun bertubuh besar, ternyata pemimpin berandal itu lebih tangkas dari Wi-lian.
Napas Tong Wi-lian mulai tersengal-sengal. Bukan hanya karena kelelahan, tapi juga karena perasaan ngeri mulai merayapi hatinya, membayangkan penghinaan yang bakal diterimanya jika ia jatuh ke tangan para berandal itu. Tiba-tiba matanya mulai berkunang-kunang dan tenaganyapun semakin lemah. Di saat itulah kedua belah tangan si pemimpin berandal itu bergerak serempak, dan kali ini tidak memberi kesempatan kepada korbannya untuk menghindar lagi.
Dengan mudah Tong Wi-lian segera dapat diringkusnya dan langsung diseret masuk ke dalam hutan. Bahkan tidak diperdulikannya anak buahnya yang masih bekerja keras untuk menundukkan Wi-hong. Malahan si pemimpin berandal itu sempat berteriak sambil tertawa,
“Kalian bereskan dulu bocah lelaki itu. nanti kalian pun akan kebagian!”
Karena Tong Wi-lian masih juga meronta mencoba melepaskan diri, maka dengan jengkel si pemimpin berandal lalu memanggul tubuh gadis itu secara paksa dan dibawa menghilang ke dalam hutan. Tong Wi-hong melihat semua kejadian itu tapi tidak dapat berbuat apa-apa, darahnya mendidih hebat. Ia berteriak-teriak kalap dan mengamuk hendak menjebol kepungan untuk merebut kembali adiknya, tapi kepungan para berandal itu sangat ketat.
Biarpun ada beberapa berandal yang roboh, tapi hanya dengan sehelai cambuk kuda ditangannya, mustahillah bagi Tong Wi-hong untuk bisa lolos dari kawanan berandal yang bersenjata itu. Karena ia semakin gugup, maka tubuh Wi-hong kembali terkena senjata lawan dan menimbulkan beberapa luka baru.
Akhirnya pemuda yang biasanya lemah lembut itu menjadi nekad dan menjadi sangat kasar, teriaknya dengan amarah meluap, “Kawanan bajingan tengik! Hari ini biarpun aku mati di tangan kalian, tapi beberapa orang diantara kalin pun harus ikut mampus menemani aku!”
Oleh semangatnya itu maka kekuatannya yang hampir habis itu seolah bertambah kembali. Dengan menggeram seperti macan luka dan menyerang membabi-buta, kembali dua orang berandal berhasil ditendangnya roboh. Tapi ia tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa akhirnya tenaganya pun mulai susut dengan cepat, dan melulu semangat yang berkobar saja tidak banyak menolongnya. Langkahnya mulai terhuyung-huyung dan sabetan cambuknya tidak terarah lagi.
Kawanan berandal itu menjadi kegirangan, mereka berteriak-teriak, “Kepung terus tikus ini! Tenaganya sudah hampir habis dan setelah itu barulah kita sembelih!”
Seorang berandal yang bersenjata ce-bi-kun secara telak berhasil menghantam punggung Tong Wi-hong, sehingga anak muda yang gagah perkasa itu kini tersungkur jatuh ke depan sambil menyemburkan darah segar dari mulutnya. Ia mendapat luka dalam yang tidak ringan.
Tapi putera Kiang-se-tay-hiap itu telah digembleng dengan watak kesatria sekaj kecil, ia pantang menyerah sebelum ajal tiba. Dengan bergulingan kesana kemari dia masih dapat menghindari senjata-senjata lawan-lawannya yang bertubi-tubi menghujani tubuhnya. Bahkan suatu kesempatan ia berhasil melompat berdiri meskipun dengan tubuh lemas dan mata berkunang-kunang.
Sambil mengayun-ayunkan cambuk kudanya, ia berteriak parau, “Kawanan anjing gila, hayo maju ke sini dan mengadu jiwa dengan aku kalau berani!”
Seorang berandal yang bersenjata pedang segera menyambut seruan itu dengan menyeringai dingin dan mengejek, “Tikus kecil ini sudah dekat ajal tetapi masih berani membuka mulut besar. Biar pedangku mencicipi darahnya!”
Begitu mulutnya tertutup begitu pula pedangnya berkelebat ke arah leher Tong Wi-hong dengan derasnya. Wi-hong sudah berusaha mati-matian mengelakkan pedang itu, tapi seluruh tubuhnya sudah begitu lemah dan tidak dapat digerakkan sedikitpun juga. Akhirnya ia cuma bisa menggertak gigi dan pasrah nasib, sementara matanya terpejam menunggu batang lehernya terpenggal. Bahkan sebelum mata pedang menyentuh lehernya, Wi-hong sudah tak sadarkan diri, bukan karena ketakutan tapi karena benar-benar telah kehabisan tenaga.
Dalam pada itu, Tong Wi-lian yang dibawa oleh si pemimpin berandal ke dalam hutan itu masih saja berusaha keras untuk melepaskan diri. Gadis itu terus meronta-ronta, menendang dan memukul, bahkan tidak segan-segan untuk menggigit pula. Tetapi sepasang tangan yang menawannya itu tetap kokoh kuat bagaikan terbuat dari besi. Si pemimpin berandal bahkan tertawa-tawa kegirangan karena merasakan gesekan-gesekan tubuh dengan gadis rampasannya ketika gadis itu meronta-ronta, sementara langkahnya tidak pernah berhenti.
“Sabarlah, sebentar lagi kita akan di tempat yang aman dan kita akan bersama-sama menikmati sorga dunia,” ejeknya sambil tertawa terkekeh-kekeh.
Semakin ngerilah gadis itu mendengar ucapan pemimpin berandal itu. di pelupuk matanya sudah terbayang suatu penghinaan yang sangat keji, lebih keji dari kematian buat seorang perempuan terhormat. Diam-diam timbul tekad Wi-lian untuk menggigit putus lidahnya sendiri agar mati saja daripada mengalami aib seumur hidupnya. Namun di saat nasib buruk sudah hampir pasti dialami oleh gadis itu, dan si pemimpin berandal pun sudah hampir pasti pula akan mengalami “kemenangan”nya, datanglah seorang dewa penolong.
Saat itu si pemimpin berandal sudah tiba di tengah hutan, di suatu tempat yang dianggapnya cukup nyaman untuk melampiaskan nafsunya sebelum memenggal kepala gadis itu dan kemudian ditukarnya dengan uang seratus tahil perak, sekonyong-konyong di tempat itu berkumandanglah suara pujian merdu kepada Sang Buddha,
“Omitohud!” Suara itu tidak terlalu keras, namun jelas mengandung suatu kekuatan yang menggetarkan hati siapapun. Ketenangannya seperti ketenangan sebuah telaga yang dalam, kewibawaannya seberat gunung Tay-san.
Si pemimpin berandal yang sudah siap melucuti pakaian korbannya itu jadi terkejut bukan main dan menyapukan pandang matanya ke sekeliling tempat itu. Tiba-tiba dilihatnya sesosok bayangan putih berkelebat dengan kecepatan yang mengaburkan mata. Lalu di tempat itu muncullah seorang rahib tua berjubah putih, berwajah ramah penuh kedamaian dengan sinar mata yang lembut. Jubah dan jenggotnya yang juga berwarna putiih melambai-lambai, menambah perbawanya sehingga mirip seorang dewa dalam dongeng kuno.
Pemimpin berandal yang merasa keinginannya terganggu itu menjadi murka bukan main. Bentaknya kasar, “Bangsat gundul! Rupanya kau sudah bosan hidup sehingga berani mengganggu kesenanganku? Sebutkan namamu!”
Si rahib itu ternyata tenang-tenang saja menghadapi sikap kasar si pemimpin berandal, dengan suara tetap lembut ia memperkenalkan dirinya, “Aku adalah Hong-tay Hwesio dari Siong-san.”
Buat kaum persilatan yang berpengetahuan luas dan sering bergaul antara sesama kaum persilatan, nama itu tentu akan mengejutkan, sebab Hong-tay Hwesio adalah tokoh sakti dari kuil Siau-lim-si yang menduduki urutan kedua dalam deretan nama “Sepuluh Tokoh Maha Sakti di Jaman Itu”.
Tapi si pemimpin berandal itu ibarat katak di dalam sumur, pengetahuannya tentang dunia persilatan sangat terbatas sehingga nama Hong-tay Hwesio justru tidak menimbulkan kesan apapun. Sikapnya tetap kasar dan takabur, geramnya, “He, keledai gundul Hong-tay, tempatmu bukan di sini tapi di kelenteng, bersembahyang serta membaca kitab suci, buat apa kau berkeliaran di tempat ini dan mengganggu kesenangan orang lain?”
Rahib itu menyahut dengan tetap ramah, “Jika saat ini aku berada di kelenteng, lalu siapa yang mencegah perbuatan jahatmu? Apa artinya aku dapat memahami seluruh kitab suci tetapi seorang sesamaku aku biarkan saja mengalami penghinaan dan dihancurkan seluruh masa depannya?”
“Kurang ajar! Jadi dengan hadirnya kau sekarang ini kau pikir kau mampu menyelamatkan gadis ini dari tanganku?” teriak pemimpin berandal itu dengan amarah meluap. Lalu dengan sekuat tenaga ia ayunkan kakinya untuk menendang ulu hati si rahib tua itu.
Dengan tenang si rahib tua mengangkat tangannya ke depan seperti orang memberi hormat sambil menggumamkan pujian, “Omitohud.”
Dan si pemimpin berandal tiba-tiba merasakan bahwa ada segulung tenaga tidak terlihat yang mendampar ke arahnya dengan kuatnya. Bukan saja tendangannya meleset dari sasaran, bahkan tubuhnya pun terdorong beberapa langkah ke belakang dan jatuh terkapar.
Baru kini tertampil perasaan kaget pada wajah si pemimpin berandal. Diam-diam dia mulai merasa keder melihat rahib tua itu demikian lihai. Tetapi dia masih belum jera, kini ia menghunus sebatang pisau belati yang disembunyikan di bajunya dan bangkit kembali. Bentaknya, “Kau memang hebat keledai gundul, tetapi kini jangan salahkan aku kalau kukirim nyawa bangkotanmu itu ke neraka!”
Pemimpin berandal itu memang cukup tangkas, gerakannya cepat seperti seekor harimau menerjang mangsanya, dan pisau belati ditangannya itu bagaikan kuku-kuku harimau yang siap merobek-robek tubuh lawan.
Namun rahib tua itu tetap berdiri di tempatnya dengan tenang dan santai, wajahnya tetap penuh welas asih. Meskipun pemimpin berandal itu telah melakukan serangan serangan yang berusaha menghabisi nyawanya tapi si rahib itu tidak kelihatan marah atau dendam. Seenaknya saja ia mengebaskan lengan jubahnya dan dengan tepat berhasil membelit pisau lawan, lalu dengan kebasan ringan ia berhasil membuat lawannya jungkir-balik.
Pemimpin berandal yang begitu garang itu ternyata tidak lebih hebat dari seorang anak kecil umur tiga tahun jika dihadapkan dengan tokoh nomor dua di Tiong-goan itu. Kini habislah nyali si pemimpin berandal itu. Jatuhnya kali ini cukup keras dan pinggangnya menimpa sepotong akar yang menonjol dari tanah. Ia tidak dapat segera bangkit kembali karena sakitnya. Dengan tertatih-tatih akhirnya ia dapat berpegangan kepada pepohonan di sekitarnya dan berdiri perlahan-lahan.
Di dalam hatinya ia merasa malu, marah, dan penasaran. Tetapi dia insyaf bahwa berlatih sepuluh tahun lagi pun belum tentu dapat menandingi rahib itu. Akhirnya ia menerima kenyataan itu dan dengan terbungkuk-bungkuk sambil memegangi pinggangnya yang sakit ia melangkah pergi dari tempat itu.
Sebelum ia melangkah terlalu jauh, masih terdengar suara rahib Hong-tay yang bernada menasehati sekaligus mengancam, “Aku berharap agar anda bersedia memikirkan kembali ke jalan yang benar. Jika anda masih saja melakukan kejahatan dan mengganggu ketenteraman sesama manusia, maka apa boleh buat, terpaksa anda akan merepotkan murid-murid Siau-lim-pay kami yang tersebar di mana-mana.”
Pemimpin penjahat itu nampak agak pucat mukanya ketika mendengar perkataan Rahib Hong-tay itu. Meskipun mulutnya tidak menyahut, tapi ia mengerti bahwa ancaman itu bukan main-main. Dengan terpincang-pincang ia meneruskan langkahnya dan sesaat kemudian ia sudah tidak terlihat lagi di tempat itu.
Tong Wi-lian menarik napas lega setelah melihat perginya pemimpin berandal itu, tidak lupa ia mengucapkan terima kasih kepada rahib tua yang telah menyelamatkannya dari aib hebat itu. Rahib tua itu menjawab ucapan terima kasihnya dengan suaranya yang berwibawa tapi lembut,
“Sudahlah, nona, berterima kasihlah kepadabThian yang selalu melindungi orang baik.”
Sementara itu, mendadak Tong Wi-lian teringat kepada kakaknya yang saat itu tentu masih menyabung nyawa di luar hutan sana. Katanya kepada rahib Hong-tay, “Tay-su (bapak pendeta), aku telah menerima pertolonganmu yang maha besar, tetapi dapatkah aku minta tolong sekali lagi kepada Tay-su?”
“Katakan saja. Jika aku mempunyai kemampuan untuk melakukannya tentu aku tidak akan menolaknya,” sahut rahib itu.
Dengan singkat segera Tong Wi-lian mengatakan tentang kakaknya yang masih terancam jiwanya oleh sekawanan berandal di luar hutan itu. Mendengar hal itu, Rahib Hong-tay langsung berkata, “Kalau begitu kita tidak boleh terlambat menolongnya. Nona, marilah tunjukkan di mana kakakmu sedang terancam bahaya!”
Lalu rahib itu mengulurkan tangannya dan berkata, “Kita harus cepat, karena itu peganglah tanganku supaya aku dapat menggunakan ilmu meringankan tubuhku.”
Tong Wi-lian tahu bahwa rahib itu berhati suci bersih dan bukan seorang munafik, lagi pula usianya cukup pantas untuk menjadi kakeknya, maka tanpa malu-malu lagi ia memegang tangan rahib itu. begitu kedua telapak tangan saling genggam, tiba-tiba Wi-lian merasa kakinya terangkat dari tanah dan tubuhnya melayang ke depan secepat kilat. Ternyata rahib itu telah menariknya dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh supaya cepat sampai di tujuan.
Gadis itu merasa betapa pepohonan di kiri kanannya seolah-olah terhanyut ke belakang dengan cepatnya. Dan ketika ia melirik ke arah sepasang kaki rahib tua itu, semakin hebatlah kekaguman gadis itu. Ternyata sepasang kaki Hong-tay Hwesio bagaikan tidak menginjak tanah karena gerakannya yang terlalu cepat. Bahkan berlari di tengah hutan yang tidak rata dan penuh pepohonan itu ternyata si rahib dapat membawa Wi-lian dengan leluasa seperti melalui tanah lapang saja.
Ginkang (Ilmu Meringankan Tubuh) sehebat itu ternyata Wi-lian belum pernah menyaksikannya. Bahkan Wi-lian menaksir bahwa kepandaian Hong-tay Hwesio ini beberapa tingkat di atas Siau-lim-hong-ceng ataupun Soat-san-kiam-sian yang juga tergolong tokoh-tokoh sakti jaman itu. Sambil membiarkan tubuhnya diseret oleh rahib itu, diam-diam Tong Wi-lian berpikir,
“Pantas sekali orang-orang dunia persilatan di Tiong-goan menjuluki kuil Siau-lim-si di Siong-san sebagai persembunyiannya naga dan harimau. Cukup Hong-tay Hwesio dan Hong-koan Hwesio saja sudah merupakan dua buah tiang yang maha kokoh untuk menunjang keangkeran Siau-lim-pay. Apalagi di dalam kuil itu tentu masih ada tokoh sakti lainnya yang seangkatan dengan mereka. Belum terhitung puluhan tokoh-tokoh angkatan muda mereka yang tentu merupakan pendekar-pendekar tangguh pula.”
Lalu gadis itu mencoba membuat perbandingan antara Siau-lim-pay dan Soat-san-pay. Maka secara jujur ia harus mengakui bahwa pengaruh Soat-san-pay masih tidak sehebat Siau-lim-pay meskipun Soat-san-pay juga merupakan perguruan besar di daerah barat. Ini disebabkan oleh karena Siau-lim-pay merupakan aliran silat yang ratusan tahun lebih tua dibandingkan Soat-san-pay.
Selain itu, tokoh-tokoh Soat-san-pay kebanyakan berdiam jauh di wilayah barat dan jarang menampakkan diri di dunia persilatan Tiong-goan sehingga nama mereka kurang dikenal orang. Ini berbeda dengan tokoh-tokoh Siau-lim-pay yang banyak berkecimpung dalam dunia persilatan dalam menegakkan kebenaran.
Dalam pada itu, tak terasa tibalah mereka di pinggir hutan di tempat terjadinya pertempuran tadi. Tetapi pertempuran telah selesai dan tempat itu telah menjadi sunyi kembali seperti semula. Yag ada hanyalah mayat para berandal yang bergelimpangan di sana-sini, sedang mayat Tong Wi-hong ternyata tidak ada diantara mayat-mayat itu!
Hal itu membuat hati Wi-lian sedikit lega, tapi timbul kegelisahan baru kalau memikirkan entah bagaimana nasib kakaknya. Ketika Wi-lian mencoba menghitung jumlah mayat-mayat itu, semuanya berjumlah empatbelas. Jadi gerombolan yang menghadangnya itu telah tertumpas habis kecuali si pemimpin berandal yang diampuni oleh Hong-tay Hwesio tadi.
Sedangkan Rahib Hong-tay justru menampakkan wajah sedih melihat mayat bergelimpangan sebanyak itu. Ia menarik nafas beberapa kali dan bergumam dengan suara rendah, “Rupanya di sinilah kakakmu tadi bertempur. Meskipun aku datang terlambat tapi agaknya kakakmu yang gagah perkasa itu telah menolong dirinya sendiri dengan menumpas semua musuh-musuhnya tanpa ampun. Omitohud! Benar-benar ganas.”
Dalam suara rahib tua itu terkandung nada penyesalan dan kesedihan, rupanya paderi itu bersedih kenapa manusia masih saja demikian buas dan saling bunuh tanpa kenal ampun? Bahkan ada nada menyalahkan Tong wi-lian yang memiliki kakak sekejam itu.
Cepat Tong Wi-lian menggelengkan kepala sambil membantah “Pasti bukan kakakku yang membunuh mereka. Aku berani bersumpah disambar petir pasti ini bukan perbuatan kakakku. Kepandaian kakakku tidak sehebat ini, ia hanya unggul sedikit dari padaku, dan dengan dasar kepandaiannya itu mustahil ia mampu membunuh empatbelas orang pembunuh bayaran yang rata-rata berkepandaian cukup tangguh itu. Bahkan ketika akau dibawa oleh pemimpin berandal tadi masuk ke dalam hutan, kakakku sudah dalam keadaan terluka dan kelelahan, hampir tidak bisa melawan sama sekali, sedang musuh-musuhnya masih dalam keadan utuh. Kakakku tidak mampu membunuh seorang lawanpun sebab ia cuma bersenjata sehelai cambuk kuda.”
Kemudian rahib Hong-tay berjongkok untuk memeriksa mayat-mayat itu, alisnya yang putih seperti kapas nampak berkerut-kerut. Dia kemudian bergumam, “Aku mempercayai ucapan nona. Memang bukan kakakmu yang membunuh berandal-berandal ini. Agaknya aku dapat menebak siapa orang itu. Rupanya setelah membunuh orang-orang ini, ia lalu membawa pergi kakakmu.”
Tong Wi-lian menjadi sangat lega karena ucapannya dipercaya oleh rahib sakti itu. Tak terasa ia berdiri di belakang rahib itu dan ikut memeriksa mayat-mayat itu. Semetara Rahib Hong-tay berkata lagi,
“Memang ada beberapa luka-luka kena cambukan, tetapi luka-luka itu hanya luka-luka kulit dan sama sekali tidak mematikan. Yang mematikan adalah luka yang membelah dada mereka. Luka itu bukan disebabkan oleh pedang atau golok, melainkan oleh jenis senjata yang lebih ganas lagi yang disebut Hau-thau-kau (Kaitan Kepala Harimau). Pedang dan golok hanya membelah kulit dan daging, tapi Hau-thau-kau orang itu dapat merobek-robek sampai ke bagian dalam tubuh lawan. Itulah yang mematikan berandal-berandal ini.”
Terdorong oleh rasa keingintahuannya, Tong Wi-lian lalu bertanya kepada rahib tua itu, “Tadi Tay-su mengatakan bahwa Tay-su mengetahui siapa orangnya yang membunuh penjahat-penjahat ini. Dapatkah Tay-su memberi tahukan kepadaku supaya aku dapat mencarinya dan menanyakan perihal kakakku kepadanya?”
Teringat kepada orang yang bersenjata Hau-thau-kau itu, berkerutlah alis Hong-tay Hwesio menandakan ketidak-senangan hatinya. Orang itu sebenarnya adalah tergolong tokoh golongan lurus, bahkan dia adalah pemimpin dari sebuah piau-hang (Perusahaan Pengawalan) yang cukup terkenal.
Namun yang menimbulkan ketidak-senangan Hong-tay Hwesio adalah sikapnya yang terlalu keras dalam menghadapi golongan hitam. Orang itu tidak pernah mengampuni penjahat-penjahat yang menjadi lawannya, meskipun lawannya sudah tunduk dan menyatakan bertobat. Ia bersemboyan “sekali penjahat tetap penjahat”, biar diampuni juga kelak akan berbuat jahat lagi.
Maka kaum penjahat yang kepergok orang ini hanya ada dua jalan, yaitu membunuh atau terbunuh. Karena rahib Hong-tay berwatak welas asih dan pengampun, maka ia merasa tidak cocok dengan sifat-sifat ganas orang ini, dan karena itu pulalah ia segan menyebutkan namanya di hadapan Tong Wi-lian.
Sedangkan Wi-lian terus mendesaknya, “Luka-luka di tubuh berandal-berandal ini cukup dalam namun lurus dan panjang. Jelas pembunuhnya adalah orang yang mampu mengerakkan Hau-thau-kaunya dengan kekuatan besar dan kecepatan yang tinggi. Orang berkepandaian yang setaraf ini tentu tidak banyak di dunia persilatan, tentu tay-su mengenalnya pula.”
Keengganan Rahib Hong-tay menyebutkan orang itu adalah karena mengkhawatirkan Wi-lian yang masih lugu itu akan menemui orang itu, berguru kepada orang itu dan kemudian ketularan sifat-sifat keras dari orang itu. hal itu tidak dikehendaki oleh rahib yang welas asih itu. Karena itu terpaksa ia agak berbohong dalam menjawab desakan Wi-lian,
“Omitohud, setiap kali aku teringat kepada orang itu, yang terbayang di benakku hanyalah muncratnya darah dan jerit kematian. Aku memang mengenal orang itu dan pernah bertemu dengannya, tetapi aku tidak tahu siapa nama aslinya dan dimana tempat tinggalnya. Jadi maaf, aku tidak bisa memberi keterangan yang jelas kepada nona.”
Sambil mengucapkan kata-kata itu, diam-diam Hong-tay Hwesio memohon ampun kepada Sang Buddha sebab telah melanggar pantangan berbohong. Tetapi rahib Hong-tay berpendapat bahwa “kebohongan yang menyelamatkan adalah lebih baik daripada kejujuran yang menjerumuskan”.
Tong Wi-lian menjadi sangat kecewa karena tidak berhasil mendapatkan keterangan yang diinginkan. Namun hatinya tidak begitu cemas lagi memikirkan kakaknya, sebab agaknya kakaknya telah diselamatkan oleh seseorang yang berkepandaian tinggi. Bahkan ada kemungkinan besar sang kakak akan berguru kepada orang itu.
Begitu pikirannya melayang ke persoalan “berguru”, tiba-tiba terbukalah pikiran gadis itu. Kini di hadapannya tengah hadir seorang rahib yang kesaktiannya seperti dewa, bahkan terhitung kakak seperguruan dari uwak angkatnya Hong-koan Hwesio, kenapa kesempatan ini tidak dimanfaatkan untuk memohon menjadi muridnya?
Karena itu alangkah kagetnya Rahib Hong-tay ketika tiba-tiba gadis she Tong itu tiba-tiba berlutut menyembah kepadanya dan berkata dengan nada menghibakan hati,
“Tay-su, kini setelah berpisah dengan kakakku maka aku benar-benar sendirian di dunia ini. Ayahku telah tiada, sedang ibuku dan kedua orang kakakku tidak kuketahui di mana beradanya. Aku seorang gadis lemah, maka mohon belas kasihan tay-su untuk menerima aku sebagai murid dan mengajarkan ilmu silat kepadaku...”
Tidak mengherankan pula kalau tongkat bambu butut milik Hong-koan Hwesio itupun mengandung kekuatan-kekuatan demikian. Jika digabungkan dengan ilmu silatnya yang tinggi, maka jadilah Hong-koan Hwesio Harimau Yang Tumbuh Sayapnya.
Kini Tong Wi-hong dan adiknya tidak ragu-ragu lagi. Cepat mereka berlutut di depan rahib itu sambil memanggil “pek-hu” (uwa).
“Nah, sekarang kalian percaya bukan?” kata Hong-koan Hwesio.
Tiba-tiba rahib itu mengibaskan lengan jubahnya yang kedodoran itu ke arah Wi-hong berdua yang berjarak berapa langkah dari padanya. Ternyata kebasan yang nampak sederhana itu telah menunjukkan ketinggian ilmu rahib kumal itu, sebab dalam satu gerakan sekaligus mengandung dua macam tenaga yang berbeda. Wi-hong dan Wi-lan terdorong oleh angin kebasan itu sehingga jatuh bergulingan di lantai yang berdebu, sebaliknya tongkat bambu yang mereka pegang itu justru “tersedot” dan melayang ke arah pemiliknya.
Rahib itu tertawa terbahak-bahak melihat kakak beradik itu menjadi tidak keruan macamnya karena tubuh dan muka mereka penuh debu. Biarpun dalam keadaan serba runyam, Wi-hong dan adiknya tidak marah namun justru ikut-ikutan tertawa. Julukan “rahib gila” yang diberikan oleh orang-orang dunia persilatan kepada Hong-koan Hwesio memang bukan nama kosong belaka dan cocok dengan sifat-sifatnya.
Sementara itu Hong-koan Hwesio telah melemparkan dua potong daging menjangan panggang itu kepada kakak beradik itu, sambil berkata, “Isilah perut kalian, jangan sampai masuk angin dan menjadi sakit.”
Sekarang Wi-hong dan Wi-lian mengerti bahwa rahib kumal ini tidak menyukai segala macam hal yang bertele-tele, termasuk segala macam basa-basi. Maka tanpa disuruh untuk kedua kalinya, kakak beradik itu segera menyambar daging yang dilemparkan itu dan langsung melahapnya, meskipun daging itu agaknya hangus sedikit.
Sedangkan Hong-koan Hwesio lalu bangkit sambil mengebas-ngebaskan jubahnya. “Aku merasa lega sekali bahwa kalian mempercayai aku. Kini kalian tunggu dulu di tempat ini. Aku akan pergi sebentar untuk mencarikan bekal serta dua ekor kuda untuk kalian, sebab kalian harus segera meninggalkan tempat ini. Semakin jauh meninggalkan paman Ting kalian itu, semakin baik buat kalian,” katanya.
Sahut Wi-hong, “Mana berani kami membikin repot pek-hu? Meskipun kami harus meninggalkan Pak-khia tetapi tidak perlu pek-hu yang bersusah payah mencarikan keperluan kami.”
Rahib kumal itu tertawa, “Maksudmu kalian akan mencari sendiri kuda dan bekal itu? Hemm, dengan kepandaianmu yang serendah itu mungkin kau akan tertangkap oleh kuku garuda atau oleh begundal-begundalnya paman Ting mu. Dengan demikian kalian justru akan semakin merepotkan aku untuk membebaskan kalian kembali.”
Keruan muka Tong Wi-hong menjadi merah mendengar sentilan tajam itu. Tapi ia tidak marah, karena hal itu memang kenyataan. Di kota kecil An-yang-shia, ia memang termasuk anak muda yang menonjol dalam hal ilmu silat. Tapi setelah melihat di dunia yang lebih luas, ternyata bahwa kepandaiannya itu belum berarti apa-apa dibandingkan dengan tokoh-tokoh dunia persilatan saat itu.
Dengan beberapa kali lompatan saja, Hong-koan Hwesio sudah pergi jauh. Meskipun tubuhnya tinggi besar, namun kelincahannya ternyata cukup mengagumkan. Bahkan Wi-hong dan adiknya menaksir bahwa kepandaian rahib kumal itu tentu tidak di sebelah bawah dari su-siok-co mereka, yaitu Soat-san-kiam-sian Oh Yu-thian.
Sementara rahib itu pergi, kakak beradik itu mulai merenungkan apa yang telah diucapkan oleh Hong-koan Hwesio mengenai diri Ting Ciau-kun. Benarkah Ting Ciau-kun berjiwa sebejat itu? Diam-diam timbul perasaan masygul yang sangat dalam di hati kakak beradik itu. Jika itu benar, maka rasanya dunia ini tidak sehangat yang mereka duga. Di balik muka yang manis belum tentu terdapat hati yang manis pula, bahkan mungkin terdapat ancaman yang keji.
Meskipun hati sedang gundah, tak urung gumpalan besar daging kijang itu lenyap juga ke dalam mulut mereka. Maklumlah, mereka belum sempat mengisi perut sejak kemarin sore, dan hari itu sudah cukup siang.
Tidak lama kemudian, dari kejauhan terdengar derap kaki kuda menuju ke arah kuil rusak tempat mereka berada itu. Didengarkan dari suara derapnya yang cepat dan mantap, nampaknya kuda yang sedang mendatangi itu merupakan kuda-kuda pilihan. Tong Wi-hong tetap santai saja mendengar suara itu, sebaliknya adiknya yang bersifat lebih cermat dari kakaknya segera menjadi tegang mukanya. Katanya,
“A-hong, kau dengar derap kaki kuda itu?”
“Aku dengar, memangnya ada apa?”
“Kau benar-benar ceroboh dan malas menggunakan otak,” demikian Wi-lian menggerutui kakaknya. “Coba kau dengar lebih cermat lagi. Derapnya cepat dan mantap, jelas merupakan kuda-kuda padang rumput yang terpilih. Orang yang menunggang kuda macam itu biasanya adalah kaum kuku garuda, lagipula tempat inipun belum jauh dari Pak-khia. Kau harus ingat, bahwa kita adalah resmi sebagai buronan pemerintah kerajaan.”
Mendengar itu Tong Wi-hong lalu melompat bangkit dengan beringas. Serunya, “Kebetulan sekali kalau yang datang ini adalah anjing-anjing Kaisar, biarlah kita hajar mereka untuk melampiaskan sakit hati keluarga kita. A-lian, bersiap!”
Namun adiknya kelihatannya tidak begitu bersemangat untuk berkelahi saat itu. Serunya, “Kakakku, kau harus ingat bahwa pada umumnya para perwira kerajaan itu berilmu cukup tinggi. Mampukah kita yang hanya berdua ini menghadapi mereka? Masih ingatkah kau akan kejadian di rumah kita pada waktu diserbu orang-orangnya Thio Ban-kiat? Waktu itu, bahkan dengan bantuan seorang tokoh selihai Su-siok-co Oh Yu-thian saja kita masih kewalahan menghadapi kerubutan mereka. Itu baru perwira-perwira daerah Kiang-se, dan perwira-perwira di ibukota kerajaan ini tentu memiliki kemampuan yang lebih baik daripada perwira-perwira daerah. Nah, apakah kita akan nekat berkelahi sehingga mampus dan tidak dapat lagi membalaskan sakit hati keluarga kita?”
Tong Wi-hong tidak menyahut, tapi uraian adiknya itu cukup masuk akal. Agaknya setelah peristiwa pemukulan Cia bok di An-yang-shia itu Tong Wi-lian berubah menjadi lebih sabar dan lebih cermat. Memang bukan mustahil bahwa Thio Ban-kiat atau Cia To-bun telah melaporkan tentang “pemberontakan” keluarga Tong itu ke pemerintah pusat, sehingga orang-orang keluarga Tong itu bukan saja akan menjadi buronan di daerah Kiang-se, tapi juga di seluruh wilayanh Kerajaan Beng yang luas itu.
“Kalau begitu, marilah kita hindari mereka,” kata Wi-hong.
Tetapi derap kaki kuda itu terlalu cepat datangnya, dan dalam sekejap saja sudah tiba didepan kuil kosong itu. Namun yang datang ternyata bukanlah kaum kuku garuda seperti yang diduga oleh Tong Wi-hong dan adiknya, melainkan rahib Hong-koan. Ia melangkah masuk ke dalam kuil dengan membawa dua buah bungkusan kain.
Sambil menarik napas lega, Tong Wi-hong dan adiknya batal untuk bersembunyi. Kata Wi-lian, “Kiranya pek-hu yang datang. Tadinya kami kira kawanan kuku garuda yang hendak menangkap kami.”
Rahib itu berkata, “Pakaian dan bekal uang sekedarnya ini aku ambil dari seorang tuan tanah kejam yang tinggal di dekat Pak-khia. Sedangkan kedua ekor kuda yang cukup bagus itu aku rampas dari serombongan anjing Kaisar yang tengah mengganas terhadap rakyat. Keponakanku berdua, kukira kalian tidak boleh membuang waktu lagi. Berangkatlah sekarang juga, makin cepat dan makin jauh makin baik, sebab di daerah ini Ting Ciau-kun punya pengaruh kuat dan baginya bukan urusan sulit untuk menemukan kalian kembali. Kuanjurkan kalian menuju ke arah selatan saja.”
Tong Wi-hong dan adiknya tercengang mendengar anjuran itu, “Ke selatan?”
Bukankah mereka meninggalkan daerah selatan lari ke utara justru untuk menghindari pengejaran Cia To-bun dan Thio Ban-kiat? Kenapa sekarang mereka harus ke selatan lagi dan seolah-olah kembali masuk ke mulut harimau?
“Ya, ke selatan,” Hong-koan Hwesio menegaskannya dengan wajah bersungguh-sungguh. Katanya lebih lanjut, “Di utara sini, jelas kalian tidak aman karena ada Ting Ciau-kun yang gila pangkat dan pujian, yang tidak akan segan-segan menyerahkan kalian kepada pihak pemerintah. Sedang daerah barat dan timur merupakan daerah-daerah yang ganas dan tempat bersembunyinya banyak tokoh-tokoh golongan hitam. Ke selatanpun cukup berbahaya, tapi bahaya itu tidak sebesar jika berada di tempat lain. Di selatan, nama besar ayah kalian masih punya cukup pengaruh untuk menggerakkan hati sahabat-sahabatnya dalam melindungi kalian.”
Penjelasan Hong-koan Hwesio itu sebenarnya cukup jelas, tapi kedua kakak beradik she Tong itu bahkan terlongong seperti orang kehilangan pegangan. Maklumlah, mereka baru saja terlempar dari sebuah dunia yang dirasa indah dan tenteram, ke sebuah dunia lain yang penuh kekerasan dimana bahaya mengancam dari segala sudut.
Mereka masih belum percaya sepenuhnya bahwa paman Ting yang baik hati itu ternyata hanya seorang munafik seperti yang dikatakan oleh Siau-lim-hong-ceng itu. Tapi semua kenyataan di depan mata memaksa mereka mau tidak mau harus waspada.
Kini mereka akan menuju ke selatan kembali. Tapi kemana? Mereka sudah tidak punya sanak keluarga atau kenalan seorangpun di daerah itu. Haruskah mereka menjadi gelandangan? Sesaat Tong Wi-hong dan adiknya menjadi kebingungan menghadapi perkembangan keadaan yang berkembang terlalu cepat itu.
Meskipun digelari si rahib sinting, sebenarnya Hong-koan Hwesio berhati baik. Jalan pikirannya pun tidak sesinting tingkah lakunya, bahkan tidak jarang ia berpikiran lebih cermat dari orang-orang yang mengaku waras. Ia menjadi iba ketika melihat kakak beradik itu menjadi kebingungan. Tetapi ia sendiripun belum dapat memberikan arah yang pasti, yang dia tahu hanyalah menjauhkan kedua anak yang masih polos itu sejauh-jauhnya dari Ting Ciau-kun, serigala berbulu domba itu.
Sementara itu, di dalam kebingungannya tiba-tiba Tong Wi-hong menemukan akal yang dianggapnya bagus. Katanya, “Pek-hu, bagaimana kalau kami berdua mengikuti pek-hu berkelana saja? Selain untuk belajar ilmu silat pek-hu yang tinggi, juga untuk menambah pengalaman dalam dunia persilatan.”
Dan sebelum Siau-lim-hong-ceng menyahut, Tong Wi-lian telah lebih dulu menyambutnya dengan sorakan gembira. Namun kakak beradik itu menjadi kecewa bukan main setelah melihat Hong-koan Hwesio menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata,
“Tidak bisa jadi, haruslah kalian ketahui bahwa musuh-musuhku sangat banyak, boleh dikatakan bahwa di segenap sudut negeri ini terdapat musuh-musuhku sebab sifatku yang gemar berkelahi. Jika kalian berdua mengikuti aku, maka keselamatan kalian pun ikut terancam, dan aku tidak akan membiarkan kalian ikut menyerempet-nyerempet bahaya bersama aku.”
Sebenarnya Hong-koan Hwesio sangat kasihan melihat kakak beradik yang kecewa itu, namun apa yang telah dikatakannya itu memang sebenarnya. Akhirnya rahib kumal itu menghiburnya, “Aku paham sekali akan hasrat hati kalian yang ingin mencari guru yang pandai dan mempelajari ilmu silat yang tinggi. Karena itu kuanjurkan kalian mencari guru di daerah selatan saja, sebab kebanyakan tokoh-tokoh lihai di daerah utara ini sudah menjadi kaki tangan Kaisar.”
“Dapatkah pek-hu menyebutkan ke mana kami harus menuju dan kepada siapa kami harus berguru?”
Sahut Hong-koan Hwesio, “Banyak sekali tokoh-tokoh di selatan yang pantas menjadi guru kalian. Pertama-tama kalian dapat mencari kakak seperguruanku, Hong-pek atau Hong-tay Hwesio, yang berdiam di kuil Siau-lim-si di Siong-san. Masih ada lagi Ketua kuil Giok-hi-koan di Bu-tong-san, yaitu Kim-hian Tojin, Liu Tay-liong di Kay-hong yang terkenal sebagai ahli menotok jalan darah nomor satu di dunia, atau Tiam-jong-lo-sia (si sesat tua dari tiam-jong-san) di Hun-lam. Tetapi kepada Tiam-jong-lo-sia ini kalian harus agak hati-hati, jangan sampai jika kalian berguru kepadanya lalu ketularan sifat-sifat gilanya.”
Tong Wi-hong dan adiknya mengangguk-anggukkan kepalanya dan mencatat nama-nama itu di dalam hati mereka. Sedangkan Hong-koan Hwesio bukan saja memberikan daftar nama-nama tokoh terkenal, tapi juga menyebutkan beberapa nama yang lebih baik dihindari daripada didekati. Antara lain adalah Lam-gak-su-koay (Empat Siluman dari Gunung Selatan) yang bersimaharajalela di Ou-lam.
Lalu Co-siang-hui-mo (Iblis Terbang di Padang Rumput) si dedengkot penjahat di Su-coan, Thi- jiau-tho-wan (Monyet Bungkuk Berkuku Besi) di Ho-lam dan sebagainya. Tokoh yang disebut terakhir ini, menurut Hong-koan Hwesio, bukan tokoh yang terlalu jahat tetapi juga bukan orang baik-baik. Setelah memberikan pesan-pesan seperlunya, rahib pengembara itupun lalu pergi meninggalkan kedua orang keponakan angkatnya itu.
Sayup-sayup masih terdengar suara nyanyiannya yang sumbang itu makin lama makin jauh sampai akhirnya tidak terdengar lagi. Sikap dan gerak-geriknya melambangkan kebebasan hidupnya, sebebas seekor burung yang terbang di udara. Tapi dibalik sikap bebasnya itu ia masih merasa dibebani sikap bertanggung-jawab untuk mengamankan dunia dari segala perbuatan busuk dan ketidak-adilan.
Tong Wi-hong dan adiknya pun merasa tidak ada lagi yang mereka tunggu di kuil kosong itu. Setelah membenahi diri, merekapun menaiki kuda mereka dan membawa bekal mereka untuk meninggalkan tempat itu menuju ke selatan. Mereka bagaikan dua ekor domba gemuk yang tersesat di padang luas dunia persilatan, dimana kelompok-kelompok serigala bertebaran di mana-mana. Tetapi kedua ekor domba gemuk itu punya tekad kuat dalam hati masing-masing bahwa mereka akan menjadikan diri mereka harimau, sehingga tidak lagi menjadi sekedar mangsa serigala.
* * * * * * *
“A-lian, kau kelihatannya lesu dan kurang bersemangat dalam melanjutkan perjalanan ini,” Tong Wi-hong menegur adiknya yang berada di sebelahnya. “Apakah kau merasa kurang enak badan?”
Gadis itu tidak menyahut. Hanya mukanya yang tertunduk seakan-akan sedang menghitung langkah-langkah kaki kuda tunggangannya. Sikap itu membuat akaknya jadi menduga-duga, apa gerangan yang telah terjadi atas diri adiknya? Tiba-tiba Tong Wi-hong berkata sambil tertawa lebar,
“Ah, alangkah bodohnya aku. Tapi sekarang aku tahu yang membuat kau tidak bersemangat meninggalkan Pak-khia!”
Kali ini Wi-lian mengangkat wajahnya memandang kakaknya. Dan terdengarlah sang kakak meneruskan ucapannya tadi, “A-lian, mengaku terus teranglah kepadaku, kau berat meninggalkan Ting Bun bukan?”
Seketika merah padamlah wajah si gadis she Tong itu, sebab isi hatinya dapat ditebak tepat oleh kakaknya. Tinjunya yang kecil itu segera terayun hendak memukul pundak kakaknya, namun Wi-hong sempat mengelakkannya sambil tertawa semakin keras.
“Nampaknya tebakanku tidak meleset,” kata Tong Wi-hong sambil mengendorkan lari kudanya.
Akhirnya Tong Wi-lian Cuma bisa menarik napas panjang sambil menundukkan kepalanya. Jauh di dasar hatinya, gadis itu memang sangat mengagumi Ting Bun. Dalam usia yang masih muda, Ting Bun telah menampakkan kepribadian yang begitu kuat mempesona, berwibawa, bertanggung jawab, jujur, dan tidak munafik. Tadinya Wi-lan menganggap perasaannya sendiri itu tidak lebih dari perasaan kagum dan hormat saja.
Tetapi setelah ia dan kakaknya berjarak puluhan li dari Pak-khia, mulai terasa bahwa perasaan yang berkembang di dalam hati mudanya itu bukan sekedar perasaan kagum dan hormat saja, tetapi jauh lebih indah dari pada itu. Tubuhnya meninggalkan Pak-khia, tetapi sebenarnya hati gadis itu telah tertambat di kota itu. Perasaan yang tengah dialaminya adalah perasaan yang paling indah, yang harus dialami oleh semua manusia.
Sedang Tong Wi-hong agaknya masih saja berniat mengganggu adiknya itu, “Aku lupa bahwa kau bukan anak kecil lagi, bahkan tahun ini usiamu sudah delapanbelas tahun lebih. Lagipula Ting Bun itu nampaknya juga... memperhatikan kepadamu....”
Wi-lian menjadi semakin tersipu, dengan gemas ia mengangkat cambuk kuda di tangannya untuk dipukulkan ke punggung kakaknya, tapi dapat dihindari oleh kakaknya. Wi-lian jadi semakin jengkel dan berseru, “A-hong, sudahlah, kenapa kau selalu mengolok aku? Bila ada kesempatan ingin kuhajar babak-belur pantatmu itu!”
Wi-hong tertawa keras, “Aduh galaknya menantu keluarga Ting ini!”
Gadis itu menjadi semakin gemas kepada kakaknya, tetapi sebenarnya jauh di dasar hatinya terselip juga sepercik rasa bahagia yang hangat. Ucapan kakaknya yang menyatakan bahwa sebenarnya Ting Bun juga menaruh perhatian kepadanya itu memang bukan ucapan ngawur, tapi kenyataan. Wi-lian sendiri juga merasakan hal itu. Hanya saja dia adalah seorang gadis, sehingga merasa malu untuk menampakkan perasaannya secara terbuka. Namun alangkah pahitnya bahwa kini ia harus berpisah sebelum sempat saling mengutarakan isi hati.
Merasa telah cukup menggoda adiknya, Wi-hong segera mendekatkan kembali kudanya dan berkata, “Baiklah, aku tidak akan mengolokmu lagi. Aku minta ampun padamu.”
Mau tidak mau Wi-lian tertawa melihat sikap kakaknya itu. Omelnya, “Dasar kau memang jahil, agaknya mulutmu gatal jika tidak menggodaku? Sedangkan di pundak kita masih terbeban beberapa kewajiban berat. Sakit hati ayah belum terbalas, lagipula ibu dan A-siang masih harus kita cari entah kemana. Bagaimana aku berani mendahulukan kepentingan pribadi dan menyampingkan kewajiban keluarga?”
Diingatkan akan kewjiban-kewajiban keluarga yang masih membebaninya, Tong Wi-hong tidak berani bergurau lagi. Demikianlah kakak beradik itu melanjutkan perjalanannya ke arah selatan. Karena mereka tidak pernah melarikan kudanya dengan cepat maka setelah menempuh perjalanan tiga hari, mereka baru mencapai kurang lebih 200 li dari Ibukota Kerajaan. Bahkan di tempat-tempat di mana ada pemandangan yang indah, kakak beradik itu sering berhenti untuk menikmati pemandangan atau untuk melatih ilmu silat mereka.
Hari keempat, mereka memasuki sebuah jalan yang sunyi dan yang terletak di pinggir sebuah hutan yang tidak begitu lebat. Tengah kedua kakak beradik itu berkuda dengan santai sambil bercakap-cakap, tiba-tiba dari arah belakang mereka terdengar derap seekor kuda yang dilarikan dengan kencangnya. Cepat Tong Wi-hong dan adiknya meminggirkan kuda mereka agar tidak tertabrak penunggang kuda itu.
Penunggang kuda itu ternyata adalah seorang lelaki yang bertubuh tegap dan bertampang kasar, di punggungnya tergendong sebatang golok besar. Ketika ia mendahului kedua kakak beradik she Tong itu, ia sengaja melambatkan kudanya dan matanya sempat melirik serta memperhatikan wajah kedua kakak beradik itu dengan seksama. Setelah merasa yakin, ia mempercepat kembali lari kudanya, dan sebentar saja sudah tidak terlihat bayangannya lagi.
Wi-hong dan Wi-lian adalah anak-anak muda yang hijau dalam pengalaman. Tingkah laku si lelaki penunggang kuda itu sama sekali tidak menimbulkan rasa curiga mereka, dianggapnya hal biasa sebab wajah Wi-lian memang cukup cantik untuk menarik perhatian kaum lelaki. Mereka tetap tenang saja dan melanjutkan perjalanan sambil bercakap-cakap.
Tetapi alangkah terkejutnya, ketika kuda mereka tiba-tiba meringkik dan roboh ke tanah, karena kaki binatang-binatang itu terjerat oleh seutas tali yang dipasang melintang di atas tanah. Rupanya tali itu memang sengaja dipasang untuk menjerat kuda yang lewat. Untunglah, biarpun Tong Wi-hong berdua tidak mengira akan kejadian itu, namun sebagai pemuda-pemudi yang terdidik ilmu silat sejak kecil, mereka dapat dengan tangkas melompat dari kudanya tanpa jatuh terbanting.
Namun muka mereka nampak pucat karena terkejutnya. Belum lagi tenang debaran jantung mereka, telah terdengar suara daun-daun tersibak dan rerumputan terinjak, lalu muncullah belasan lelaki bertubuh kekar dan bermuka garang yang langsung bersikap mengurung Tong W-hong dan adiknya. Diantara mereka, nampaklah si penunggang kuda yang tadi hampir menabrak Tong Wi-hong dan adiknya.
Jumlah para penghadang itu ada limabelas orang, semuanya nampak tangkas. Disimpulkan bahwa mereka adalah kawanan manusia yang mencari nafkah dengan senjata. Ada pula yang bertangan kosong, namun agaknya tidak kalah berbahayanya dengan kawan-kawannya yang bersenjata.
Melihat itu diam-diam Tong Wi-hong dan adiknya mengeluh di dalam hati. Ketika mereka dibawa dari rumah Ting Ciau-kun oleh Hong- koan Hwesio, pedang mereka telah tertinggal di rumah paman Ting, dan sampai sekarang mereka belum sempat mendapat gantinya! Menghadapi lima belas orang berandal tangguh itu tanpa pedang adalah pekerjaan yang cukup berat buat orang-orang yang berkepandaian setaraf dengan Wi-hong dan Wi-lian.
Salah seorang dari berandal-berandal itu segera bertanya kepada Tong Wi-hong dengan suaranya yang berat, “He, kau tentu yang bernama Tong Wi-hong? Dan gadis itu tentu yang bernama Wi-lian bukan?”
Wi-hong dan adiknya saling bertukar pandang dengan herannya karena ternyata orang-orang ini dapat mengenali nama-nama mereka. Diam-diam mereka mulai merasakan adanya gelagat kurang baik. Kemudian Wi-hong memberi hormat sambil balas bertanya, “Siapakah tuan-tuan ini? Ada keperluan apa dengan diri kami?”
Lelaki tadi tertawa pendek sambil memegang-megang kumisnya, “He-he, ditanya belum menjawab tapi malah balas bertanya. He, bocah dungu! Jawab dulu pertanyaanku tadi!"
Tong Wi-hong mengerutkan keningnya, dan hatinya mulai menjadi tidak senang melihat sikap orang yang sok jagoan itu. Tapi mengingat kekuatan mereka sendiri yang terbatas, terpaksa ia menyabarkan diri dan menekan kemarahannya. Katanya, “Kami memang benar Tong Wi-hong dan Tong Wi-lian dari An-yang-shia. Ada urusan apakah kalian mencari kami?”
Seorang berandal lainnya yang bersenjata kampak bertangkai panjang, segera mendengus, “Hah, benar-benar bernyali besar, begitu ditanya langsung mengaku. Tidak mengecewakan kalian sebagai putera-puteri Kiang-se-tay-hiap yang tersohor itu. He, anak muda yang berani, ketahuilah, bahwa kami sudah menyetorkan delapanbelas batok kepala ke hadapan si gemuk Cia To-bun, tetapi tidak sebutir batok kepala pun yang cocok sehingga upah yang dia janjikan pun belum kami terima. Tapi berdasarkan pengakuanmu tadi, agaknya kini kami tidak akan salah penggal lagi. Jadi terima kasih atas pengakuanmu.”
Hati Wi-hong dan Wi-lian bergejolak hebat mendengar ucapan berandal itu. ternyata para berandal itu bekerja demi upah yang dijanjikan oleh Cia To-bun untuk memburu dan membunuh sisa-sisa keluarga Tong. Agaknya Cia To-bun benar-benar menjalankan pedoman “membabat rumput seakar-akarnya”.
Sementara berandal berkumis itu telah berkata lagi, “Benar, kali ini orang she Cia itu pasti akan membayar upah kita, seratus tahil perak untuk tiap batok kepala. Setelah itu tinggallah kita mencari di mana isteri Tong Tian dan anak tertuanya yang benama Tong Wi-siang itu, dan setelah itu kita punya cukup banyak uang untuk berfoya-foya.”
Kemarahan telah meluap dalam diri Wi-hong dan adiknya setelah tahu bahwa berandal-berandal itu bekerja untuk Cia To-bun. Bentak Wi-lian, “Bagus! Jadi kalian ini adalah anjing-anjingnya si keparat itu?”
Berandal berkumis itu masih saja tertawa-tawa sambil memegang-megang kumisnya, sahutnya, “Begitulah, berhubung kantong kami sedang kosong, terpaksa akan kami pinjam kepala kalian untuk ditukarkan dengan uang si gendut she Cia itu. kami berjanji jika ada uang akan menyelenggarakan sembahyang sederhana untuk menghormati arwah kalian.”
Kawanan berandal itu serempak tertawa ketika mendengar kelakar kawannya yang berkumis itu. bahkan ada seorang berandal muda yang menimbrung kurang ajar, “Gadis anak Tong Tian ini boleh juga. Sebelum kita jual kepalanya, baiklah kita kerjakan dulu, sebab kurang enak kalau bermesraan dengan gadis tanpa kepala.”
Sekali lagi hutan itu bagaikan tergetar oleh suara tertawa para berandal itu. Sedang Wi-hong dan Wi-lian menjadi merah mukanya karena marahnya. Merekapun sudah menyadari bahwa sulit untuk meloloskan diri dari kepungan ke limabelas orang berandal bersenjata ini, namun mereka lebih suka bertempur mati-matian daripada menodai nama Keluarga Tong.
Mendadak Tong Wi-hong melompat ke arah si berandal muda yang berdiri tiga langkah dari tempatnya. Dengan sebuah pukulan dan tendangan kilat ia membuat si berandal muda itu roboh terkapar sambil memuntahkan darah. Rupanya Wi-hong ingin membuat kawanan berandal yang sedang mabuk kegirangan itu untuk mengurangi jumlahnya, dan ternyata ia berhasil.
Wi-lian cukup cerdas untuk menangkap maksud kakaknya, diapun segera menirunya dengan menyerang berandal terdekat secara mendadak. Tapi gebrakan pertama dari kakaknya tadi telah membuat para berandal bersiaga, sehingga serangan mendadak Wi-lian itu kurang berhasil.
Berandal yang bersenjata kampak bergagang panjang itu agaknya merupakan pimpinan dari kelompok berandal itu. Melihat kakak beradik itu mulai bergerak, ia segera memerintahkan kepada anak buahnya, “Bunuh yang lelaki! Usahakan tangkap hidup-hidup yang perempuan!”
Tetapi putera-puteri Kiang-se-tay-hiap itu justru lebih dahulu menerjang lawan-lawan mereka dengan kemarahan meluap. Dalam waktu sekejap saja terjadilah perkelahian sengit dua lawan empatbelas di tempat yang sunyi itu. Para penjahat itu ternyata bukan manusia-manusia lemah, mereka cukup punya bekal dalam menjalankan kejahatan-kejahatan mereka. Mereka juga sudah menang pengalaman dan mampu bekerja sama dengan rapi dalam menghadapi kakak beradik she Tong yang mengamuk seperti harimau terluka.
Sebentar saja Wi-hong dan Wi-lian mulai merasakan tekanan berat dari lawan-lawan mereka, apalagi mereka berdua cuma bersenjata cambuk kuda, sedang lawan-lawan mereka bersenjata tombak panjang, toya, golok, dan sebagainya. Apalagi si pemimpin berandal yang bersenjata kampak bergagang panjang itu benar-benar tidak dapat dipandang ringan, dialah yang ilmu silatnya paling tangguh.
Dalam keadaan yang semakin gawat buat dirinya dan adiknya itu, sekonyong-konyong Tong Wi-hong ingat ajaran ayahnya bahwa “membekuk ular harus menangkap kepalanya lebih dulu”. Maka diam-diam Tong Wi-hong mulai berusaha bergeser mendekati si pemimpin berandal, dan mempersiapkan tindakan-tindakan kilat untuk menjalankan rencananya.
Suatu ketika Tong Wi-hong merasa sudah tiba waktunya. Dengan disertai bentakan menggeledek ia berhasil merobohkan salah seorang berandal dengan tendangan ke bawah perutnya sehingga si berandal roboh dengan perut mulas. Setelah itu sambil memutar cambuk kudanya secepat angin puyuh, Tong Wi-hong menerjang ke arah pemimpin berandal.
Si pemimpin berandal itupun bukan manusia keroco yang tak berguna, ia membabatkan kampaknya ke kepala Wi-hong. Wi-hong terpaksa menjatuhkan diri dan bergulingan untuk menghindarkan diri dari sambaran maut itu, dengan demikian, gagallah maksud Tong Wi-hong untuk menjalankan tipu “membekuk ular menangkap kepalanya dulu" itu. Bahkan kini si pemimpin berandal yang cukup berpengalaman itu sudah dapat menebak maksudnya.
Baru saja Tong Wi-hong melompat bangun, dua orang berandal yang masing-masing bersenjata golok dan tombak panjang telah menyergap serempak. Dengan sabetan cambuknya ke samping, Tong Wi-hong berhasil melibat dan membelokkan arah bacokan golok lawan. Sedang kaki kirinya melakukukan gerakan kaki Pay-lian-ka (Tendangan Teratai Tertembus Angin) dan berhasil pula menendang tombak lawan sehingga meleset jauh dari sasarannya.
Untuk sementara dia masih bisa membela diri, tetapi Wi-hong sadar bahwa keadaannya yang seperti itu tidak dapat dipertahankan terus. Kekalahan baginya hanya soal waktu. Dia dan adiknya ibarat dua ekor binatang buruan yang sudah masuk dalam perangkap, biarpun sudah meronta bagaimanapun pasti akan mati di ujung senjata lawan-lawan mereka, kecuali datangnya suatu keajaiban.
Keadaan Wi-lian juga tidak kalah payah dari kakaknya. Sebenarnya gadis itu punya niat untuk mencapai kudanya dan naik ke atas punggung kuda. Dia berharap akan lebih mendapat keuntungan jika berkelahi di atas kuda. Dan dia memang pernah berhasil hampir menduduki punggung kuda, tapi seorang lawan berhasil menarik kakinya sehingga terpaksa ia berkelahi di atas tanah kembali.
Satu-satunya keuntungan Tong Wi-lian dibandingkan dengan kakaknya hanyalah bahwa berandal-berandal itu agaknya tidak ingin melukai kulit gadis itu. mereka ingin menjadikan gadis itu sebagai pelampiasan hawa nafsu lebih dulu, sebelum memotong batok kepalanya dan membawanya kepada Cia Tong-bun. Mereka menggunakan tipu hanya mengurung untuk menghabiskan tenaga Wi-lian, dan jika sudah kelelahan barulah akan ditangkap hidup-hidup.
Tiba-tiba si pemimpin berandal yang bersenjata kampak panjang itu berteriak kepada anak buahnya yang tengah mengurung Wi-lian, “He, pusatkan kekuatan kalian untuk menghabisi si bocah lelaki yang bandel itu. Anak gadis yang mulus ini biarlah kutangani sendiri!”
Sebenarnya berandal-berandal itu lebih senang berkelahi melawan Tong Wi-lian yang cantik, tapi mereka pun tidak berani menentang perintah pemimpinnya. Beberapa orang berandal yang mengepung Wi-lian segera berlompatan meninggalkan lawanny dan beralih mengepung Wi- hong yang sedang kepayahan. Meskipun dalam hati kawanan berandal itu memaki pemimpin mereka yang mau enaknya sendiri saja.
Kawanan berandal itu memang hanya menguasai ilmu silat kasaran saja, namun kekuatan tubuh mereka rata-rata justru cukup tangguh, begitu pula kekasaran dan kelicikan mereka. Mereka adalah petualang-petualang yang kenyang dengan pengalaman tempur, dan sanggup berkelahi sehari suntuk tanpa beristirahat. Sebaliknya, meskipun Tong Wi-hong memiliki ilmu silat yang lebih baik, tapi dalam masalah ketahanan tubuh dan pengalaman justru tidak dapat menandingi berandal-berandal itu.
Sementara itu si pemimpin berandal telah melemparkan kampaknya dan menempur W-lian dengan tangan kosong. Gerakannya mantap dan kuat, dan nampaknya dia cukup mahir dalam ilmu gulat Mongol. Tingkat kepandaiannya pun mengungguli Wi-lian. Bukan itu saja, pemimpin berandal itu ternyata cukup kuat kulitnya, sehingga cambuk Wi-lian yang berkali-kali menghantam tubuhnya itu seakan-akan dianggapnya hanya gigitan nyamuk yang tidak berarti.
Malahan beberapa kali gadis itu hampir saja terpegang oleh tangan yang kekar dan berbulu lebat itu. makin lama makin terdesaklah Wi-lian. Dalam keadaan genting itu, sadarlah Wi-lian bahwa dia harus memilih sasaran dalam mencambuk lawan, sebab kulit lawan ternyata cukup tebal dan liat. Maka selanjutnya gadis itu mulai mengarahkan ayunan-ayunan cambuknya ke bagian-bagian lemah seperti mata, tenggorokan, dan bahkan ke bagian terlarang seorang lelaki.
Meskipun hal itu dilakukan dengan muka merah karena malu sendiri, tapi akhirnya gadis itu menekan jauh-jauh semua perasaannya. Demi kehormatan yang dipertahankannya ia tak segan-segan berbuat apa saja. Siasatnya itu ternyata cukup ampuh juga, sebab kini si pemimpin berandal tidak berani lagi mengabaikan cambukan-cambukan gadis itu, dan desakannya pun berkurang tidak segarang tadinya.
Namun kemarahannya justru semakin meningkat, geramnya, “Bagus, gadis binal, sekarang kau boleh melihat kelihaianku!”
Begitu selesai dengan kalimatnya, ia merapat maju dan kedua tangannya secara bergantian menangkap dan mencengkeram secara gencar dengan ilmu gulat Mongol. Didesak semacam itu, cambuk Wi-lian jadi agak kehilangan daya gunanya. Setiap kali Wi-lian mencoba mengatur jarak dengan lawannya, tapi lawannya yang lebih berpengalaman itu malah berhasil mendesaknya bagaikan bayangannya. Meskipun bertubuh besar, ternyata pemimpin berandal itu lebih tangkas dari Wi-lian.
Napas Tong Wi-lian mulai tersengal-sengal. Bukan hanya karena kelelahan, tapi juga karena perasaan ngeri mulai merayapi hatinya, membayangkan penghinaan yang bakal diterimanya jika ia jatuh ke tangan para berandal itu. Tiba-tiba matanya mulai berkunang-kunang dan tenaganyapun semakin lemah. Di saat itulah kedua belah tangan si pemimpin berandal itu bergerak serempak, dan kali ini tidak memberi kesempatan kepada korbannya untuk menghindar lagi.
Dengan mudah Tong Wi-lian segera dapat diringkusnya dan langsung diseret masuk ke dalam hutan. Bahkan tidak diperdulikannya anak buahnya yang masih bekerja keras untuk menundukkan Wi-hong. Malahan si pemimpin berandal itu sempat berteriak sambil tertawa,
“Kalian bereskan dulu bocah lelaki itu. nanti kalian pun akan kebagian!”
Karena Tong Wi-lian masih juga meronta mencoba melepaskan diri, maka dengan jengkel si pemimpin berandal lalu memanggul tubuh gadis itu secara paksa dan dibawa menghilang ke dalam hutan. Tong Wi-hong melihat semua kejadian itu tapi tidak dapat berbuat apa-apa, darahnya mendidih hebat. Ia berteriak-teriak kalap dan mengamuk hendak menjebol kepungan untuk merebut kembali adiknya, tapi kepungan para berandal itu sangat ketat.
Biarpun ada beberapa berandal yang roboh, tapi hanya dengan sehelai cambuk kuda ditangannya, mustahillah bagi Tong Wi-hong untuk bisa lolos dari kawanan berandal yang bersenjata itu. Karena ia semakin gugup, maka tubuh Wi-hong kembali terkena senjata lawan dan menimbulkan beberapa luka baru.
Akhirnya pemuda yang biasanya lemah lembut itu menjadi nekad dan menjadi sangat kasar, teriaknya dengan amarah meluap, “Kawanan bajingan tengik! Hari ini biarpun aku mati di tangan kalian, tapi beberapa orang diantara kalin pun harus ikut mampus menemani aku!”
Oleh semangatnya itu maka kekuatannya yang hampir habis itu seolah bertambah kembali. Dengan menggeram seperti macan luka dan menyerang membabi-buta, kembali dua orang berandal berhasil ditendangnya roboh. Tapi ia tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa akhirnya tenaganya pun mulai susut dengan cepat, dan melulu semangat yang berkobar saja tidak banyak menolongnya. Langkahnya mulai terhuyung-huyung dan sabetan cambuknya tidak terarah lagi.
Kawanan berandal itu menjadi kegirangan, mereka berteriak-teriak, “Kepung terus tikus ini! Tenaganya sudah hampir habis dan setelah itu barulah kita sembelih!”
Seorang berandal yang bersenjata ce-bi-kun secara telak berhasil menghantam punggung Tong Wi-hong, sehingga anak muda yang gagah perkasa itu kini tersungkur jatuh ke depan sambil menyemburkan darah segar dari mulutnya. Ia mendapat luka dalam yang tidak ringan.
Tapi putera Kiang-se-tay-hiap itu telah digembleng dengan watak kesatria sekaj kecil, ia pantang menyerah sebelum ajal tiba. Dengan bergulingan kesana kemari dia masih dapat menghindari senjata-senjata lawan-lawannya yang bertubi-tubi menghujani tubuhnya. Bahkan suatu kesempatan ia berhasil melompat berdiri meskipun dengan tubuh lemas dan mata berkunang-kunang.
Sambil mengayun-ayunkan cambuk kudanya, ia berteriak parau, “Kawanan anjing gila, hayo maju ke sini dan mengadu jiwa dengan aku kalau berani!”
Seorang berandal yang bersenjata pedang segera menyambut seruan itu dengan menyeringai dingin dan mengejek, “Tikus kecil ini sudah dekat ajal tetapi masih berani membuka mulut besar. Biar pedangku mencicipi darahnya!”
Begitu mulutnya tertutup begitu pula pedangnya berkelebat ke arah leher Tong Wi-hong dengan derasnya. Wi-hong sudah berusaha mati-matian mengelakkan pedang itu, tapi seluruh tubuhnya sudah begitu lemah dan tidak dapat digerakkan sedikitpun juga. Akhirnya ia cuma bisa menggertak gigi dan pasrah nasib, sementara matanya terpejam menunggu batang lehernya terpenggal. Bahkan sebelum mata pedang menyentuh lehernya, Wi-hong sudah tak sadarkan diri, bukan karena ketakutan tapi karena benar-benar telah kehabisan tenaga.
Dalam pada itu, Tong Wi-lian yang dibawa oleh si pemimpin berandal ke dalam hutan itu masih saja berusaha keras untuk melepaskan diri. Gadis itu terus meronta-ronta, menendang dan memukul, bahkan tidak segan-segan untuk menggigit pula. Tetapi sepasang tangan yang menawannya itu tetap kokoh kuat bagaikan terbuat dari besi. Si pemimpin berandal bahkan tertawa-tawa kegirangan karena merasakan gesekan-gesekan tubuh dengan gadis rampasannya ketika gadis itu meronta-ronta, sementara langkahnya tidak pernah berhenti.
“Sabarlah, sebentar lagi kita akan di tempat yang aman dan kita akan bersama-sama menikmati sorga dunia,” ejeknya sambil tertawa terkekeh-kekeh.
Semakin ngerilah gadis itu mendengar ucapan pemimpin berandal itu. di pelupuk matanya sudah terbayang suatu penghinaan yang sangat keji, lebih keji dari kematian buat seorang perempuan terhormat. Diam-diam timbul tekad Wi-lian untuk menggigit putus lidahnya sendiri agar mati saja daripada mengalami aib seumur hidupnya. Namun di saat nasib buruk sudah hampir pasti dialami oleh gadis itu, dan si pemimpin berandal pun sudah hampir pasti pula akan mengalami “kemenangan”nya, datanglah seorang dewa penolong.
Saat itu si pemimpin berandal sudah tiba di tengah hutan, di suatu tempat yang dianggapnya cukup nyaman untuk melampiaskan nafsunya sebelum memenggal kepala gadis itu dan kemudian ditukarnya dengan uang seratus tahil perak, sekonyong-konyong di tempat itu berkumandanglah suara pujian merdu kepada Sang Buddha,
“Omitohud!” Suara itu tidak terlalu keras, namun jelas mengandung suatu kekuatan yang menggetarkan hati siapapun. Ketenangannya seperti ketenangan sebuah telaga yang dalam, kewibawaannya seberat gunung Tay-san.
Si pemimpin berandal yang sudah siap melucuti pakaian korbannya itu jadi terkejut bukan main dan menyapukan pandang matanya ke sekeliling tempat itu. Tiba-tiba dilihatnya sesosok bayangan putih berkelebat dengan kecepatan yang mengaburkan mata. Lalu di tempat itu muncullah seorang rahib tua berjubah putih, berwajah ramah penuh kedamaian dengan sinar mata yang lembut. Jubah dan jenggotnya yang juga berwarna putiih melambai-lambai, menambah perbawanya sehingga mirip seorang dewa dalam dongeng kuno.
Pemimpin berandal yang merasa keinginannya terganggu itu menjadi murka bukan main. Bentaknya kasar, “Bangsat gundul! Rupanya kau sudah bosan hidup sehingga berani mengganggu kesenanganku? Sebutkan namamu!”
Si rahib itu ternyata tenang-tenang saja menghadapi sikap kasar si pemimpin berandal, dengan suara tetap lembut ia memperkenalkan dirinya, “Aku adalah Hong-tay Hwesio dari Siong-san.”
Buat kaum persilatan yang berpengetahuan luas dan sering bergaul antara sesama kaum persilatan, nama itu tentu akan mengejutkan, sebab Hong-tay Hwesio adalah tokoh sakti dari kuil Siau-lim-si yang menduduki urutan kedua dalam deretan nama “Sepuluh Tokoh Maha Sakti di Jaman Itu”.
Tapi si pemimpin berandal itu ibarat katak di dalam sumur, pengetahuannya tentang dunia persilatan sangat terbatas sehingga nama Hong-tay Hwesio justru tidak menimbulkan kesan apapun. Sikapnya tetap kasar dan takabur, geramnya, “He, keledai gundul Hong-tay, tempatmu bukan di sini tapi di kelenteng, bersembahyang serta membaca kitab suci, buat apa kau berkeliaran di tempat ini dan mengganggu kesenangan orang lain?”
Rahib itu menyahut dengan tetap ramah, “Jika saat ini aku berada di kelenteng, lalu siapa yang mencegah perbuatan jahatmu? Apa artinya aku dapat memahami seluruh kitab suci tetapi seorang sesamaku aku biarkan saja mengalami penghinaan dan dihancurkan seluruh masa depannya?”
“Kurang ajar! Jadi dengan hadirnya kau sekarang ini kau pikir kau mampu menyelamatkan gadis ini dari tanganku?” teriak pemimpin berandal itu dengan amarah meluap. Lalu dengan sekuat tenaga ia ayunkan kakinya untuk menendang ulu hati si rahib tua itu.
Dengan tenang si rahib tua mengangkat tangannya ke depan seperti orang memberi hormat sambil menggumamkan pujian, “Omitohud.”
Dan si pemimpin berandal tiba-tiba merasakan bahwa ada segulung tenaga tidak terlihat yang mendampar ke arahnya dengan kuatnya. Bukan saja tendangannya meleset dari sasaran, bahkan tubuhnya pun terdorong beberapa langkah ke belakang dan jatuh terkapar.
Baru kini tertampil perasaan kaget pada wajah si pemimpin berandal. Diam-diam dia mulai merasa keder melihat rahib tua itu demikian lihai. Tetapi dia masih belum jera, kini ia menghunus sebatang pisau belati yang disembunyikan di bajunya dan bangkit kembali. Bentaknya, “Kau memang hebat keledai gundul, tetapi kini jangan salahkan aku kalau kukirim nyawa bangkotanmu itu ke neraka!”
Pemimpin berandal itu memang cukup tangkas, gerakannya cepat seperti seekor harimau menerjang mangsanya, dan pisau belati ditangannya itu bagaikan kuku-kuku harimau yang siap merobek-robek tubuh lawan.
Namun rahib tua itu tetap berdiri di tempatnya dengan tenang dan santai, wajahnya tetap penuh welas asih. Meskipun pemimpin berandal itu telah melakukan serangan serangan yang berusaha menghabisi nyawanya tapi si rahib itu tidak kelihatan marah atau dendam. Seenaknya saja ia mengebaskan lengan jubahnya dan dengan tepat berhasil membelit pisau lawan, lalu dengan kebasan ringan ia berhasil membuat lawannya jungkir-balik.
Pemimpin berandal yang begitu garang itu ternyata tidak lebih hebat dari seorang anak kecil umur tiga tahun jika dihadapkan dengan tokoh nomor dua di Tiong-goan itu. Kini habislah nyali si pemimpin berandal itu. Jatuhnya kali ini cukup keras dan pinggangnya menimpa sepotong akar yang menonjol dari tanah. Ia tidak dapat segera bangkit kembali karena sakitnya. Dengan tertatih-tatih akhirnya ia dapat berpegangan kepada pepohonan di sekitarnya dan berdiri perlahan-lahan.
Di dalam hatinya ia merasa malu, marah, dan penasaran. Tetapi dia insyaf bahwa berlatih sepuluh tahun lagi pun belum tentu dapat menandingi rahib itu. Akhirnya ia menerima kenyataan itu dan dengan terbungkuk-bungkuk sambil memegangi pinggangnya yang sakit ia melangkah pergi dari tempat itu.
Sebelum ia melangkah terlalu jauh, masih terdengar suara rahib Hong-tay yang bernada menasehati sekaligus mengancam, “Aku berharap agar anda bersedia memikirkan kembali ke jalan yang benar. Jika anda masih saja melakukan kejahatan dan mengganggu ketenteraman sesama manusia, maka apa boleh buat, terpaksa anda akan merepotkan murid-murid Siau-lim-pay kami yang tersebar di mana-mana.”
Pemimpin penjahat itu nampak agak pucat mukanya ketika mendengar perkataan Rahib Hong-tay itu. Meskipun mulutnya tidak menyahut, tapi ia mengerti bahwa ancaman itu bukan main-main. Dengan terpincang-pincang ia meneruskan langkahnya dan sesaat kemudian ia sudah tidak terlihat lagi di tempat itu.
Tong Wi-lian menarik napas lega setelah melihat perginya pemimpin berandal itu, tidak lupa ia mengucapkan terima kasih kepada rahib tua yang telah menyelamatkannya dari aib hebat itu. Rahib tua itu menjawab ucapan terima kasihnya dengan suaranya yang berwibawa tapi lembut,
“Sudahlah, nona, berterima kasihlah kepadabThian yang selalu melindungi orang baik.”
Sementara itu, mendadak Tong Wi-lian teringat kepada kakaknya yang saat itu tentu masih menyabung nyawa di luar hutan sana. Katanya kepada rahib Hong-tay, “Tay-su (bapak pendeta), aku telah menerima pertolonganmu yang maha besar, tetapi dapatkah aku minta tolong sekali lagi kepada Tay-su?”
“Katakan saja. Jika aku mempunyai kemampuan untuk melakukannya tentu aku tidak akan menolaknya,” sahut rahib itu.
Dengan singkat segera Tong Wi-lian mengatakan tentang kakaknya yang masih terancam jiwanya oleh sekawanan berandal di luar hutan itu. Mendengar hal itu, Rahib Hong-tay langsung berkata, “Kalau begitu kita tidak boleh terlambat menolongnya. Nona, marilah tunjukkan di mana kakakmu sedang terancam bahaya!”
Lalu rahib itu mengulurkan tangannya dan berkata, “Kita harus cepat, karena itu peganglah tanganku supaya aku dapat menggunakan ilmu meringankan tubuhku.”
Tong Wi-lian tahu bahwa rahib itu berhati suci bersih dan bukan seorang munafik, lagi pula usianya cukup pantas untuk menjadi kakeknya, maka tanpa malu-malu lagi ia memegang tangan rahib itu. begitu kedua telapak tangan saling genggam, tiba-tiba Wi-lian merasa kakinya terangkat dari tanah dan tubuhnya melayang ke depan secepat kilat. Ternyata rahib itu telah menariknya dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh supaya cepat sampai di tujuan.
Gadis itu merasa betapa pepohonan di kiri kanannya seolah-olah terhanyut ke belakang dengan cepatnya. Dan ketika ia melirik ke arah sepasang kaki rahib tua itu, semakin hebatlah kekaguman gadis itu. Ternyata sepasang kaki Hong-tay Hwesio bagaikan tidak menginjak tanah karena gerakannya yang terlalu cepat. Bahkan berlari di tengah hutan yang tidak rata dan penuh pepohonan itu ternyata si rahib dapat membawa Wi-lian dengan leluasa seperti melalui tanah lapang saja.
Ginkang (Ilmu Meringankan Tubuh) sehebat itu ternyata Wi-lian belum pernah menyaksikannya. Bahkan Wi-lian menaksir bahwa kepandaian Hong-tay Hwesio ini beberapa tingkat di atas Siau-lim-hong-ceng ataupun Soat-san-kiam-sian yang juga tergolong tokoh-tokoh sakti jaman itu. Sambil membiarkan tubuhnya diseret oleh rahib itu, diam-diam Tong Wi-lian berpikir,
“Pantas sekali orang-orang dunia persilatan di Tiong-goan menjuluki kuil Siau-lim-si di Siong-san sebagai persembunyiannya naga dan harimau. Cukup Hong-tay Hwesio dan Hong-koan Hwesio saja sudah merupakan dua buah tiang yang maha kokoh untuk menunjang keangkeran Siau-lim-pay. Apalagi di dalam kuil itu tentu masih ada tokoh sakti lainnya yang seangkatan dengan mereka. Belum terhitung puluhan tokoh-tokoh angkatan muda mereka yang tentu merupakan pendekar-pendekar tangguh pula.”
Lalu gadis itu mencoba membuat perbandingan antara Siau-lim-pay dan Soat-san-pay. Maka secara jujur ia harus mengakui bahwa pengaruh Soat-san-pay masih tidak sehebat Siau-lim-pay meskipun Soat-san-pay juga merupakan perguruan besar di daerah barat. Ini disebabkan oleh karena Siau-lim-pay merupakan aliran silat yang ratusan tahun lebih tua dibandingkan Soat-san-pay.
Selain itu, tokoh-tokoh Soat-san-pay kebanyakan berdiam jauh di wilayah barat dan jarang menampakkan diri di dunia persilatan Tiong-goan sehingga nama mereka kurang dikenal orang. Ini berbeda dengan tokoh-tokoh Siau-lim-pay yang banyak berkecimpung dalam dunia persilatan dalam menegakkan kebenaran.
Dalam pada itu, tak terasa tibalah mereka di pinggir hutan di tempat terjadinya pertempuran tadi. Tetapi pertempuran telah selesai dan tempat itu telah menjadi sunyi kembali seperti semula. Yag ada hanyalah mayat para berandal yang bergelimpangan di sana-sini, sedang mayat Tong Wi-hong ternyata tidak ada diantara mayat-mayat itu!
Hal itu membuat hati Wi-lian sedikit lega, tapi timbul kegelisahan baru kalau memikirkan entah bagaimana nasib kakaknya. Ketika Wi-lian mencoba menghitung jumlah mayat-mayat itu, semuanya berjumlah empatbelas. Jadi gerombolan yang menghadangnya itu telah tertumpas habis kecuali si pemimpin berandal yang diampuni oleh Hong-tay Hwesio tadi.
Sedangkan Rahib Hong-tay justru menampakkan wajah sedih melihat mayat bergelimpangan sebanyak itu. Ia menarik nafas beberapa kali dan bergumam dengan suara rendah, “Rupanya di sinilah kakakmu tadi bertempur. Meskipun aku datang terlambat tapi agaknya kakakmu yang gagah perkasa itu telah menolong dirinya sendiri dengan menumpas semua musuh-musuhnya tanpa ampun. Omitohud! Benar-benar ganas.”
Dalam suara rahib tua itu terkandung nada penyesalan dan kesedihan, rupanya paderi itu bersedih kenapa manusia masih saja demikian buas dan saling bunuh tanpa kenal ampun? Bahkan ada nada menyalahkan Tong wi-lian yang memiliki kakak sekejam itu.
Cepat Tong Wi-lian menggelengkan kepala sambil membantah “Pasti bukan kakakku yang membunuh mereka. Aku berani bersumpah disambar petir pasti ini bukan perbuatan kakakku. Kepandaian kakakku tidak sehebat ini, ia hanya unggul sedikit dari padaku, dan dengan dasar kepandaiannya itu mustahil ia mampu membunuh empatbelas orang pembunuh bayaran yang rata-rata berkepandaian cukup tangguh itu. Bahkan ketika akau dibawa oleh pemimpin berandal tadi masuk ke dalam hutan, kakakku sudah dalam keadaan terluka dan kelelahan, hampir tidak bisa melawan sama sekali, sedang musuh-musuhnya masih dalam keadan utuh. Kakakku tidak mampu membunuh seorang lawanpun sebab ia cuma bersenjata sehelai cambuk kuda.”
Kemudian rahib Hong-tay berjongkok untuk memeriksa mayat-mayat itu, alisnya yang putih seperti kapas nampak berkerut-kerut. Dia kemudian bergumam, “Aku mempercayai ucapan nona. Memang bukan kakakmu yang membunuh berandal-berandal ini. Agaknya aku dapat menebak siapa orang itu. Rupanya setelah membunuh orang-orang ini, ia lalu membawa pergi kakakmu.”
Tong Wi-lian menjadi sangat lega karena ucapannya dipercaya oleh rahib sakti itu. Tak terasa ia berdiri di belakang rahib itu dan ikut memeriksa mayat-mayat itu. Semetara Rahib Hong-tay berkata lagi,
“Memang ada beberapa luka-luka kena cambukan, tetapi luka-luka itu hanya luka-luka kulit dan sama sekali tidak mematikan. Yang mematikan adalah luka yang membelah dada mereka. Luka itu bukan disebabkan oleh pedang atau golok, melainkan oleh jenis senjata yang lebih ganas lagi yang disebut Hau-thau-kau (Kaitan Kepala Harimau). Pedang dan golok hanya membelah kulit dan daging, tapi Hau-thau-kau orang itu dapat merobek-robek sampai ke bagian dalam tubuh lawan. Itulah yang mematikan berandal-berandal ini.”
Terdorong oleh rasa keingintahuannya, Tong Wi-lian lalu bertanya kepada rahib tua itu, “Tadi Tay-su mengatakan bahwa Tay-su mengetahui siapa orangnya yang membunuh penjahat-penjahat ini. Dapatkah Tay-su memberi tahukan kepadaku supaya aku dapat mencarinya dan menanyakan perihal kakakku kepadanya?”
Teringat kepada orang yang bersenjata Hau-thau-kau itu, berkerutlah alis Hong-tay Hwesio menandakan ketidak-senangan hatinya. Orang itu sebenarnya adalah tergolong tokoh golongan lurus, bahkan dia adalah pemimpin dari sebuah piau-hang (Perusahaan Pengawalan) yang cukup terkenal.
Namun yang menimbulkan ketidak-senangan Hong-tay Hwesio adalah sikapnya yang terlalu keras dalam menghadapi golongan hitam. Orang itu tidak pernah mengampuni penjahat-penjahat yang menjadi lawannya, meskipun lawannya sudah tunduk dan menyatakan bertobat. Ia bersemboyan “sekali penjahat tetap penjahat”, biar diampuni juga kelak akan berbuat jahat lagi.
Maka kaum penjahat yang kepergok orang ini hanya ada dua jalan, yaitu membunuh atau terbunuh. Karena rahib Hong-tay berwatak welas asih dan pengampun, maka ia merasa tidak cocok dengan sifat-sifat ganas orang ini, dan karena itu pulalah ia segan menyebutkan namanya di hadapan Tong Wi-lian.
Sedangkan Wi-lian terus mendesaknya, “Luka-luka di tubuh berandal-berandal ini cukup dalam namun lurus dan panjang. Jelas pembunuhnya adalah orang yang mampu mengerakkan Hau-thau-kaunya dengan kekuatan besar dan kecepatan yang tinggi. Orang berkepandaian yang setaraf ini tentu tidak banyak di dunia persilatan, tentu tay-su mengenalnya pula.”
Keengganan Rahib Hong-tay menyebutkan orang itu adalah karena mengkhawatirkan Wi-lian yang masih lugu itu akan menemui orang itu, berguru kepada orang itu dan kemudian ketularan sifat-sifat keras dari orang itu. hal itu tidak dikehendaki oleh rahib yang welas asih itu. Karena itu terpaksa ia agak berbohong dalam menjawab desakan Wi-lian,
“Omitohud, setiap kali aku teringat kepada orang itu, yang terbayang di benakku hanyalah muncratnya darah dan jerit kematian. Aku memang mengenal orang itu dan pernah bertemu dengannya, tetapi aku tidak tahu siapa nama aslinya dan dimana tempat tinggalnya. Jadi maaf, aku tidak bisa memberi keterangan yang jelas kepada nona.”
Sambil mengucapkan kata-kata itu, diam-diam Hong-tay Hwesio memohon ampun kepada Sang Buddha sebab telah melanggar pantangan berbohong. Tetapi rahib Hong-tay berpendapat bahwa “kebohongan yang menyelamatkan adalah lebih baik daripada kejujuran yang menjerumuskan”.
Tong Wi-lian menjadi sangat kecewa karena tidak berhasil mendapatkan keterangan yang diinginkan. Namun hatinya tidak begitu cemas lagi memikirkan kakaknya, sebab agaknya kakaknya telah diselamatkan oleh seseorang yang berkepandaian tinggi. Bahkan ada kemungkinan besar sang kakak akan berguru kepada orang itu.
Begitu pikirannya melayang ke persoalan “berguru”, tiba-tiba terbukalah pikiran gadis itu. Kini di hadapannya tengah hadir seorang rahib yang kesaktiannya seperti dewa, bahkan terhitung kakak seperguruan dari uwak angkatnya Hong-koan Hwesio, kenapa kesempatan ini tidak dimanfaatkan untuk memohon menjadi muridnya?
Karena itu alangkah kagetnya Rahib Hong-tay ketika tiba-tiba gadis she Tong itu tiba-tiba berlutut menyembah kepadanya dan berkata dengan nada menghibakan hati,
“Tay-su, kini setelah berpisah dengan kakakku maka aku benar-benar sendirian di dunia ini. Ayahku telah tiada, sedang ibuku dan kedua orang kakakku tidak kuketahui di mana beradanya. Aku seorang gadis lemah, maka mohon belas kasihan tay-su untuk menerima aku sebagai murid dan mengajarkan ilmu silat kepadaku...”
Selanjutnya;